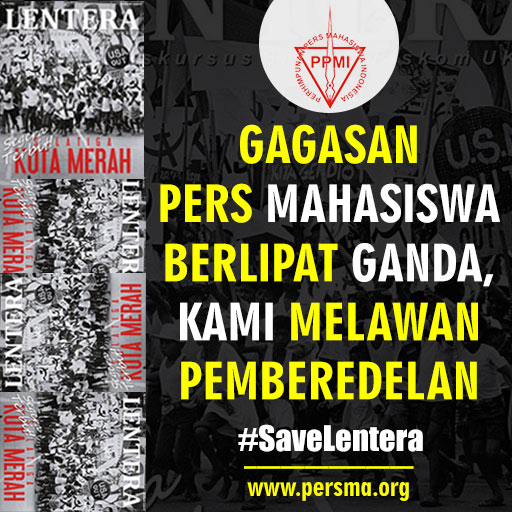Militer selalu beroperasi dengan mumpuni asal tuannya beri perintah. Munir Said Thalib menolak kekerasan militerisme demi pengamanan. Kesepakatan menuju demokratisasi tanpa adanya kesadaran menolak bentuk dan manifestasi militerisme adalah upaya mustahil. Namun, sejarah yang berhubungan dengan miiter justru sebaliknya. Militerisme digunakan sebagai mesin perluasan kewenangan sosio-politik sehingga kekuatan militer akibatkan laku “kekerasan absah” pada warganya.
Penghancuran cita-cita reformasi adalah mimpi buruk, yang terjadi akibat membesarnya kekuatan militer, tanpa pernah kita bayangkan sejak terpilihnya Prabowo sebagai Presiden. “Saya prajurit yang ksatria,” berikut omon-omon pernyataan diri patriotik khas Prabowo hanya bikin kita jengah. Padahal yang kita tahu dia itu gelagatnya tantrum, benci kegaduhan sipil karena ia tak suka protes dan penolakan.
Inilah mengapa corak pemerintahan Prabowo cenderung bungkam kritik warga terlebih setelah ia sukses kuasai istana tua di Jalan Merdeka Barat, seratus meter di depan berdirinya korban pelanggaran HAM berat: aksi kamisan.
***
Prabowo mengingatkan saya dengan perkataan George Junus Aditjondro. Ia bilang enam tahun setelah Soeharto lengser keprabon, setidaknya ada delapan indikator remiliterisisasi di Indonesia akibat penghapusan peran politik militer dan pemisahan angkatan bersenjata. Sebagian kecil–namun selalu langgeng–militer gunakan keunggulan dan kekuatan fisiknya di lapangan menghadapi rakyat yang berani memberontak.
Hal ini makin parah dengan disahkannya Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada 20 Maret 2025. Meminjam istilah Aditjondro, demokratisasi kini menabrak tembok arus balik pemisahan militer. Artinya perlawanan terhadap kondisi demokrasi yang makin buruk diwarnai badai pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan fakta bagi-bagi jabatan buat tentara.
Belum sampai situ, remiliterisasi yang dianggap nir-kekerasan seperti Operasi Militer Selain Perang (OPMSP) mandatnya turun langsung dari Presiden. Kita bisa melihat sinyal-sinyal kecil, antara lain, pendekatan tentara terhadap mereka yang kritis. Seperti aktivis dan mahasiswa. Remiliterisasi terbaca saat tentara teritorial lakukan sosialisasi di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto; permintaan data mahasiswa yang menolak PSN melalui surat Kodim 1707/Merauke; perjanjian kerjasama Kodam IX/Udayana dengan Universitas Udayana, Bali; hingga teror dan intimidasi terhadap mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (yang gugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi).
Taman bermain militer bukan kampus apalagi ruang publik. Tentara sudah mengobok-obok wilayah akademik, mencari data personal, sampai nekat ikut campur dalam urusan konstitusional perguruan tinggi. Kunjungan tentara dengan kamuflase pakaian sipil di tubuhnya ibarat serigala berbulu domba sehingga tak masuk akal jika personilnya lakukan tugas “pembinaan masyarakat” di kampus semata-mata kegiatan rutin.
Bikin Barak Tandingan
Jika remiliterisasi sudah mulai dilakukan, maka diskursus militerisme boleh saja masuk kampus sebagai bahan obrolan atau diskusi bagi akademisi, praktisi, aktivis, dan siapapun agar mewaspadai bahaya yang muncul dari kekuatan militer di wilayah akademik-sipil. Muhidin M. Dahlan menganggap kampus sebagai tempat yang cocok, karena di sanalah regenerasi kaum terpelajar berlangsung ajeg. Cara tentara berpikir itu khas madrasah bersenjata, lanjut Muhidin, dalam militerisme manusia terdidik terbaik tidak lahir dari kampus.
Begitu pula seharusnya kampus tak bikin kerjasama dengan Kodam. Alih-alih membuka pintu bagi tentara supaya dapat kursi di kelas reguler. Ini bakal mendepak calon mahasiswa baru yang sudah membidik kampus impian sejak kelas sepuluh di Sekolah Menengah Atas (SMA). Kalau pintu kampus dibuka lebar-lebar untuk sanak famili tentara, apa mereka tidak makin jemawa? Pakai seragam saja sudah dibilang “orang berseragam” apalagi ditambah jas almamater. Ini malah jadi olok-olok tiga kata lucu: seragam jas loreng. Aneh!
Belum lagi Gubernur di Jawa Barat mengirim siswa nakal ke barak tentara. Rupanya yang terhormat Kang Dedi Mulyadi tak serius belajar membaca sejarah. Jakarta 1993, Panglima Kodam Jaya A.M. Hendropriyono kirim pelajar yang gemar tawuran ke barak tentara. Kriteria siswa nakal itu ialah yang berperilaku menjurus pada kriminalitas: membawa senjata tajam, mengganggu kepentingan umum, meminum BK (diduga sejenis narkoba). Hendropriyono juga kirim siswi provokator perkelahian. Model pembinaan di barak paling lama satu bulan. Angkatan pertamanya hanya menjalani empat hari dan dianggap tak lagi berpotensi jadi biang keladi tawuran. Program ini berjalan sampai 1997. Namun, Sekolah Khusus Kodim itu justru meningkatkan angka perkelahian remaja pelajar. Awalnya hanya siswa dari delapan sekolah lalu meningkat jadi lima puluh sekolah pada1995. Karena tidak efektif, Kepala Staf Kodam Jaya Susilo Bambang Yudhoyono menghapus program itu.
Sebenarnya, bentuk kebijakan yang melibatkan militer bukan jalan keluar sungguhan. Ia membunuh kritisisme. Karena tentara teritorial berikut pendidikan militernya berorientasi pada pembentukan fisik, bukan nalar. Terlebih doktrin militer yang ditanamkan berpotensi mencuci otak. Inisiatif akan tumpul sebab budaya barak melatih penghuninya patuh pada instruksi.
Maka perlawanan barakisme seperti ini adalah dengan menghidupkan budaya kultural (konstrusi berpikir kritis) bukan struktural (perintah dan instruksi) sekalipun di wilayah akademik. Percayalah, membantah bukan berarti membangkang melainkan ciri kebebasan akdemik dan berpendapat itu hidup.

Menengok Pintu Belakang Militer
Selama hampir 80 tahun, kondisi demokrasi Indonesia terus berjalan mundur. Bukannya maju, kita justru terus mengulang sejarah lama yang buruk. A Historia Se Repete, kata Karl Marx. Jika keadaan terus seperti ini, slogan Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi bualan rezim Prabowo-Gibran. Bangun, lihatlah realita, Jenderal!
Generasi remaja di Indonesia medio 1970-1980 pernah dibuat kagum dengan lagu “Seorang Kapiten” yang begini liriknya:
Aku seorang kapiten
mempunyai pedang panjang
kalau berjalan prok-prok-prok
aku seorang kapiten!
Sosok yang ‘kalau berjalan prok-prok-prok’ kemudian masuk ke desa-desa, film-film perjuangan, sampai cerita mulut ke mulut dan tafsir tunggal bagaimana tentara berhasil melewati masa sulit republik dengan kesetiaan dan pengorbanan yang diproduksi oleh rezim Orde Baru. Tapi ini tak menampik bahwa di pintu belakang barak, konflik internal tentara pun pecah ketuban.
Jauh sebelum Gestok 1965 (Gerakan Satu Oktober) pecah, konflik di AD pada 17 Oktober 1952 antara Bambang Soepeno dengan Nasution bikin keruh hubungan antar prajurit. Soepono pernah menunjukkan ketidakpuasannya pada Kepala Satuan Angkatan Darat (KASAD) yakni AD Nasution. Ia dianggap pemecah TNI oleh Yoga Soegomo mengingat pada 1952-1955 keduanya dipasang-copot oleh Soekarno akibat konflik yang tak kunjung padam.
Berlanjut pada peristiwa 1965. Ini juga menjadi awal kekuatan tak seimbang antara AD, AL, dan AU. Yang terakhir dianaktirikan karena dianggap terlibat dalam penculikan para jenderal dalam naskah Cornell Paper. Kumpulan makalah berjudul “The Coup of October 1 1965” itu membahas sejumlah anggota Divisi Diponegoro membangkang akibat frustasi melihat sejumlah jenderal bergelimang harta di Jakarta. Pelaku penculikan Cakrabirawa (sekarang Paspampres) sebenarnya tentara juga persisnya Angkatan Darat. Lalu AD membela bahwa mereka disusupi anasir lain.
Hal ini terjadi berulang sampai periode transisi 1998 antara Soeharto-Wiranto selepas Soeharto dipaksa turun dari kursi Presiden. Awalnya, Wirantolah yang ditunjuk menggantikan Soeharto, bukan Habibie.
Sebenarnya, konflik Tentara di pintu belakang barak sudah terjadi sejak negara ini berdiri. Pada 1945, berdasar identifikasi Harold Crouch, setidaknya ada dua penyebab terlibatnya militer di urusan sipil. Pertama, militer bermuatan politis sejak awal. Orientasi tentara ketika bergabung bukan ingin kejar karir melainkan lebih tertarik dengan perjuangan kaum nasionalis melawan kolonialisme. Dalam “Militer dan Politik di Indonesia” Crouch berpendapat penyebab kedua ialah kegagalan golongan sipil dalam menjalankan pemerintahan. Militer beranggapan bahwa merekalah satu-satunya golongan yang dapat mengatasi gejolak politik-ekonomi seperti krisis, pergantian kabinet, terutama pemberontakan.
***
Militer dijadikan alat politik Suharto pasca-1965. Mata kuliah “kewiraan” masuk dalam kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) sampai pembentukan Resimen Mahasiswa merupakan cara “penghijauan kampus” di era Orde Baru tepatnya pada 1978. Gejala ini bukan tidak mungkin bakal terulang apabila kita tak acuh atas “mata dan telinga” penguasa otoritarian jebolan barak.
Sekarang, seorang mantan penculik aktivis ‘98, anggota Tim Mawar, dicopot jabatannya pada pengadilan militer 1999, tiga kali mencalonkan diri jadi presiden, yang mengatakan asetnya mandek karena tidak berkuasa, yang bermaksud melakukan autogolpe, suka teriak anti asing itu adalah presiden kita. Ini realita pahit yang harus kita terima. Meskipun demikian, diam bukanlah pilihan. Kekuatan militer terus menggemuk. Kritik dibalas penangkapan. Hanya ada satu cara: lawan!
Andai kita tak menjaga pintu belakang, maka si penjahat tak pernah mau tuntaskan kejadian masa lalu, sejarah akan terulang. Ia akan tetap kabur lewat pintu belakang istana tua: melenggang dari Aksi kamisan.
Penulis: Rossihan Anwar
Editor: Solichah & Delta