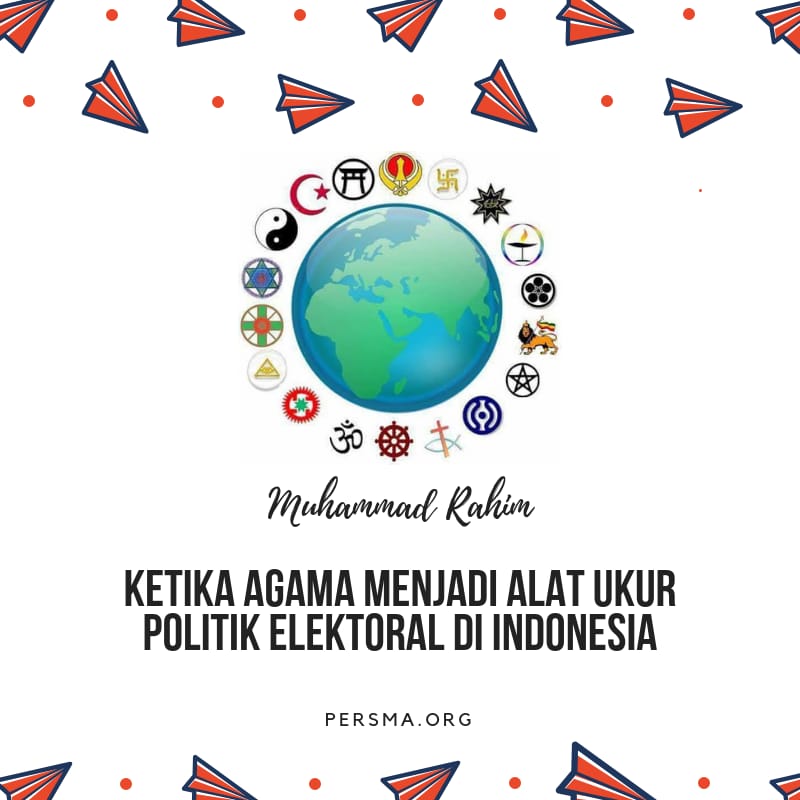Rektor UIN Antasari, Prof Mujiburrahman pernah menulis dalam Jendela (Esai) di koran Banjarmasin Post. Tulisan tersebut membahas tentang “Politik Uang” di Indonesia, dimana banyak politisi di negeri berkembang ini menggunakan uang untuk mendapatkan kekuasaan. Ia menyebut bahwa menerima atau menolak uang adalah pilihan moral. Maraknya politik uang menunjukan betapa bobroknya moralitas kita! Kondisi ini diperparah dengan dengan rendahnya pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai sistem perpolitikan yang mengakibatkan depedensi kepada segelintir golongan yang dipercayai, utamanya adalah golongan ulama atau tokoh agama lainnya.
Keadaan ini jelas berbanding terbalik dengan bangsa yang dicita-citakan oleh founding fathers Indonesia, Soekarno. Ia pernah berpidato pada tahun 1966 mengenai “Nation and Character Building.” Isi pidatonya antara lain adalah ungkapan di depan rakyat, bahwa membangun bangsa dan karakter di Nusantara adalah kewajiban pemerintah saat itu. Karakter adalah bagian dari mental, menciptakan moral adanya mental yang bersih, yaitu membangun pendirian yang kuat dan adil. Tanpa di imingi oleh uang. Jelas, pada saat itu politik uang adalah hal tabu yang tidak sesuai dengan moralitas bangsa.
Kondisi ini kemudian berbanding terbalik dengan arah perpolitikan masa kini yang menganggap politik uang yang didalamnya termasuk mahar politik adalah sesuatu yang biasa. Mundurnya kualitas politik elektoral di Indonesia, menjadi perhatihan besar bagi pengamat politik. Burhanuddin Muhtadi mengatakan praktik jual-beli suara (money politics) di Indonesia sangat besar. Salah satu sebabnya adalah rendahnya Party-ID antara warga dan partai yang kemudian menjadi tolak ukur kesuksesan kampanye.
Rendahnya Party-ID, SARA dan Ormas Keagamaan
Salah satu persoalan utama kita hari ini ialah rendahnya party-identification (party-ID) di Indonesia. Party-ID merupakan derajat kedekatan warga dengan partai yang diyakininya untuk dipilih saat pemilu dilaksanakan. Stigma yang berkembang terhadap partai semakin memburuk di negeri ini, apalagi adanya politik uang yang mendominasi di berbagai daerah. Kecenderungan itu membuat orang apatis terhadap sesuatu yang awalnya ia yakini, sehingga menimbulkan suatu perilaku yang buruk ke depannya.
Hal itu menciptakan streotype yang akut. Pragmatisme yang tumbuh di masyarakat, membuat rakyat menjadi bingung untuk memilih hak politiknya. Menjadi faktor kedekatan warga dengan partai yang sangat rendah. Survei yang dilaksanakan oleh Saiful Mujani Research Center (SMRC) pada bulan Desember 2017 lalu menyebutkan bahwa tingkat kedekatan warga Indonesia dengan partai yang diyakininya hanya sebesar 11,7 persen. Dalam studi komparatif dunia, hasil survei tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat party identification yang paling rendah di dunia (kbr.id, 03/01).
Studi yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi (2018) mengusulkan tentang sistem pemilihan legislatif kita ada baiknya untuk dipertimbangkan dikembalikan ke sistem proposional tertutup. Alasannya, semakin tahun pemilu yang dihadapi Indonesia, presentasinya semakin memburuk terhadap kepercayaan warga. Pertama, tren penurunan partisipasi elektoral dalam tiga pemilu legislatif yang terakhir. Pada Pemilu 1999, pemilih yang menggunakan haknya sebesar 93,3%, lalu turun menjadi 84,9% pada 2004, dan terakhir tinggal 70,9% saja yang masih menggunakan haknya dalam pemilu legislatif pada 2009.
Apabila sistem proporsional tertutup dilakukan, maka dalam pemilu ke depan tidak ada kampanye yang berbau SARA. Dalam berita Kompas.com, Ketua Setara Institute Hendardi berharap semua pihak yang berkontestasi dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 tidak menggunakan sentimen SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) dalam berkampanye. Hendardi mengatakan, kampanye melalui politisasi agama dan ujaran kebencian dapat mengancam kohesi sosial, kebhinekaan, dan integrasi nasional.
Semua yang ditakutkan oleh Hendardi, sama halnya yang ditakutkan oleh warga Kalimantan Selatan, Banjarmasin, yang dominan adalah warga NU. Terlihat beberapa APK terpasang dengan bunyi: “Warga NU, Pilih Kyai NU” tentu menjadi stigma yang berkembang di masyarakat. Bahwa agama kini menjadi daya tawar dalam perpolitikan di Indonesia, dengan adanya organisasi masyarakat (Ormas) berbasis agama itu kini menjadi alat besar untuk mendorong massa. Benar memalukan, sehingga dirasa ormas itu tidak memiliki marwahnya kembali, dengan esensi yang pernah dibangun oleh para pendiri terdahulu.