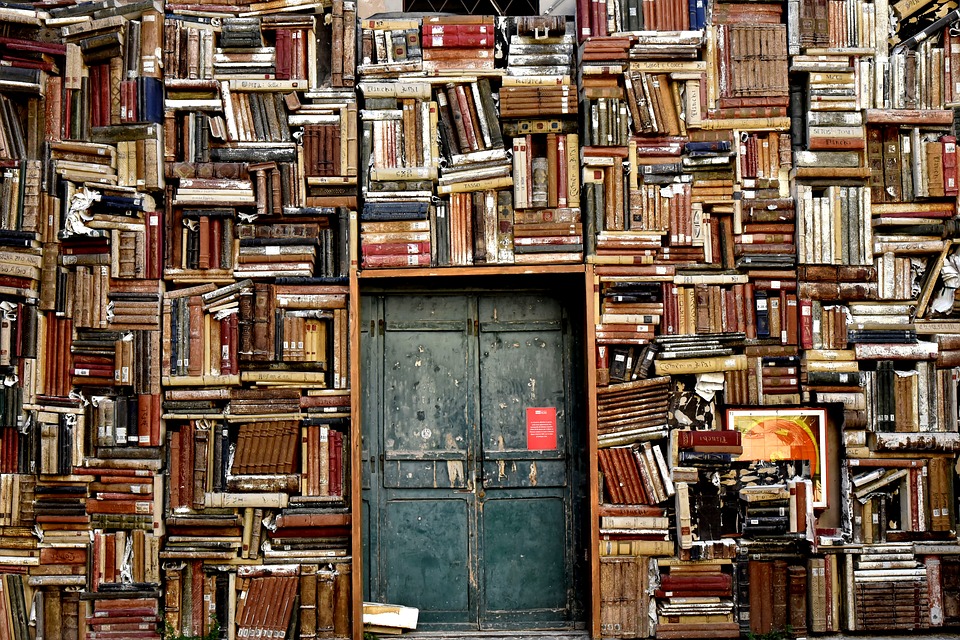Label media alternatif yang disandang Pers Mahasiswa (Persma), tidak sedikit menemui kegelisahan pada perencanaan segmentasi pembaca. Adanya lingkaran setan –dikelola dikonsumsi sendiri- masih disugesti akan membawa kebangkrutan Persma dalam menyebarkan wacana kritis. Kebangkrutan yang mana? bangkrut yang dimaksud yaitu distribusi produk masih sekitaran itu-itu saja, internal Persma dan kalau beruntung bisa dikonsumsi mahasiswa seantero kampus tempat lembaga pers tersebut bernaung.
Alhasil wacana media alternatif tidak dapat dipahami sebagai alat perjuangan atau kontrol sosial. Melainkan suara kaum konservatif yang tersingkir dari perdebatan media umum yang begitu banyak jumlahnya.
Parahnya, apabila Persma mengamini bahwa dirinya bangkrut dan tidak bisa keluar dari lingkaran setan tersebut maka jalan terbaik adalah ‘berdamai dengan keadaan’. Agar pembacanya meluas, tidak ada cara lain selain berjalan beriringan dengan industri media –mutung sebagai alih-alih berdamai . Agar wacana kritis yang dihasilkan dapat sampai ke pembaca yang cakupannya lebih luas, minimal menyaingi separuh dari total pembaca media umum (lokal) perharinya.
Muncul lah keinginan bertubi-tubi seperti, kemandirian dana –lah, membentuk yayasan –lah, membuat kantor –lah, semuanya berakar pada membadanhukumkan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI).
Saya mungkin akan menganggap tawaran Mas Muadz sebagai angin lalu. Tapi saya rasa lebih ber-faedah ketika tulisan yang kadung dibaca lebih baik diperdebatkan secara sehat.
Dalam beberapa hal, tawaran perlindungan hukum ini lebih sejalan dengan pemikiran pragmatisme dibanding teori. Seseorang mungkin membayangkan bahwa legitimasi hukum akan mengantarkan Persma kepada tameng besar yang akan melindungi segala bentuk sengketa pers. Meski tidak dalam hal kebenaran-loyalitas-independensi. Karena pada dasarnya media alternatif dibentuk dalam menjalankan peran anjing penjaga, serta memihak –bukan senantiasa pihak yang benar dan menang di tempat publik.
Tiga Poin Dasar yang Dianut Persma
Anggap saja Persma sudah mapan dalam hal administrasi dan punya peluang besar menjalin relasi sponsor atau founding. Dalam hal kebenaran, apakah dapat menyajikan tanpa pledoi bahwa Persma sekalipun harus menulis kebenaran meski sulit.
Keberanaran tak jauh dengan kejujuran, karena hasrat ini ada sejak manusia dilahirkan. Tetapi konsktruksi diluar dirinya bergesekan dengan hasrat ini. Penyajian informasi bukan sekadar pemungutan fakta-fakta yang berserakan lalu membungkusnya menjadi sebuah cerita.
Dalam buku Bill Kovach dan Tom Rosensteil, Walter Lippman menggunkan istilah kebenaran dan berita yang bisa saling dipertukarkan. Namun pada 1992 dalam Public Opinion, ia menulis “Berita dan kebenaran bukanlah hal yang sama, fungsi berita adalah menandai suatu peristiwa,” atau membuat orang sadar akan hal itu. “Fungsi kebenaran adalah menerangi fakta tersebunyi, menghubungkannya satu sama lain, dan membuat sebuah gambaran realitas yang dari sini orang bisa bertindak.”
Lalu bagaimana hasrat jujur ini terbentur oleh founding yang kadung dijalin? Meggie Gallagher mengatakan bahwa menjaga jarak dengan faksi menjadi sangat penting. Dalam buku Sembilan Elemen Jurnalisme, Gallagher mengungkapkan, “saya rasa hal ini berkaitan dengan kepercayaan mendasar saya bahwa ada hubungan anatara jurnalisme dan persepsi seoarang akan kebenaran,” selanjutnya, “namun dengan loyal pada sebuah partai politik, seseorang atau faksi , Anda tak punya komitmen untuk berbicara kebenaran kepada orang-orang yang menjadi audiens”.
Kemudian kepada siapa wartawan bekerja? Pertanyaan tersebut subjekif ketika dihadapkan pada profesi wartawan profesional. Kerena wartawan profesional diberikan wewenang sesuai dengan kemauan perusahaan medianya dan redaktur yang menyaring kerja wartawan.
Kesetiaan kepada warga, merupakan makna dari yang sering kita sebut sebagai independensi jurnalistik. Sering kita maknai sebagai ketidakterikatan, tidak berat sebelah. Masih di buku Kovach, survei tentang nilai nilai jurnalisme pada 1999, yang dilakukan Pew Research center For The People and The Press and Committe Concerned Journalist, lebih dari 80 persen responden menempatkan “kewajiban pertama adalah kepada pembaca-pendengar-pemirsa.”
Namun istilah-istilah itu disadari terbatas dengan norma-norma tertentu, norma yang disinggung Gallagher diatas. Hal itu memang dianggap wajar dikalangan wartawan, namun konsep kejujuran yang dibangun melalui laku wartawan masih terlalu kabur. Apalagi Persma, sok membadanhukumkan.
Kovach menuliskan yang dialami Maggie Gallagher dan beberapa temanya yang kuliah di Yale University. Mereka capek dengan yang mereka anggap kemapanan harian Yale Daily News, yang selalu mencerminkan pandangan pejabat universitas dan sebagian besar lembaga kemahasiswaan disana.
Lima belas tahun berikutnya, Saat kariernya beranjak naik hingga jadi kolumnis untuk Universal Press Syndicate dan harian New York Post, ia mengatakan kepada kami dalam sebuah forum Committee of Concerned Journalist, bahwa pengalamannya selalu membawakannya kembali pada kata-kata yang terpampang di slogan koran kampus itu “Jurnalisme dengan Sikap.”
Dengan kata lain independensi Persma seolah-olah berpihak pada perlawanan kaum yang tertindas. Sebagai Persma yang ‘mapan’, Persma akan tetap mengupayakan menjadi media alternatif dan mendahulukan kepentingan publik diatas segalanya sebagai ‘sikap’. Namun sebuah khayali bahwa kebiasaan Persma yang sudah mapan dengan gelontoran dana tidak ada pengaruh dalam kerja jurnalismenya. Seolah-olah alternatif, tetap saja Persma akan bersikap pada yang memberi kemapanan.
Refleksi Membadanhukumkan PPMI
Bagaimana dengan Badan Hukum? Masih mengupayakan terlaksana? Seharusnya wacana ini selesai ditataran kota. Sebagai upaya tidak memutus wacana ke-PPMI-an, serta merawat ingatan atas sejarah yang telah terbentuk.
Mugkin bisa melalui meja warung kopi atau silahkan membuka arsip PPMI, pada selebaran dengan judul ‘Serat Merah Putih #edisi April 2013’. Disitu tertulis bagaimana kiranya PPMI kota Jember bersikap atas wacana Badan Hukum PPMI, melalui serangkaian acara Nasional dintaranya Kongres XI Tulungagung dan Mukernas IX Surabaya. Jika tidak menemukan berkas yang saya maksud, baiklah saya akan membagikannya.
Wacana membadanhukumkan PPMI hadir jauh sebelum munculnya riset kekerasan persma. Wacana badan hukum memunculkan stigma positif karena ketika sudah berbadan hukum akan ada jalan hukum yang menunutun penyelesaian kasus sengketa, Persma akan lebih kuat dengan itu. Namun beberapa kota menyatakan sikapnya menentang pembadanhukuman.
Salah satunya PPMI Jember, pada acara Mukernas IX PPMI di IAIN Sunan Ampel Surabaya (21/9/1012) Badan Pengurus Nasional Advokasi(BPN-A) memaparkan program kerjanya. Pembahasan yang berlarut-larut adalah membadanhukumkan PPMI.
BPN-A menjelaskan beberapa poin alasan kenapa membadanhukumkan PPMI, 1) Membadanhukumkan PPMI adalah rekomendasi dari Kongres XI PPMI di Tulungagung yang harus dilaksanakan. 2) PPMI merupakan organisasi dengan kas yang selalu kosong. Ketika PPMI berbadan hukum maka akan dengan mudah menjalin kerjasama dengan sponsor dan founding. PPMI akan kaya ! 3) Advokasi terhadap permasalahan persma akan lebih mudah, karena PPMI mempunyai legalitas hukum.
Begitu kiranya alasan wacana PPMI harus berbadan hukum. Malam itu perdebatan alot terjadi pada poin pembadanhukuman PPMI, beberapa peserta forum mengamini membadan hukumkanan sebelum ketokan “sepakat” Jember memberikan pandangan perserta forum agar tidak begitu mudahnya tergiur tawaran badan hukum.
Menaggapi BPN-A, Pertama Jember mengklarifikasi bahwa rekomendasi badan hukum yang tercetus di Tulungagung hanya bersifat rekomendasi. Artinya ‘bisa dilaksanakan atau tidak dilaksakan’ oleh pengurus nasional. Karena kesepakatan forum itu adalah segala bentuk rekomendasi yang diusulkan kota tidak untuk dipermasalahkan melalui proses pembahasan, melainkan hanya ditampung.
Dari situ BPN-A bukan menjelaskan secara detail mengapa ada program membadanhukumkan PPMI, bagaimana nantinya proses menuju badan hukum, persyaratan apa saja yang harus dilakukan untuk berbadan hukum, apakah dampak badan hukum terhadap pola kerja PPMI Nasional-PPMI kota-LPM, dll kepada peserta. Selain hanya menakut-nakuti hasil kesepakatan Kongres XI Tulungagung yang sudah ‘disahkan’ tidak dapat dirubah.
Kedua dalam pendanaan, selama ini PPMI mengelola badan usaha mandiri melalui kerjasama dengan sponsor atau instansi yang tidak bertentangan dengan AD/ART. Namun pengurus nasional saat itu menginginkan memperoleh founding.
Dalam hal founding bentuk kerjasama yang saling menguntungkan akan didapat PPMI ketika memperoleh founding, seperti fasilitas riset yang secara penuh didanai founding. Iming-iming gelontoran dana yang pada saat itu dominan muncul ketika PPMI ingin mendapatkan founding. Efeknya pandangan dari Jember membadanhukumkan PPMI merupakan upaya praktis demi mendapat dana dari founding, karena BPN-A seringkali mencekoki fantasi kucuran dana.
Ketiga ketika PPMI berbadan hukum tidak akan jauh dalam proses advokasi. Hanya saja PPMI akan memiliki kewenangan mendapat data atau melakukan uji materi. Tentu saja yang diinginkan dari badan hukum dalam hal advokasi adalah pelebaran kekuasaan PPMI.
Ketika ujung permasalahan adalah LPM yang tidak mematuhi kode etik, maka sanksi yang didapat LPM bisa bergantung bagaimana mediator dan penggugat. Bisa saja melakukan hak jawab, memecat anggota LPM, membekukan LPM, dll. Lantas tidak ada bedanya mediasi yang dilakukan AJI atau Dewan Pers. Bisa dikatakan bahwa untuk memperkecil permasalahan kerja jurnalistik adalah dengan memperbanyak pelatihan.
Perdebatan panjang terjadi antara delegasi Jember dengan BPN-A. Lagi-lagi Jember masih marasa penjelasan BPN-A tidak mengarah pada petanyaan bagaimana nantinya proses menuju badan hukum, persyaratan apa saja yang harus dilakukan untuk berbadan hukum, apakah dampak badan hukum terhadap pola kerja PPMI Nasional-PPMI kota-LPM.
Kemudian pimpinan sidang menawarkan kepada forum, apakah forum menyetujui program kerja badan hukum. Suara dominan adalah ‘tidak’. Palu tidak segera diketok, malah menawarkan ulang program kerja terbut disetujui atau tidak. Alhasil tetap, forum dominan dengan ‘tidak’.
Kali ini pemimpin sidang mengetok palu, sebagai tanda disahkannya putusan badan hukum tidak disepakati forum. Lalu ada orang dengan cekatan mengambil microphone untuk menyatakan akan melakukan peninjauan kembali (PK), secara bersamaan juga dia melakukan rasionalisasi kenapa butuh adanya badan hukum.
Forum ramai dan mempertanyakan mekanisme PK, peserta menginiginkan pemimpin sidang menawarkan kepada forum apakah PK diterima peserta forum. Kemudian pemimpin sidang menawarkan kepada forum, ternyata sebagian besar tidak menyetujui, akan tetapi pemimpin sidang mengetuk palu sidang dan mengatakan PK disetujui.
Kemudian Dewan Etik Nasional PPMI yang mengajukan PK tadi meminta untuk merasionalkan kembali kepada yang tidak sepakat dengan badan hukum BPN-A. Bermodalkan selembar catatan kecil delegasi Jember mempresentasikan di depan peserta forum.
Setelah itu, Sekjend Nasional mengambil microphone dan memberikan rasionalisasinya kepada forum. Tidak jauh-jauh rasionalisasi itu menyinggung betapa pentingnya PPMI dibadanhukumkan. Dengan power yang dimiliki Sekjend peserta forum meng’iya’kan program kerja BPN-A setelah pemimpin sidang menawarkan ulang kepada forum.
Jember berunding, bahwa sengotot apapun Jember meminta penjelasan dan tidak menyepakati program kerja itu tetap saja tidak ada gunanya. Barangkali akan muncul ribuan PK, atau yang paling buruk diadakannya voting. Atas dasar kedewasaan berpikir, Jember memutuskan walk out dari forum.
Tidak berhenti sampai disitu, sikap Jember berlanjut dengan mendokumentasikan hasil forum nasional di media Serat Merah Putih edisi April 2013. Pada kondisi tertentu, peserta forum butuh refleksi atas apa yang terjadi pada forum nasional tersebut. Melalui tulisan, perserta yang tadinya menyetujui badan hukum PPMI akan lebih mencerna betapa politisnya tawaran badan hukum itu. Tidak ada indahnya berlindung dibalik kekuasaan.
Badan hukum akan memicu regulasi yang ber-sentral pada satu tubuh, yaitu PPMI. Justru mengkaburkar sistem bottom to up, LPM yang sejatinya PPMI itu sendiri saling mempunyai tubuh masing-masing. Up to bottom kira-kira yang bakal terjadi.[]