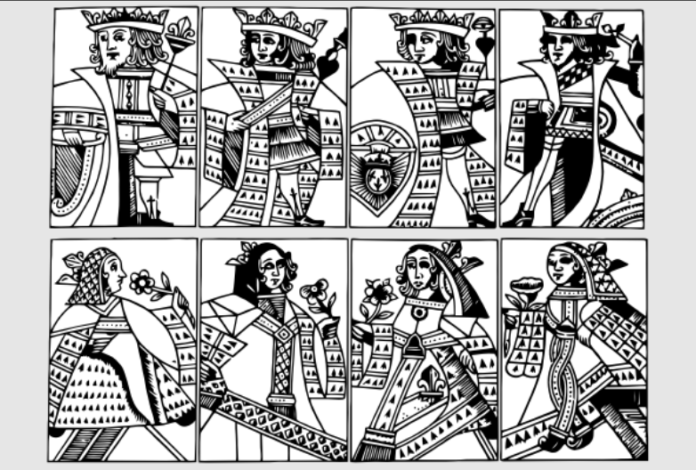
Power dalam bingkai studi hubungan internasional sering disebut dengan kekuasaan. Dengan koleganya, ilmu politik, power didefinisikan sebagai perebutan kekuasaan. Namun dalam HI, power adalah segala sesuatu (atribut, atau tujuan) yang bisa menciptakan dan mempertahankan pengendalian seseorang atas orang lain.
Bila dilihat dari intensitasnya, istilah power merupakan kata yang paling sering diucap dosen saat mengajar di kelas-kelas. Bila dilihat lebih dalam lagi, power (kekuasaan) merupakan inti dari setiap upaya menyelami ilmu hubungan internasional. Siapapun yang belajar tentang HI, seyogyanya tau akan hal ini. Siapapun yang (niat) belajar ilmu ini, ia bakal dihadapkan dengan pencarian makna dan konsekuensi praktisnya, sebagai upaya untuk merebut, mencapai dan mempertahankan sebuah kekuasaan.
Memaknai power bukan berarti kita harus bergabung di dalamnya. Bukan berarti kita harus menjadi presiden, Jendral, atau bos kartel narkoba untuk bisa mengerti tentang power, apa itu kekuasaan dan bagaimana ia bekerja. Tapi, jika ingin merasakannya secara langsung, saya kira opsi untuk menjadi pemimpin dalam sebuah institusi (lembaga, organisasi) bisa menjadi pilihan yang baik (asal bertanggung jawab).
Sebelum memulai lebih lanjut, perlu saya jelaskan disini bahwa pendefinisian power itu sendiri banyak memicu perdebatan. Columbius dan Wolfe menyebut ada dua hal yang masih disilangpendapat kan, yaitu tentang power sebagai atribut (militer, tingkat ekonomi), atau hubungan antara dua aktor politik yang berbeda. Namun saya tidak akan menjelaskannya dalam catatan singkat ini.
Hans Morgenthau, dalam bukunya “Politic among Nations”, mendefinisikan power sebagai hubungan antara dua aktor politik dimana aktor A memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan tindakan aktor B.
Jadi, power menurut Morgenthau bisa berupa apa saja, dari ancaman fisik hingga tekanan psikologis yang menciptakan dan mempertahankan pengendalian seseorang terhadap orang lain.
Dalam pengertian ini, misalnya : Fulan, seorang yang tinggi berotot menyuruh Alan yang kering kerontang untuk membelikannya sebungkus rokok di warung. Jika si Alan menolak, Fulan berjanji akan meninju Alan habis-habisan. Alan akhirnya mau, meski dengan terpaksa.
Pada contoh diatas, “badan tinggi dan otot kuat” merupakan sebuah atribut yang dimiliki oleh Fulan untuk bisa mengendalikan Alan untuk mau menuruti perintahnya. Jika menolak permintaan itu, Alan takut dirinya bakal diberi bogem mentah di sekujur tubuhnya. Dengan kata lain, Fulan mempunyai power (kuasa) terhadap Alan.
Columbius dan Wolfe lebih lanjut menjelaskan tiga unsur penting dalam power. Pertama adalah daya paksa. Yaitu beragam ancaman kasat mata sebagai faktor pemaksa oleh aktor A terhadap aktor B. Unsur kedua ialah pengaruh (influence), yang diartikan sebagai alat-alat persuasi (tanpa kekerasan) untuk menjamin perilaku aktor B agar sesuai keinginan aktor A.
Terakhir, yang ketiga, adalah authorithy (wewenang). Konsep ini merujuk pada sikap tunduk secara sukarela aktor B lewat nasehat, perintah, atau karisma yang ditunjukan oleh aktor A.
Pada contoh diatas, Fulan memakai power yang dimilikinya untuk mengendalikan tindakan Alan. Unsur yang digunakan ialah daya paksa, dengan atribut berupa ancaman fisik (tinju) yang bakal didaratkan Fulan kepada Alan jika ia tak mau menerima perintahnya.
Paradoks Kekuasaan
Yang menarik dari sebuah kekuasaan adalah wujudnya yang paradoks. Persis seperti dua sisi mata koin yang saling berlainan, kekuasaan menampilkan dirinya sebagai entitas berwajah ganda.
Di satu sisi, di tangan yang tepat, kekuasaan bisa menjadi pintu gerbang bagi manusia dalam rangka mencapai mimpi-mimpi indahnya. Upaya-upaya menciptakan kedamaian, ketertiban, keadilan hingga kesetaraan, dapat terwujud jika kekuasaan digunakan dengan dan oleh pemimpin yang tepat.
Di sisi yang lain, kekuasaan adalah rahim bagi lahirnya neraka duniawi. Terutama bila ia berwujud penindasan, pemiskinan, pembodohon atau penyalahgunaan sewenang-wenang oleh pemimpin, institusi hingga lembaga yang menjelma sebagai iblis berkaki dua kepada warganya.
Menariknya, yang terakhir ini bisa kita temukan sehari-hari dalam institusi yang bernama negara. Baik dalam bentuk kebijakan maupun tindakan aparatusnya, negara acap kali bertindak di luar batas dalam maksud menggunakan kekuasaan yang ia miliki. Soal ini kita bisa menyebutnya sebagai penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
Kekuasaan, dalam sifat dan praktiknya, punya batasan-batasan yang terkait dengan ruang lingkupnya. Batasan-batasan inilah yang memungkinkan para pemimpin atau orang yang punya kuasa untuk tidak menyalahgunakannya secara sewenang-wenang. Di ranah negara, batasan ini dimanifestasikan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat dan punya sifat memaksa. Ia disebut hukum. Hukum ibarat wasit yang menjaga pemimpin agar tidak keluar jalur saat melakukan pekerjaan.
Sebagai pemimpin umum, saya punya kuasa untuk mengatur dan menyuruh pengurus saya untuk mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Namun, saya tak punya wewenang untuk memaksa mereka. Kekuasaan dalam organisasi sifatnya terbatas, didapatkan dari konsensus bersama melalui musyawarah dan batasan-batasannya amat kabur. Misalnya, mendorong mereka untuk mau menulis merupakan salah satu tugas (baca: kuasa) saya, tapi, menggunakan jabatan ini untuk mendekati perempuan demi dijadikan pacar adalah hal yang tidak patut, setidaknya dalam pertimbangan etis dan moral.
Beda lagi dengan kekuasaan yang ada pada negara (saya menyebut negara sebagai kesatuan dari pemerintah dan para aparatusnya). Di tangan mereka, kekuasaan menjelma sebagai barang yang bisa dipermainkan sekehendak hatinya. Sia-sia saja menuliskan disini pelbagai catatan kelam penyalahgunaan kekuasan oleh negara terhadap warganya sendiri. Sebuah roman 1000 halaman pun takan cukup. Konflik Wadas bisa menjadi cerminan paling anyar dari upaya negara untuk menukar sumber kehidupan warga Kecamatan Bener, Purwerojo dengan sebuah bendungan yang entah dibuat untuk siapa.
Kekerasan Aktifis di Jombang
Salah satu unsur yang bisa digunakan untuk mengendalikan orang lain ialah wewenang (authorithy). Wewenang ini menurut saya bisa dibedakan menjadi dua, formal dan non formal. Yang pertama bisa didapatkan ketika mempunyai jabatan/posisi sebuah institusi (negara, organisasi dll). Ada kerangka legal dimana kita menggunakan kuasa kita (hukum, AD-ART).
Yang kedua sifatnya tak terlihat. Ia berasal dari atribut-atribut “spesial” yang melekat dalam sosok seseorang. Atribut-atribut itu dapat berupa ilmu, karisma, ahlak, hingga adab.
Dalam dua tahun terakhir, selama berkuliah saya memilih nyantri di pondok pesantren yang masih satu “keluarga” dengan kampus. Saya sedikit mengerti bahwa kyai adalah sosok yang amat di hormati dan dijunjung tinggi dalam lingkungan pesantren. Para santri biasanya bakal dengan gampang mengikuti tutur kata dan perbuatan yang dititahkan oleh kyainya.
Penganiayaan yang dialami Rani (bukan nama sebenarnya) diduga dipicu oleh kegiatannya sebagai aktifis kekerasan seksual, lebih khusus lagi pada kasus yang melibatkan anak Kyai terkenal di Jombang, M, Subchi Azal Tsani. Saya tak tahu apakah ada korelasi langsung antara kekerasan yang dialami Rani dengan posisi Subchi yang merupakan anak Kyai. Namun, kita tahu bagaimana posisi prestisius seseorang acap kali bisa membuatnya kebal dari tindakan hukum. Terkait kekerasan seksual yang (diduga) dilakukan oleh Subchi, apakah saya salah jika mengatakan bahwa posisi Subhci yang saat ini masih melenggang bebas adalah buntut dari privilisnya yang seorang anak kyai?
Tentu ini cuma hipotesa belaka. Tapi kita semua sudah mafhum bahwa pelaksanaan hukum Indonesia seringkali tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Bedebahnya, ini merupakan fenomena umum yang lazim ditemukan. Authority (wewenang) yang dipunyai seseorang bisa (atau biasa) menjadi tameng perlindungan bagi ia untuk melenggang dari jerat hukum yang sudah jelas bisa menimpa orang-orang kecil.
Contoh konkritnya bisa kita temukan dalam tindakan Tim Mawar atas penyulikan para aktifis di medio 98 an. Atau pada kasus-kasus HAM masa lalu yang belum terselesaikan hingga sekarang. Pada kasus penculikan aktifis, mirisnya, jenderal yang (diduga) menjadi tersangka masih berkeliaran bebas bahkan ada yang sampai dua kali nyalon sebagai Presiden.
Kasus 65 lebih ngeri lagi. Pembantaian besar-besaran 500 hingga 1 juta orang tak menyisakan pelaku yang jelas untuk diadili. Rezim Soeharto menguburnya dalam-dalam. Dan rezim Habibi hingga Jokowi tak ada kemauan kuat untuk mengungkapnya.
Rani, 23 tahun, mengalami penganiayaan karena memperjuangkan penyelesaian kasus kekerasan seksual. Dan itu bukanlah sebuah mukjizat. Siapapun bisa dianiaya dan melakukan aniaya. Terlebih bila ia punya kekuasaan yang besar, otoritas yang kuat, pengaruh yang luas, maka menyalahgunakannya hanya sebatas pilihan mau atau tidak mau. Semudah Thanos ketika menghilangkan separuh isi penduduk alam semesta hanya dengan sekali klik jentakan jari.
Namun saya kira orang-orang seperti Rani bakal tetap ada dan terus berlipat ganda. Nyala apinya menjalar bagi siapapun yang merasakan dirinya terkungkung dalam tempurung penyiksaan, kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh negara, otoritas keagamaan hingga para iblis kapital. Dan siapa tahu, nyala api itu dapat masuk dalam tubuh kita semua. Semoga dan semoga.























