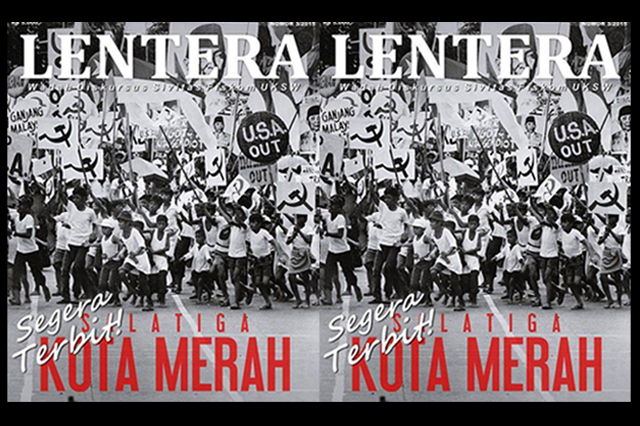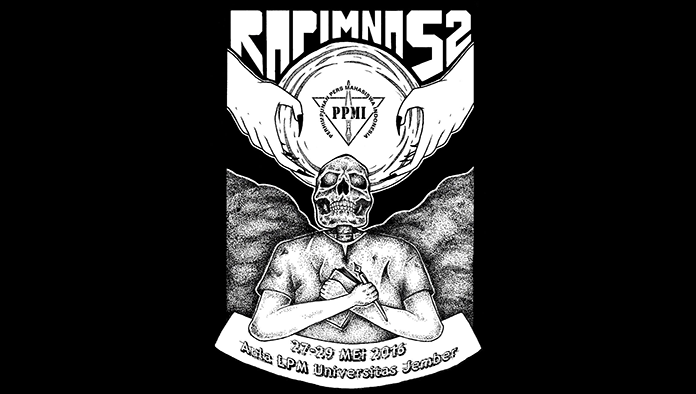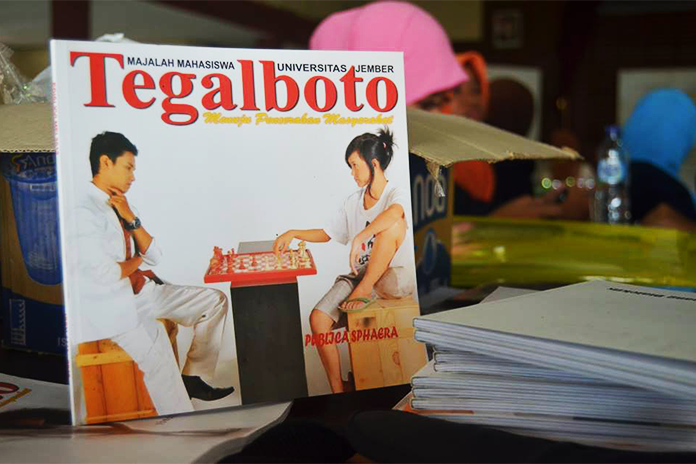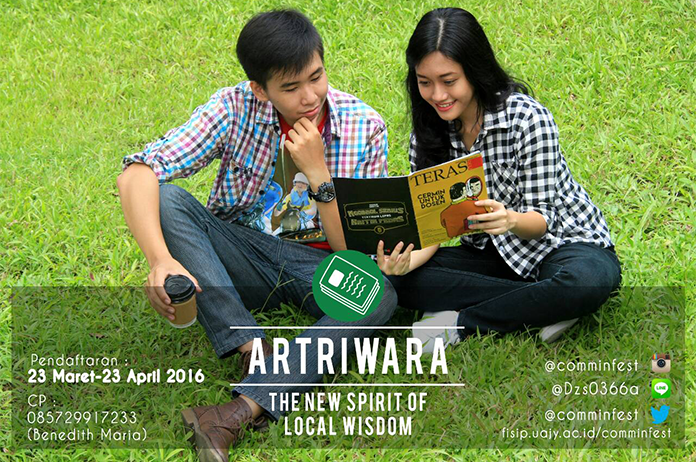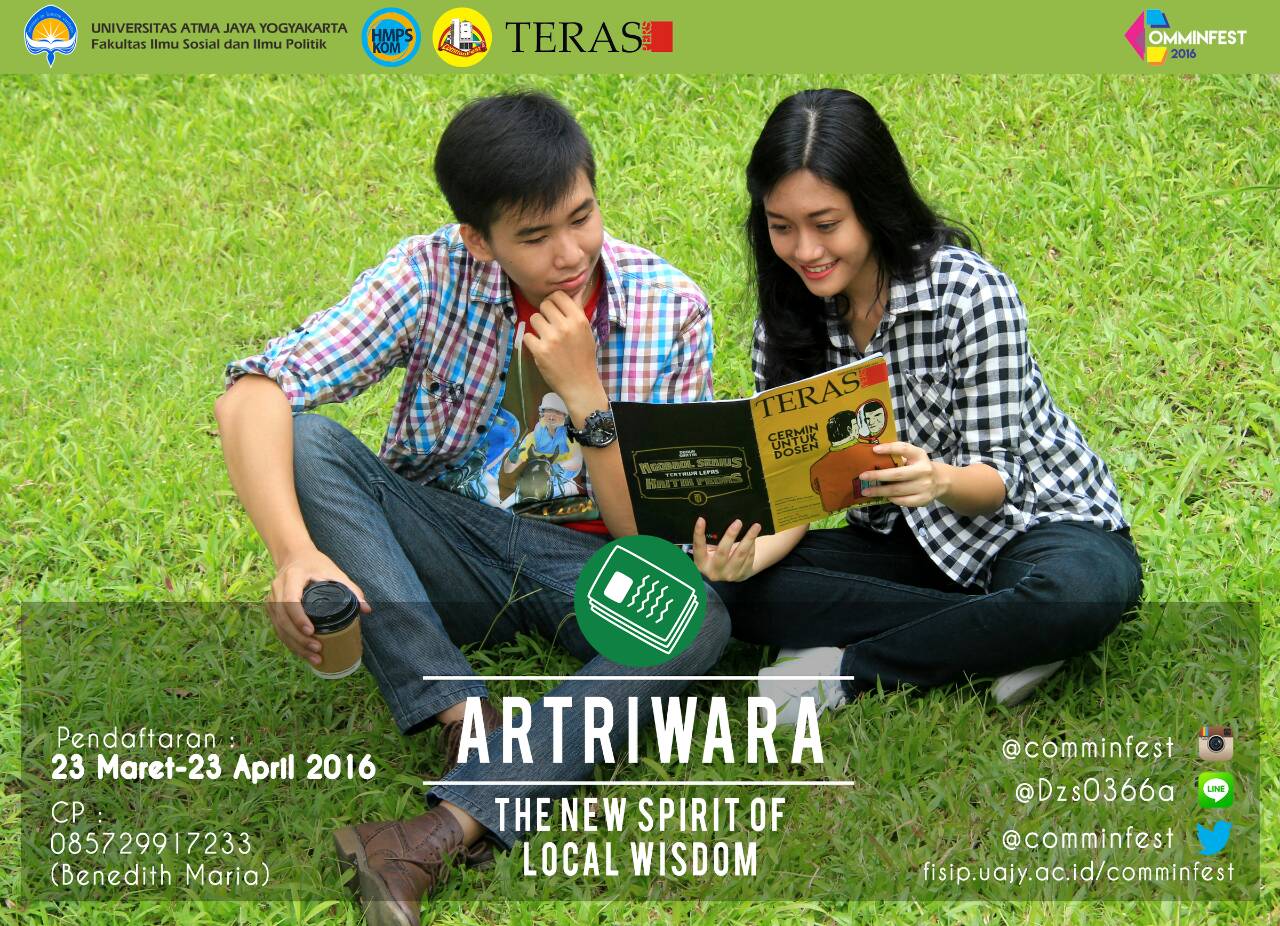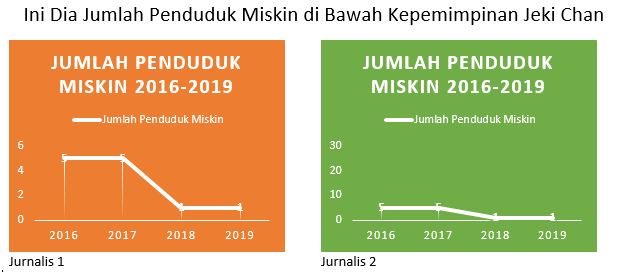Sebagai sebuah pranata dan dan sebuah media massa, Persma punya modal sejarah dan berita yang berpotensi ledakan dalam gerakan perubahan. Dalam buku Anak Semua Bangsa yang ditulis Pramoedya sebagai potongan serial dari Tetralogi Buru, diceritakan potongan percakapan antara seorang wartawan senior De Locomotief dari Belanda, dengan Minke sang tokoh utama.
Pada obrolan keduanya diketahui tentang sebuah gerakan kaum terpelajar yang sedang besar di Filipina, sebuah gerakan pers yang keluar dari arus utama dan dimotori gerakan pemuda pelajar. Gerakan tersebut berusaha mengabarkan kenyataan yang disembunyikan pemerintah kolonial, dan diluar dugaan berhasil merubah iklim politik Negara-negara koloni di Asia.
Gerakan pers pemuda pelajar Filipina masa itu, kemudian menginspirasi gerakan pemuda Negara koloni di seluruh Asia termasuk Hindia Belanda. Disaat kemerdekaan gagal diupayakan dengan senjata, saat itulah pena harus mengambil perannya.
****
Karena tidak berniat melangkahi sejarah dalam memberi penjelasan, sehingga detail gerakan pers masa lalu tak perlu detil lebih jauh. Cukuplah perkara penjelasan sejarah yang seluruhnya dibebankan kepada pakar yang lebih berkapasitas.
Dalam diskursus teori kreativitas, pertanyaan jatuh pada “generasi emas sepanjang zaman” yang kemudian terjawab oleh “generasi yang tumbuh di masa perang.” Pada kajian konsep kreativitas, tekanan keadaan disebut-sebut sebagai faktor paling dominan. Sementara keinginan untuk segera lepas dari tekanan adalah motif yang mendasari sebuah gagasan ataupun gerakan.
Secara mendasar, tekanan keadaan dibutuhkan untuk memunculkan sebuah potensi hingga titik maksimal. Meminjam asumsi psikoanalisa, mengenai teritori kesadaran yang dipopulerkan Sigmund Freud lewat buku Introducing Psychoanalysis. Konflik id-ego-superego yang masing-masing mewakili kesadaran dorongan-kenyataan-keyakinan, akan menyeleksi informasi sebagai referensi dalam pengambilan keputusan.
Singkatnya, konflik yang terjadi antar teritori akan memaksa kognisi bekerja mencari pemecahan. Semakin sulit konflik dipecahkan, semakin banyak kognisi bekerja, semakin banyak pula pengambilan keputusan. Sehingga rangkaian keputusan yang dinilai gagal, akan menjadi evaluasi kognitif kemudian mengumpulkan seluruh informasi menjadi sebuah gagasan resolutif.
Rentetan pembungkaman persma yang belakangan terjadi, barangkali kemunduran bagi demokrasi. Tapi tidak bagi persma itu sendiri. Dari mengurusi pembangkangan terhadap kolonial, sampai terlempar mengurusi pemberitaan remeh soal kegiatan ormawa. Persma tidak sedang mengalami kemunduran, hanya sedang mengurusi keadaan yang salah.
Bila harapannya, persma sebagai tonggak perubahan. Maka persma punya kewajiban untuk lekas menyembuhkan dari gejala disosiasi yang belakangan menaruh persma keluar dari arus balik. Persma mesti menyadari perannya sebagai sarana pengabaran alternatif, untuk hal-hal yang enggan dikabarkan pers industri karena bakal mengganggu iklim investasi. Sementara bila persma memang diniatkan sejak awal oleh pegiatnya, semata demi melatih diri menulis dan menjadi jurnalis belaka. Rasanya industri media adalah tempat yang jauh lebih tepat.
Karena sebagai pers, dan sebagai mahasiswa. Persma adalah oposisi yang lengkap, wajah utuh dari independensi yang ideal. Posisi yang menganugerahkan bagi pegiatnya, tupoksi mengkoreksi minim potensi terkooptasi. Kooptasi kepentingan politik-ekonomi, dan tentu saja tabiat anti demokrasi. Kira-kira sejalan dengan petitih Tan Malaka “Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki seorang pemuda.”
Meminjam pengakuan dari Alejandro Carpentin sebagai saran yang patut diterangkan pada akhir tulisan “menjalani hidup penuh resiko, jauh lebih bermakna ketimbang menunggu berkarung-karung tertigu dengan penuh kesalehan.” Ketimbang mengurusi soal pengabaran kegiatan kampus yang bersifat hura-hura. Persma perlu lebih banyak berurusan dengan lebih banyak resiko untuk memaksimalkan potensi. Barangkali bisa dengan menghadapi yang kualitas kolonial atau orde baru bila bernyali, atau minimal resiko kualitas ormas intoleran dan polisi, hingga yang paling dekat, resiko kualitas birokrasi.