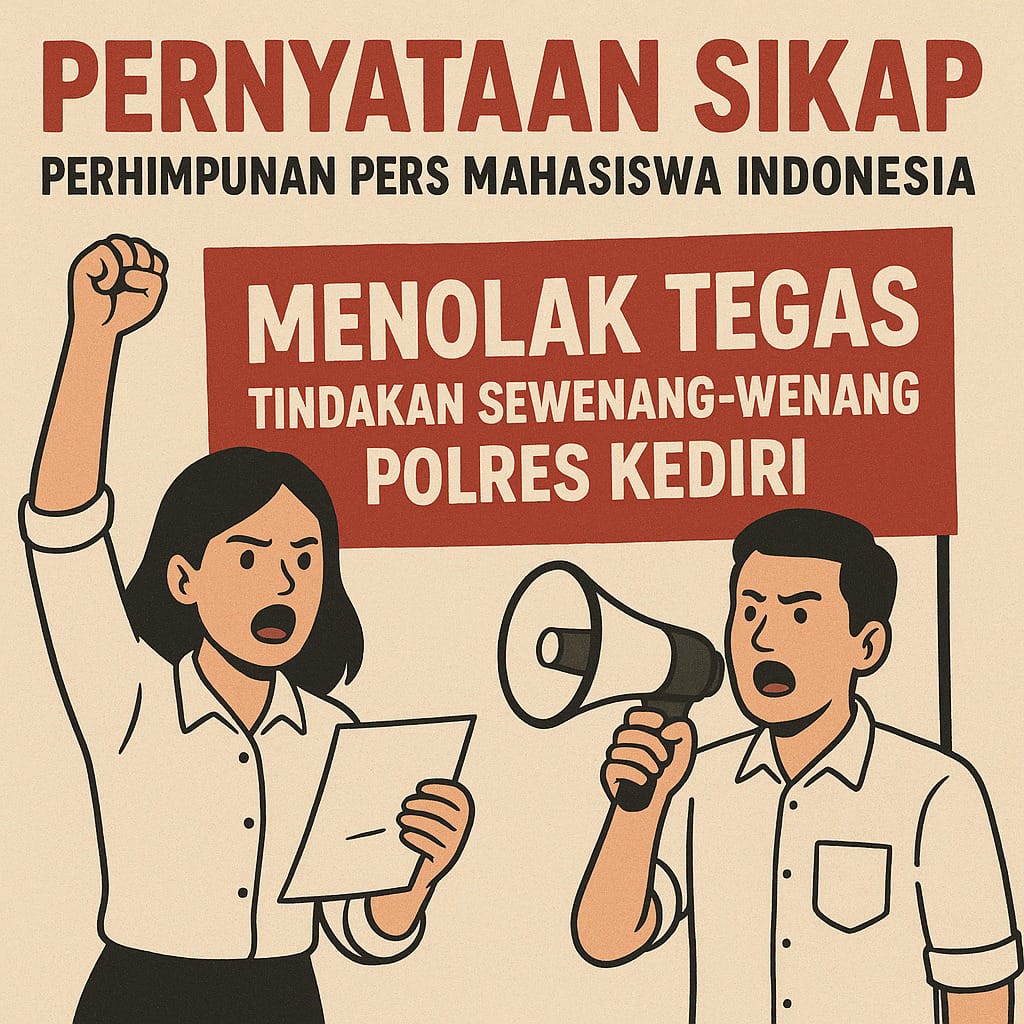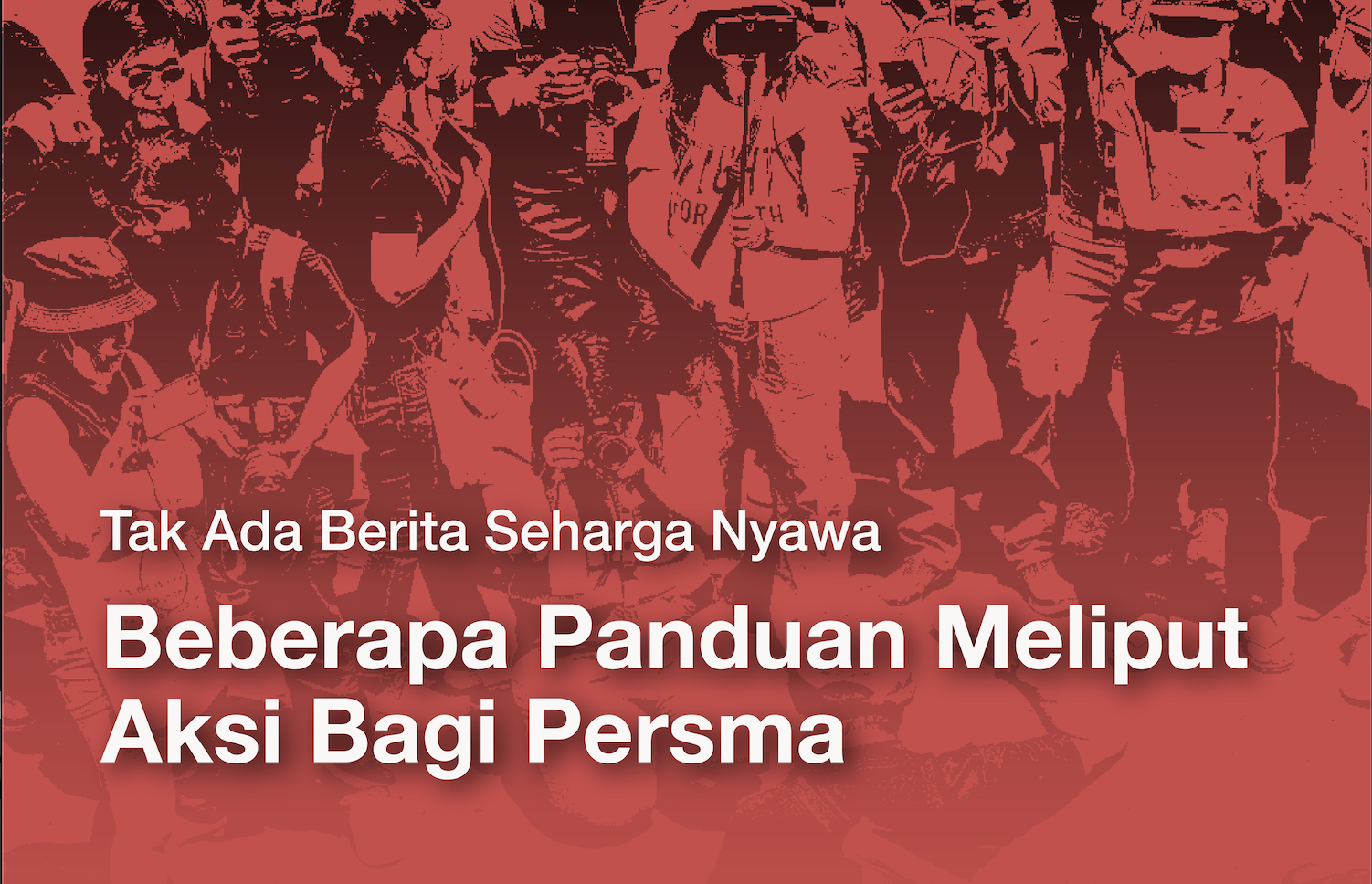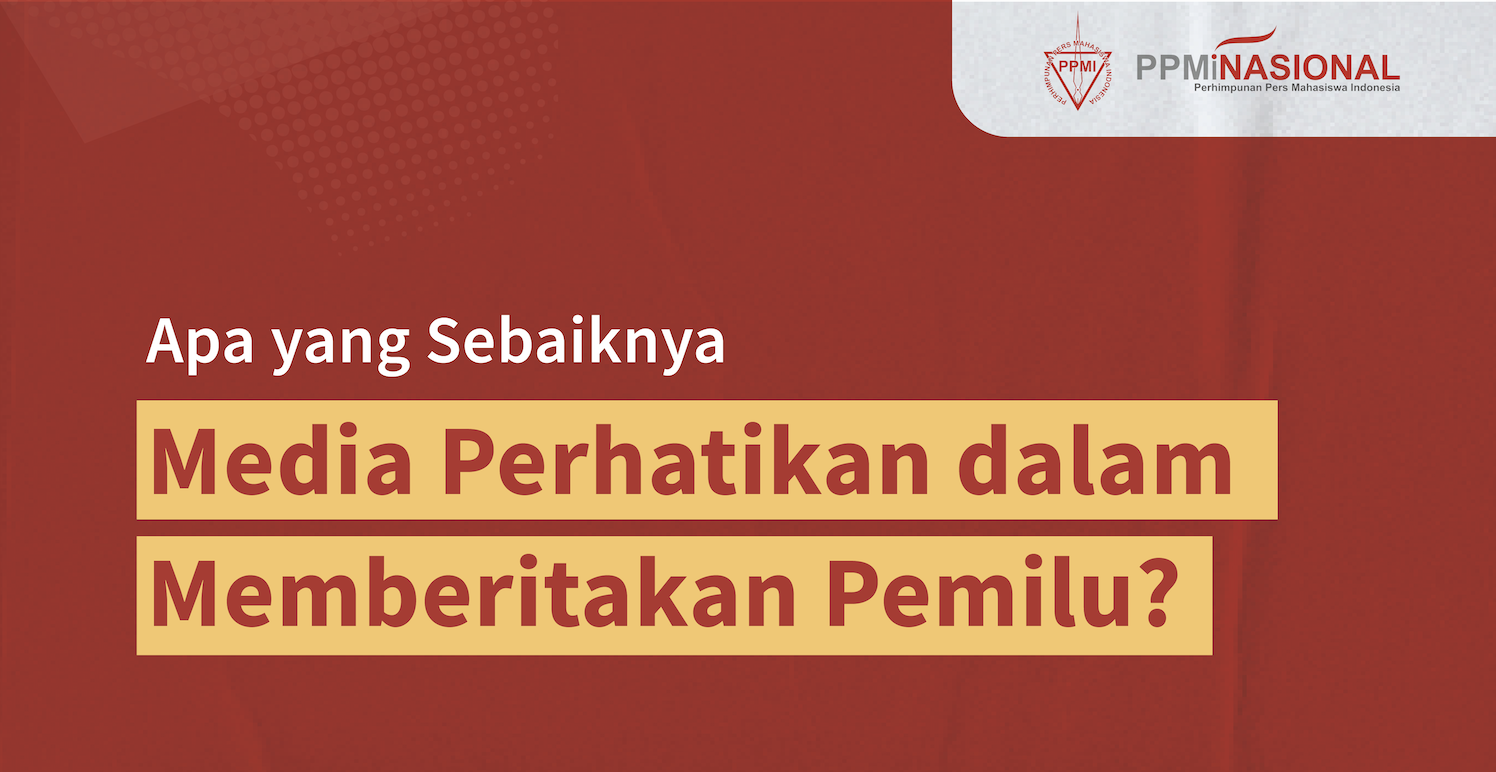Tidak berlebihan rasanya kala Jarar Siahaan, mantan redaktur koran harian Jawa Pos Grup di Medan, menyebut bahwa tugas jurnalis laiknya menjalankan fungsi kenabian. Di antara yang ia sampaikan adalah jurnalis dapat membidani sejarah, menyebarkan kebajikan, membela kebenaran, memperjuangkan keadilan, membongkar kejahatan, dan mencerahkan pikiran. Dalam tataran paling dasar, itu merupakan tugas sehari-hari seorang jurnalis yang nantinya akan menghasilkan luaran bermacam rupa. Fungsi-fungsi tersebut akan membawa jurnalis melewati kerja-kerja pencarian berita yang menyeluruh, berimbang, dan disiplin melakukan verifikasi.
Predikat tugas kenabian itu akan gugur apabila jurnalis melewatkan salah satu tahap saja. Tidak terkecuali pers mahasiswa yang merupakan bagian dari ekosistem pers. Bukan karena mereka mahasiswa-bekerja secara sukarela, dianggap sedang main jurnalistik-jurnalistikan-lantas tidak dikenakan konsekuensi tugas mulia tersebut, tetapi siapa saja yang mengenyam predikat pers cum jurnalistik, tugas kenabian itu sesungguhnya melekat di dalam dirinya. Kendati, peran pers mahasiswa acap kali direduksi dan dipandang sebelah mata hanya karena mereka masih mahasiswa. Ya, sesederhana itu.
Padahal, apabila ingin sedikit meromantisasi, pada periode kelam dunia pers Indonesia lantaran pembatasan-pembatasan yang begitu ketat oleh rezim, pers mahasiswa muncul sebagai media alternatif yang mengedarkan berita dan wacana kritis di tengah masyarakat. Di era kiwari seperti saat ini, sebenarnya pers mahasiswa masih dianggap sebagai media alternatif yang mampu bersaing dengan media arus utama yang konon terverifikasi itu. Apalagi, pers mahasiswa yang luwes, tanpa ada kepentingan akumulasi kapital, dan dekat dengan isu publik–dalam hal ini pendidikan tinggi–yang tidak mungkin semua isunya diangkat oleh media arus utama, harusnya menjadi momentum untuk lebih progresif dan menghasilkan liputan yang “berdampak”.
Masih begitu segar di ingatan tentang peristiwa awak LPM Lintas dipolisikan oleh kampusnya sendiri, IAIN Ambon, karena menguak fakta terkait dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus dan dianggap mencemarkan nama IAIN Ambon. Saat itu, LPM Lintas menerbitkan majalah berjudul IAIN Ambon Rawan Pelecehan edisi 14 Maret 2022 yang berisi laporan investigasi 32 kasus kekerasan seksual di IAIN Ambon periode 2015-2021. Selain mempolisikan beberapa anggota LPM Lintas, pihak kampus juga menerbitkan surat pembekuan yang membuat aktivitas LPM Lintas terpaksa berhenti. Padahal, kalau kampus yang mengklaim sebagai “Institute Agama Islam” itu bijak dan arif dalam merespons laporan jurnalistik, harusnya temuan LPM Lintas bisa dijadikan bahan awal untuk mewujudkan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Namun, sikap kampus itu jauh panggang dari api: bar-bar dan tidak mencerminkan sikap kedewasaan perguruan tinggi dan semangat dalam mewujudkan Islam Kaffah sebagaimana Islam yang dicatut di nama kampus mereka. Ibaratnya, IAIN Ambon ingin Jumatan, tetapi dia salat di hari Sabtu. Tersesat jauh hidupnya.
Kasus Lintas ini baru satu dari sekian banyak kasus represi yang menimpa pers mahasiswa karena aktivitas jurnalistiknya. Berdasarkan laporan dari PPMI Nasional, sejak tahun 2013-2021, terdapat tren peningkatan represi terhadap pers mahasiswa.
Peningkatan tersebut cukup tajam setelah pada periode 2017-2019 ‘hanya’ terdapat 58 kasus represi yang tercatat dan kemudian meningkat menjadi 185 kasus represi yang tercatat pada periode 2020-2021. Pereduksian pers mahasiswa bisa datang dari mana saja, kasus terbanyak dilakukan oleh birokrat kampus (48), sesama mahasiswa (16), dan Badan Eksekutif Mahasiswa/Dewan Eksekutif Mahasiswa (12).
Bentuk represinya pun beragam dengan yang paling banyak berupa teguran (81), pencabutan berita (24), dan makian (23).
Fenomena represi yang dialami pers mahasiswa ini tidak boleh dinormalisasi, meski sesama pers mahasiswa persoalan ini selalu menjadi sajian utama di forum diskusi: bahwa pers mahasiswa direpresi karena kesalahannya sendiri. Ya, memang harus diakui masih ada pers mahasiswa yang melakukan kesalahan, berupa tidak melakukan verifikasi, menulis berita hanya berdasarkan sentimen dan opini pribadi, tidak menerapkan asas praduga tak bersalah terhadap “subjek” yang diduga melakukan kejahatan, dan aneka umpan yang pers mahasiswa pasang sendiri agar disantap oleh “mereka”. Namun, bukan berarti merepresi pers mahasiswa boleh dilakukan ketika mereka melakukan kesalahan, kembali lagi: kalau yang bermasalah berita atau aktivitas jurnalistik, langkah yang dilakukan, ya, diselesaikan dengan mekanisme pers. Itu!
Diskursus ini menurut saya penting dibahas di barak pers mahasiswa: peningkatan kapasitas awak dan menjadikan kode etik jurnalistik sebagai pegangan ketika melakukan aktivitas jurnalistik. Sembari kita terus mengupayakan payung hukum yang selama ini diperjuangkan agar bisa menjamin aktivitas jurnalistik dan perlindungan bagi pers mahasiswa secara komprehensif.
Meningkatkan Kapasitas itu Penting
Di saat banyak sekali pembicaraan yang mengudara tentang perlindungan hukum bagi pers mahasiswa (Persma), ada satu hal yang tertinggal di sudut-sudut kesadaran kita. Hal ini menjadi kapiran dan ironisnya, pereduksian itu datang dari diri Persma itu sendiri: kurangnya kesadaran untuk senantiasa meningkatkan kapasitas yang sampai pada waktunya bisa berakibat fatal.
Permasalahan ini membawa Persma pada suatu fenomena tersendiri. Persma tidak bisa menutup mata bahwa kurangnya kapasitas untuk menyajikan liputan yang komprehensif dapat berujung bahaya bagi mereka. Dengan perlindungan terhadap persma yang ringkih saat ini, bisa dibilang penyelamat pertama bagi awak persma adalah diri mereka sendiri. Kondisi ini menyebabkan setiap awak pers mahasiswa, mau tidak mau, harus menggenapkan pengetahuan-pengetahuan mereka terlebih dulu, baik pengetahuan sebelum, ketika, maupun setelah liputan. Sialnya, hal ini banyak terabaikan lantaran Persma kerap kali disibukkan dengan kerja-kerja klasik organisasi, menggarap event, mengejar tenggat, lantas sudah keburu lelah untuk menambah bekal ilmu. Dan, selalu tergoda untuk menerbitkan berita “sensitif” secara terburu-buru?
Biarpun kata pepatah, pengalaman adalah sebaik-baiknya guru, sebagai bagian dari awak pers yang tidak terlepas dari etika keprofesian, Persma tetap butuh didudukkan bersama teori-teori. Kerapkali pendidikan jurnalistik pada pers mahasiswa berhenti di diklat dasar. Padahal awak pers mahasiswa berjalan dari pemberangkatan yang berbeda-beda, yang itu artinya perlu rancangan silabus yang optimal untuk diajarkan agar setiap awak persma memiliki pemahaman yang sama.
Pengajaran ini pun tidak boleh hanya pada masa pengkaderan, tapi juga terus sampai selesai keanggotaan. Bentuk dan cara pengajarannya dapat bermacam-macam, tidak mentok hanya pengajaran konvensional di ruang kelas. Soal ini, kita bisa diskusikan lagi lain waktu. Sebab, persoalan lain yang perlu diingat adalah barangkali kawan-kawan di kanan-kiri kita inilah yang nanti akan mewarnai dunia pers Indonesia ke depannya. Tentu kita tidak mau, di masa mendatang perusahaan-perusahaan media menyaru sebagai pemroduksi propaganda dan dikuasai oleh jurnalis bodrek, mereka-mereka yang mengabaikan panduan moralnya dalam menjalankan profesi jurnalistik.
Saya memahami gairah yang berkelindan di dalam tubuh pers mahasiswa karena saya sendiri pernah merasakannya. Mendengar selentingan ketidakberesan dari birokrat kampus, misalnya. Biasanya, sesaat kita mendapat ‘isu bagus’ yang memiliki nilai berita tinggi, kita akan menggebu-gebu membawanya ke meja redaksi. Bersemangat merencanakan dan merancang liputan. Mencari data dan berkas sana-sini, melontarkan hipotesa begitu dan begini, wawancara si itu dan si ini. Namun, barangkali ketergesa-gesaan ini justru bisa berbalik memakan kita.
Dalam konteks liputan investigasi, Andreas Harsono dalam bukunya ‘A9ama’ Saya adalah Jurnalisme, membeberkan meski ukuran waktu bersifat nisbi, tetapi sebuah karya investigasi memakan waktu pengerjaan yang cukup lama. Karya investigasi tidak dimulai dari sebelum terjun ke lapangan, tapi jauh sebelum itu. Liputan investigasi dimulai sejak desas-desus beredar, lalu pencarian data-data awal dan pengajuan hipotesa, merekonstruksi kejadian, hingga pada akhirnya menjadi liputan yang utuh. Agar menjadi liputan yang berdampak, liputan investigasi butuh ketelatenan yang memakan waktu.
Dalam liputan investigasinya yang berjudul Bre-X: Sebungkah Emas di Kaki Langit, Bondan Winarno, seorang jurnalis lepas bercerita bahwa ia memerlukan waktu dua bulan penuh untuk menyelesaikan liputan tersebut. Menengok ke Tempo, kantor berita yang sudah menghasilkan banyak sekali liputan investigasi, menurut pengakuan jurnalis-jurnalisnya, juga menguraikan pernyataan yang kurang-lebih serupa.
Kita, pers mahasiswa, memang tidak bisa membandingkan diri dengan Bondan Winarno atau Tempo yang telah malang-melintang di dunia pers Indonesia, khususnya peliputan investigasi. Namun, kita bisa mencontoh satu pakem watak dari mereka, yaitu tenang dan tidak grasak-grusuk. Bondan dengan tekun bolak-balik Calgary-Toronto lalu Jakarta-Manila kemudian Samarinda-Balikpapan-Busang agar dapat merekonstruksi temuannya secara utuh. Pun dengan Tempo yang berhati-hati menggeledah berkas-berkas, menelusuri data-data, melakukan lobi-lobi receh sampai tingkat tinggi. Semua dilakukan dengan tenang dan tidak jarang secara senyap.
Entah berapa kali, tapi yang pasti setiap pers mahasiswa pernah bersinggungan dengan liputan investigasi. Tentang ini, sampai sekarang, saya masih teringat akan satu hal. Saat itu, di kampus terdengar selentingan adanya ketidakberesan dari suatu event yang digelar oleh salah satu UKM. Lama tidak diurai, kerunyaman itu berujung pada perang dingin antar beberapa UKM yang berkaitan. Mendengus hal tersebut saya tergugah dan mengajak salah seorang rekan untuk menelusurinya. Kebodohan saya tiada tanding karena di hari pertama saya mendengar kabarnya, saya langsung bernafsu untuk mewawancarai pihak-pihak yang bersengketa. Tanpa pegangan latar belakang, profil, atau duduk sengkarut masalahnya. Hingga pada akhirnya, entah harus senang atau sedih, permintaan wawancara saya untuk kedua pihak ditolak. Kelak saya menyadari, andaikan liputan itu saya teruskan dengan kapasitas yang alakadarnya pada saat itu, besar kemungkinan saya akan terjerumus dalam bahaya.
Menjalankan liputan investigasi tanpa bekal dan persiapan yang matang hanya akan membawa jurnalis pada pengabaian terhadap kode etik jurnalistik. Kita akan mudah hilang kesabaran, ketekunan, dan yang paling berbahaya, hilang keteguhan. Analoginya seperti kita menaiki tangga gantung vertikal yang harus dititi satu per satu. Sebutlah tangga pertama dengan mencari penyokong; mentor, dana, dlsb. Tangga kedua adalah perencanaan; tangga ketiga sebagai mencari sumber-sumber awal; dan seterusnya hingga mencapai tangga terakhir yaitu publikasi. Tidak bisa tidak kita harus menaikinya satu per satu atau tangga akan bergoyang, dan kemungkinan terburuknya kita akan jatuh. Sebuah definisi nyata dari sudah jatuh, tertimpa tangga pula.
Menurut hemat saya, pers mahasiswa tidak perlu seperti media penghamba klik lantas tergesa-gesa dan ingin menjadi yang paling terkini, tetapi hasilnya jadi terasa kitsch. Menurunkan kualitasnya demi kecepatan. Alih-alih menunggangi ombak, dengan kapasitas optimumnya, pers mahasiswa justru dapat menciptakan ombaknya sendiri. Meluapkan fakta yang dihasilkan dari praktik-praktik jurnalisme yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, perjuangan meningkatkan ketahanan diri dari represi akan muspro kalau tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas individu. Sebab, seandainya pun payung hukum untuk pers mahasiswa sudah ada lalu dikemudian hari terjadi konflik, apabila sejak awal kerja-kerja dibalik liputannya sudah keliru, tetap akan sukar untuk mengadvokasinya.
Untuk itu, tidak ada salahnya menarik langkah mundur sebentar untuk kemudian melenting dengan ilmu-ilmu yang sudah genap. Kapasitas individu ini nantinya berkorelasi dengan kapasitas kolektif pers mahasiswa itu sendiri. Kalau sudah begini, saya jadi ingat wejangan salah satu senior saya dulu, persma tidak perlu terjebak dari hiruk-pikuk informasi di media sosial maupun media mainstream. Sudah saatnya pers mahasiswa memiliki agenda setting sendiri yang bermuara untuk kepentingan publik. Tentu hal ini akan tercapai apabila pers mahasiswa senantiasa mawas diri dan bersedia terus mengakselerasi kemampuannya.
Penulis: Mardhiah Nurul Lathifah, pembelajar di LPM Kentingan UNS
Penyunting: Adil Al Hasan