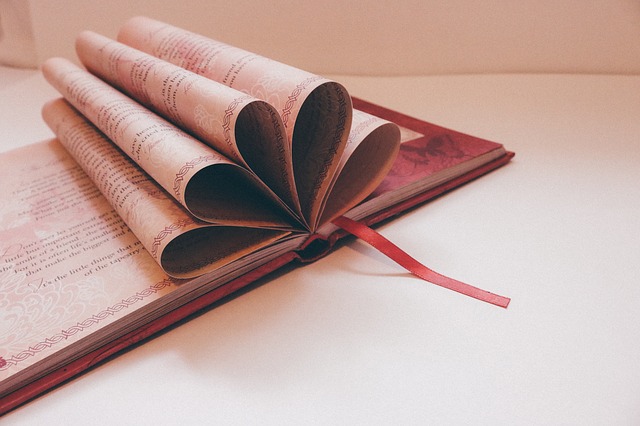Inilah provokasi untuk membangkitkan kewarasan intelektual kita. Kalimat demi kalimat yang tertulis ini merupakan rangkaian gagasan agar kita yang waras tidak melulu mengalah kepada para fasis naif. Merenungi dua kasus pembubaran forum diskusi dalam tempo tahun 2015 ini. Terjadi di dua kota: Semarang dan Yogyakarta. Korbannya, sama-sama sekawanan pers mahasiswa (persma). Namun kepentingan gagasan ini ditulis bukan semata membela persma. Mengingat kejadian nahas tersebut bisa menimpa siapapun yang waras. Atasnama kewarasan intelektual, gagasan ini mendesak untuk ditulis, dibagi, dibaca, lalu diperjuangkan sewarasnya kita.
***
Laporan dari LPM Gema Keadilan FH Undip terpampang di laman Persma.org. Singkat cerita, sekawanan Gema Keadilan dilarang menyelenggarakan diskusi publik “LGBT dalam Sosial Masyarakat Indonesia” pada 12 November 2015. Alasan naif dituturkan birokrat kampus bahwa wacana dalam diskusi tersebut sangat sensitif. Si Rektor pun mendukung pelarangan demi menyelamatkan citra Kampus Undip menuju PTNBH. Uh, demi jualan nama kampus, kepentingan belajar sekawanan mahasiswa jadi korban! Pada sore hari kelam itu pula, Polrestabes Semarang menyegel ruang diskusi sebagai antisipasi terhadap kedatangan ormas. Yeah, makin kompak aja nih: rektor, polisi, dan ormas. Ada apa ya?
Memutar mundur waktu menuju beberapa bulan sebelumnya, kejadian nahas itu pun menimpa sekawanan LPM Natas dari Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta. Diberitakan oleh Ekspresionline.com, pada 25 Februari 2015, sekawanan Natas gagal memutar Film Senyap. Saat itu, pihak intelijen Polsek Depok Barat telah menyusup dalam ruang diskusi. Intelijen pun berujar agar Natas membatalkan pemutaran film dikarenakan akan berdatangan ormas menyerbu. Jika Natas ngeyel, polisi tidak mau bertanggungjawab mengamankan situasi. Nah lho, polisi dan ormas benar-benar kompak ya? Birokrat akademis USD pun tak digdaya menunjukkan kuasa intelektualnya dalam kampus. Natas pun memilih bubar.
Dua kasus tersebut merupakan contoh dari sekian banyak kasus represi atas forum diskusi. Itu baru contoh dari dalam kampus yang birokratnya tidak bertaji intelektual. Di luar kampus, masih banyak kelompok studi yang kena celaka. Apakah para rektor, polisi, dan ormas sedang gandrung akan zaman kegelapan?
Alangkah terpujinya bagi mereka yang bergiat membuka forum-forum diskusi lintas basis intelektual tanpa membela fanatisme ideologi apapun. Nalar kritis dan kepekaan rasa adalah penggairah mereka dalam memperjuangkan misi pencerdasan nan solutif ini. Itulah sekawanan manusia waras di tengah absurd-nya gejolak kemajemukan masyarakat kita.
Siapapun manusia waras dipersilahkan hadir meramaikan forum-forum diskusi lintas kalangan, asal saja tidak kerasukan setan sembari berkoar mengatasnamakan Tuhan atau bela negara. Apalagi jika sedang membahas kasus kemanusiaan, betapa jahanamnya jikalau para setan fasis berhasil mendobrak pintu dan merangsek dalam ruang diskusi. Adalah kesialan bagi kita yang waras apabila mengalami hal demikian. Bukannya pencerahan yang datang, malahan segerombolan boneka kerasukan yang kacau-meracau datang mengintimidasi kita.
Setan memang tidak pernah senang melihat manusia waras berkumpul untuk saling membuka pikir dan hati dalam ruang diskusi. Bagi mereka yang kerasukan, forum diskusi cerdas-waras adalah metode berbahaya yang akan menjungkalkan kangkangan stigma di atas mindset masyarakat majemuk. Jika masyarakat menjadi cerdas-waras karena sering diskusi, artinya ruang kuasa para setan fasis menjadi kian sempit. Keseragaman warna berwacana pun kian memudar. Monopoli atas rekayasa tragedi bisa saja terungkap kebenarannya. Para fasis menjadi gelap mata. Pembukaan ruang-ruang diskusi bagi kasus kemanusiaan kerap membikin sibuk para pendakwah stigma untuk membubarkannya. Itulah tugas setan!
Tindakan-tindakan lancang pembubaran forum diskusi menjadi andalan merepresi tumbuh-kembangnya kebebasan berwacana. Setumpuk pemberitaan media mencatat ada wacana-wacana tertentu dalam forum diskusi yang menjadi target represi. Ciri khasnya, wacana-wacana tersebut membawa problem pihak-pihak tertindas. Berikut barisan wacana problematik yang kerap direpresi: G30S dan Tragedi ‘65, LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender), konflik agraria, kebebasan berkeyakinan aliran minoritas, dan anekaragam wacana penindasan lainnya. Walau ruang diskusinya kerap bubar, efek baiknya ialah menebarnya wacana-wacana tersebut kepada otak-otak manusia yang penasaran. Entah hal tersebut disadari atau tidak oleh geng-geng fasis di penjuru negeri ini.
Begitu perihatin ketika mendapat kabar adanya forum diskusi yang dibubarkan. Tragedi pembubaran atau represi bentuk lain terhadap agenda diskusi bukanlah keisengan belaka. Ada sebab sensitif bagi golongan tertentu. Golongan inilah yang kerap mendaku dirinya selalu paling benar. Saking merasa benarnya, maka tidak perlu lagi adanya dikusi. Forum diskusi berpotensi menyesatkan kebenaran tunggal versi pendakwah stigma nan fasistik. Pembubaran demi pembubaran pun tak memuaskan nafsu kaum yang kesetanan ini. Jika belum puas nafsunya, para pegiat forum diskusi tak akan lepas diburu ancaman yang mengarah pada pencederaan fisik maupun psikis.
Kita yang waras tidak boleh membiarkan kelakuan tidak senonoh mereka. Forum diskusi bukanlah ajang kongkow basa-basi. Inilah ruang belajar yang tidak sesempit ruang kuliah para pembalap IPK. Dari ruang inilah kita bisa saling menjalin keilmuan, mencerahkan nalar, memadu rasa, dan membangun kepedulian kepada yang terpinggirkan. Maka terkutuklah para pembubar ruang belajar-dialogis tersebut. Aksi membubarkan forum diskusi berarti menghalangi niat baik kaum waras-intelektual belajar menganalisa persoalan sosial-kemanusiaan demi meramu solusi jitu sebelum nantinya terjun ke masyarakat. Apalagi analisa-analisa advokatif menjadi penggugah kewarasan kita dalam ruang belajar ini.
Sekali lagi, terpujilah bagi para pegiat forum diskusi. Mereka berjerih payah membuka ruang belajar kepada barisan intelektual-waras yang masih berkepedulian. Namun bila ruang-ruang belajar ini terus-menerus diberangus, akan adakah generasi cerdas-waras bangsa ini di masa depan? Barisan wacana sosial-budaya pun akan menjadi milik para tiran. Ilmu yang membebaskan akan segera mati. Bangsa ini akan menjadi bangsa boneka, bukan bhinneka!
Ini gawat. Setan-setan fasis sedang memainkan penjajahan nalar. Jika kita masuk dalam daftar calon korban, menyikapi hal ini bukan dengan cara kebanyakan update status di sosmed. Sering mengutuk para fasis via status sosmed hanya semakin menjadikan kita sebagai alay yang latah perlawanan. Itu percuma, kaum fasis bukan tandingan kaum alay!
Konflik Kepentingan
Kenapa ruang diskusi direpresi? Benarkah wacana di dalamnya begitu sensitif?
Tidak ada ruang netral. Ruang pun tidak lepas dari mainan kaum intelektual. Diskusi apapun dengan muatan wacana di dalamnya mengarahkan aktor-aktor di forum untuk megapresiasi nilai-nilai tertentu. Analogi gampangnya, kita mau kuliah aja ada kurikulumnya. Itulah yang dinyatakan barisan teoritikus mazhab kritis asal Frankfurt: kaum intelektual tidak netral. Kita yang waras punya keberpihakan. Keberpihakan yang waras ialah memihak kaum tertindas menuju pembebasan.
Nyatanya tidak semua manusia waras-intelektual. Ada geng-geng yang mendaku sensitif atas pembahasan wacana tertentu. Nah, mengatasnamakan sensitivitas siapakah itu? Ada penindasan maka ada kekuasaan. Bila wacana pengadvokasian pihak tertindas begitu sensitif hingga bikin murka, sudah pasti si pemurka itulah yang punya kuasa. Geng-geng fasis penyerbu ruang diskusi ialah barisan boneka milik penguasa tiran.
Di situlah konflik sengaja diciptakan. Kita yang waras intelektual dan mereka yang tertindas diposisikan sebagai pemantik konflik itu. Padahal ruang diskusi kita justru mengarah pada penyelesaian (rekonsiliasi) dari segala problem sosial-kemanusiaan. Sementara mereka yang fasis terus mengkontra wacana mengatasnamakan Tuhan atau bela negara.
Mau tidak mau, konflik memang mesti terjadi. Walau dalam posisi ditindas apapun, kita mesti siap berkonflik. Sosiologi mengajarkan kita bahwa perubahan sosial-budaya bisa dicapai melalui konflik dan konsensus (kesepakatan). Jika kita yang waras berkehendak mengubah masyarakat menjadi cerdas-waras, konflik harus ikut kita mainkan. Tentunya memakai dialektika nalar sehat.
Ketika geng-geng fasis mendobrak bubar ruang diskusi, marilah kita buka seluas-luasnnya di manapun. Manfaatkan ruang literasi dan konsolidasi lintas komunitas intelektual hingga rakyat tertindas. Sebarkanlah pamflet-pamflet propaganda dan dudukilah kampus-kampus yang birokratnya waras-intelektual. Bukankah di era sebelum merdeka, barisan intelektual bangsa ini juga begitu? Kenapa kita tidak meneladaninya? Ayo cetak sejarah baru, bung dan nona!
Begitulah konflik kepentingan. Kita mau menang atau terus-terusan mengalah, toh anak-cucu kita yang akan mengapresiasi kita sebagai: pahlawan atau pecundang. Apapun konflik yang kita mainkan, kepentingan kita yang waras tetap membebaskan orang-orang tertindas.
Gugat Otoritas Pendidikan
Kita hidup bernegara kan ya? Negara mengakomodir segala otoritas di bawahnya, termasuk urusan pendidikan. Tidak perlu disebutkan barisan pasal hukum yang menjamin kebebasan, HAM, dan pendidikan. Negara ini punya seabrek pasal begituan yang urusannya dibagi-bagi ke beberapa otoritas di bawahnya. Mari kita yang waras bicara praksisnya saja. Nyatanya teks-teks konstitusional yang mengklaim perlindungan kepada rakyat itu belum begitu sakti menghalau para fasis.
Pemimipin-pemimpin otoritas sedang terlelap? Atau gandrung romantisme zaman kegelapan?
Kampus-kampus sudah bolak-balik diserbu fasis. Beritanya pun mengemuka di media massa. Urusan pendidikan tinggi ada menterinya tapi entah apa manifestonya. Ini nama Kemenristekdikti itu: Prof. H. Mohamad Nasir, Ph. D., Ak. Apapun tetek bengek gelar akademisnya, panggil sewajarnya saja Pak Nasir. Tentunya kita yang waras, menghormati otoritas dari kiprahnya bukan dari seabrek gelar itu.
Semoga Pak Nasir pernah membaca pembukaan UUD 1945. Ada manifestasi mulia berkalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Lantas ketika fasis-fasis mengacau di kampus, sepaktkah Pak Nasir? Apakah otoritasnya akan mengutuk aksi kesetanan itu?
Ketika kaum intelektual waras menggandeng kaum tertindas berdiskusi-belajar bersama lalu segerombolan fasis berdatangan menghajar, otoritas pendidikan cenderung memilih duduk nyaman. Apa kita mesti mengganti Pak Nasir dengan Arian (vokalis band Seringai) sebagai Menristekdikti?
Arian, si vokalis grup musik cadas kerap menyuarakan manifesto anti fasis pada momen-momen konser Seringai. Banyak penggemar cadas mengamini propagandanya. Malah lebih sering Arian dibanding Pak Nasir yang lantang bersuara untuk melawan bahaya fasisme. Mungkinkah posisi Menristekdikti kena reshuffle? Ini bisa jadi usulan waras kepada Presiden yang ngakunya juga metalhead. Itu pun kalau Arian mau jadi menteri, kalau tidak?
Otoritas pendidikan mestinya jadi teladan untuk menyetop aksi-aksi represi ruang diskusi. Tempo dulu, seorang teladan pendidikan bangsa: Ki Hadjar Dewantara, pernah menuliskan gagasan untuk melawan represi dunia pendidikan. Ada tulisan bertempo Agustus 1933, judulnya demikian “Tabiat Pengrusak Lahir dan Pengrusak Batin. Vandalisme dan Terrorisme”. Ki Hadjar menggagas bahwa aksi-aksi beringas yang mencederai hak orang lain identik sebagai terorisme batin. Para pelakunya ialah orang yang merasa benar sendiri dan sifat demikian hanya dimiliki anak-anak berkisar usia 4-8 tahun. Berarti para fasis penyerang forum diskusi begitu kekanak-kanakan. Kita yang waras harus berkonfik melawan anak-anak?
Ki Hadjar bernasihat bahwa kita yang terdidik semestinya mampu menyingkirkan sifat perusak itu lewat jalan pendidikan. Lebih lanjutnya, bisa dibaca di buku kumpulan esai “Bagian Pendidikan” terbitan Majelis Luhur Taman Siswa. Apakah Pak Nasir tertarik membacanya?
Mendiamkan otoritas pendidikan yang abai akan represivitas sama saja menggali kubur kewarasan intelektual kita sendiri. Marilah kita yang waras mendesak Pak Menteri lebih dulu. Mungkin dia pun diam-diam sedang mengamati kita. Bisa saja Pak Menteri sedang menunggu anak bangsa terdidik bertumpahdarah ria, hingga ia mau turun berjuang bersama kita.
Lagipula kita punya hak sah untuk menggugat-mempertanyakan keberpihakan Kemenristekdikti. Di posisi siapakah otoritas itu berdiri? Kita punya tata cara waras, undanglah dia ke kampus atau kita gedor berkali-kali pintu kementerian dengan gelegar suara kritis pinggiran kita. Biar mata otoritas kian melek, lemparkan setumpukan literasi kritis ke wajahnya, maksudnya: ayo kita nulis!
Itulah cara menggugat kita. Mau menggugat atau kita angkat saja Arian sebagai menteri! Semoga Ki Hadjar Dewantara merestui.
Jalan Pembebasan
Forum-forum diskusi kerap menghadirkan permasalahan sosial-kemanusiaan. Selain sebagai ruang pemahaman, forum diskusi mestinya tidak netral begitu saja. Jika sekawanan terdidik mengundang kaum yang ditindas untuk berbagi persepsi di dalam forum, tentunya itu bukan sekedar forum narsisnya moderator, berbagi kacang dan kopi, atau numpang ngerokok. Di ruang inilah orang-orang waras mendidik dirinya melalui dialog untuk mengaksikan misi pembebasan. Katanya Paulo Freire, pemikir pendidikan asal Amerika Latin, manusia yang saling berdialog akan memanusiakan diri sendiri.
Pemebebasan bermaksud melepaskan korban penindasan dari belenggu tiran. Pendidikan yang memanusiakan mestinya begitu. Kita yang waras, mengakses pendidikan bukan untuk lifestyle belaka. Jika pendidikan adalah gengsi gaya hidup, kapan bangsa ini cerdas? Forum diskusi sebagai ruang belajar adalah jalan ideal pembebasan. Mempertemukan korban penindasan dengan intelektual-waras secara dialogis adalah ajang belajar nan saling mencintai. Itu katanya Mbah Freire!
Revolusi memang gak harus bertumpah-tumpah darah. Dimulai dari cinta dan dialog, kita yang waras bisa mengubah dunia menjadi cerah. Dialog tercipta atas motif cinta akan pembebasan kemanusiaan. Belenggu orang-orang tertindas bisa disingkirkan jika kita duduk satu ruang bersama, membangkitkan kesadaran mereka. Freire memikirkan demikian dalam karya klasiknya “Pedagogy of The Oppressed”. Tidak perlu bingung, karya tersebut sudah diterjemahkan ke banyak bahasa lokal bangsa, misalnya Bahasa Indonesia. Mari kita pelajari pemikirannya lalu berjuang sewarasnya!
Bayangkan saja, berapa kali forum diskusi harus kita giatkan mengingat bangsa ini multiproblema dari kelas elit hingga akar rumput? Wacana-wacana diskusi semacam LGBT dan Korban 65 saja kerap direpresi. Apapun represinya, dialog harus terus jalan. Ruang-ruang diskusi harus tetap terus terbuka walaupun setan-setan fasis bergentayangan. Bila dibubarkan, jangan kapok! Masih banyak orang waras di negeri ini.
Saatnya menggandeng solidaritas. Bila memang ruang-ruang tatap muka kerap direpresi, masih ada ruang lain yang memungkinkan menjalin gagasan dan solidaritas: literasi. Zaman sudah begitu digital yang harusnya memudahkan timbal-balik karya literasi advokatif. Masalahnya, sekawanan yang mengaku pegiat literasi garda depan apakah masih peka otak dan rasa untuk menulis? Duh, kritik kepada sekawanan persma nih!
Siapapun kita yang masih merasa waras ini, entah ngikut persma, organ ekstrakampus, dan barisan kelompok studi lainnya, bukan waktunya jadi aktivis narsis, pemalas, sekaligus alay! Ruang diskusi-belajar kita sebagai jalan pembebasan kaum tertindas sudah dirusak geng-geng fasis.
Apa masih mau keranjingan update status sosmed? Apa masih cukup penting pasang foto profil mengenakan seragam organisasi? Apa masih etis kita ngafe sembari latah bersuara keras ngomongin organisasi supaya pengunjung kafe lain memperhatikan? Apa waras bila keseringan mengupload foto gaya mengacungkan jari tengah? Betapa jancuknya kita kalau masih begitu. Itu sih barisan penonton music show di stasiun televisi juga bisa.
Ruang belajar hampir direbut fasis sepenuhnya. Jalan pembebasan hampir diblokir. Kaum tertindas semakin miris meratap. Kita yang waras harus membebaskannya. Ingat, kaum alay bukan tandingan kaum fasis! Mari bung dan nona rebut kembali!