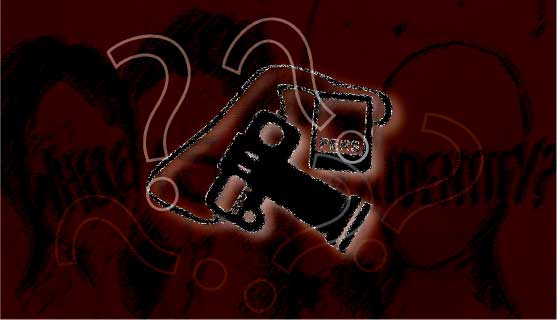
Beberapa hari belakangan, saya mengikuti satu peristiwa yang melibatkan jurnalis Detikcom. Dia menulis soal kebutuhan seksual dari istri Jrinx, yaitu Naura. Kejadian itu mengundang banyak kritik dari netizen setelah Naura mengunggah tangkapan layar dari isi percakapannya dengan si jurnalis. Reaksi jurnalislah yang mengundang banyak kecaman, seperti:
“Maaf mbak, salah saya dimana ya?”
Dalam satu garis waktu, produk jurnalistik yang muncul di layar saya semakin tidak karuan. Selain judul tulisan dari Detikcom tadi, ada banyak judul-judul sejenis yang muncul ke beranda. Kebetulan, halaman pembuka dari browser saya adalah MSN, yang mengkurasi banyak berita yang sedang banyak dibaca orang. Hasilnya? Tak jauh berbeda.
Tidak bisa saya pungkiri, tulisan-tulisan nyeleneh yang banyak keluar dari media-media, terutama yang berbasis online, adalah hasil dari tingginya tuntutan kepada jurnalis untuk menghasilkan tulisan yang dibaca banyak orang. Semakin bombastis judulnya, semakin banyak diklik orang. Semakin banyak diklik orang, semakin banyak iklan yang ingin tampil di halaman depan. Semakin banyak iklannya, semakin banyak uang yang didapat. Pada akhirnya, media bukan menghamba kepada masyarakat, tapi justru malah menghamba kepada SEO atau peringkat Alexa.
Kejadian demi kejadian serupa akhirnya memantik banyak diskusi liar di media sosial. Diskusi tersebut, kebanyakan mempertanyakan “Bagaimana masa depan media dan jurnalisme”. Sebagai orang yang aktif di pers mahasiswa empat tahun belakangan, rasanya saya juga gatal untuk mengomentari kejadian ini.
Pers mahasiswa tidak bisa dihilangkan begitu saja dari berbagai kejadian belakangan ini, terutama setelah masa banjirnya informasi. Karena, walau bagaimanapun, para wartawan yang hari ini bekerja untuk memberi informasi kepada publik—mungkin—adalah alumni dari pers mahasiswa. Kalau media mainstream saja kelimpungan untuk mencari dana sampai harus mengorbankan kualitasnya, apalagi pers mahasiswa?
Mencoba menghindari kekangan birokrat kampus lewat pendanaan
Sudah lazim dimengerti bagi para insan pers mahasiswa, dana dari kampus adalah sumber keuangan utama yang bisa mereka dapatkan. Dana itu dianggarkan dari kampus setiap tahunnya, dan digunakan untuk kelangsungan berbagai kebutuhan pers mahasiswa selama satu tahun berikutnya. Jumlahnya pun bervariasi, tergantung apakah pers mahasiswa berdiri di tingkat kampus, atau fakultas. Bisa saja tergantung keras-lunaknya pers mahasiswa kepada birokrat.
Tidak asing bagi saya mendengar penurunan dana setiap tahun dari birokrat karena kerasnya pers mahasiswa kepada birokrat, karena saya mengalaminya. Alokasi dana bisa turun 50-70% setiap tahunnya, itu belum termasuk pemangkasan-pemangkasan lain jika pers mahasiswa ingin melakukan kegiatan tertentu. Alasannya selalu klise: pers mahasiswa tidak menghasilkan prestasi (biasanya birokrat membandingkan pers mahasiswa dengan organisasi lain yang bertolak ukur kepada piala), dan malah justru membuka borok kampus.
Dalam menghadapi pendanaan yang seret dari kampus, pers mahasiswa dihadapkan kepada pilihan yang sulit. Apakah harus melunak kepada birokrat dengan cara mengikuti lomba (atau bahkan membuat lomba), meliput ‘keberhasilan’ kampus (dan menjadi humas kampus), atau mencari dana sendiri untuk membiayai berbagai kebutuhan selama satu periode kepengurusan. Tentunya, pilihan-pilihan di atas memiliki kesulitannya masing-masing, dan tidak mudah untuk memilihnya. Di antara berbagai macam pilihan tersebut, -yang saya lihat- mereka cenderung memilih opsi ketiga: mendanai secara mandiri dan tetap pada pendirian mereka sebagai organisasi independen.
Mungkin saja, banyak pers mahasiswa yang memiliki dana yang cukup atau bahkan lebih dalam tiap tahunnya, sehingga paragraf-paragraf di atas tidak relate dengan keadaan mereka. Namun ada satu pertanyaan saya: apakah itu bisa menjamin keberlangsungan pers mahasiswa ke depan?
Kita tidak pernah tahu seperti apa masa depan yang akan dihadapi. Tiga tahun yang lalu, siapa di antara kita yang menyangka, kalau roda-roda organisasi—dan kehidupan pada umumnya—akan direm secara darurat karena sebuah pandemi sialan? Karena dari itu, sudah saatnya bagi pers mahasiswa untuk memiliki badan usaha sendiri, lalu secara perlahan bebas dari ancaman dana dari kampus atau dari kejadian tidak terduga seperti pandemi, sehingga menjadi independen dan mandiri secara kaffah.
Tapi bagaimana caranya? Mungkin caranya berat. Seperti apa langkah menuju ‘independen dan mandiri secara kaffah’?
Perlakukan pers mahasiswa semirip-miripnya dengan perusahaan media bekerja
Banyak yang harus dipertimbangkan oleh pers mahasiswa—terutama yang sudah maju atau sedang berkembang—untuk merubah gaya kerja, dari organisasi menjadi ‘selayaknya’ perusahaan media yang ada. Terlebih, jika kita bicara soal finansial. Saya pikir, dalam proses bekerja sebagai media, pers mahasiswa sudah bisa disamakan dengan media profesional—bahkan lebih bagus hasilnya dari beberapa media yang ada sekarang.
Dalam pengelolaannya selama ini, pers mahasiswa kebanyakan dikelola sebagai sebuah organisasi kemahasiswaan. Dikelolanya pers mahasiswa sebagai sebuah organisasi, menurut saya, dapat mengurangi marwah pers mahasiswa yang digadang-gadang sebagai media alternatif. Ada banyak aspek yang lebih-kurang mempengaruhi pers mahasiswa yang berkaitan dengan alur kaderisasi dan produktivitas.
Aspek yang paling dasar dalam pengelolaan pers mahasiswa adalah terikatnya dengan aturan-aturan kampus tentang organisasi kemahasiswaan. Aturan-aturan tata kelola semacam ini bukan hal yang tidak umum di kampus. Misalnya, dalam tahun kedua, anggota pers mahasiswa akan otomatis menjadi pengurus. Pada tahun ketiga akan menjadi pimpinan, lalu selanjutnya demisioner, dst. Apalagi dalam setiap jabatan mengandung berbagai tanggung jawab yang tidak mudah.
Tanggung jawab itu, yang mungkin saja hanya karena kewajiban untuk mengikuti aturan tata kelola dari kampus, memakan banyak tenaga sehingga anggota pers mahasiswa tidak fokus kepada media—yang menjadi aspek utama di dalam pers mahasiswa. Alur kaderisasi pers mahasiswa—yang paling lama saya tahu adalah satu tahun—juga kebanyakan berhenti di tahun pertama. Di dalam dunia media yang selalu berimprovisasi terhadap perubahan tiap tahunnya, treatment ini sudah seharusnya dipikirkan ulang untuk diubah.
Bukan berarti anggota pers mahasiswa harus menjabat lebih lama. Bukan pula pers mahasiswa butuh waktu kaderisasi yang lebih lama. Tetapi yang menjadi fokus perhatian bagi saya adalah, lama waktu belajar tidak menjamin anggota pers mahasiswa tanggap terhadap perubahan. Improvisasi signifikan atas cepatnya perubahan tidak akan terjadi apabila kita masih menunggu satu periode kepengurusan untuk merubahnya. Maka itu, proses pembelajaran di pers mahasiswa harus dinamis dan tidak terpaku kepada satu waktu saja.
Inkompetensi pers mahasiswa dalam menanggapi berbagai perubahan—terutama dalam produk dan cara mereka bekerja—hanya akan membuat mereka berputar-putar di dalam lingkaran permasalahan yang sama tiap tahunnya. Pada akhirnya, yang menjadi fokus bertahun-tahun untuk pers mahasiswa adalah bukan pada produk dan gaya baru untuk mengelola organisasi, tetapi lebih kepada cara-cara klasik berorganisasi, seperti keaktifan anggota, kekurangan anggota, atau anggota yang tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya.
Karena pers mahasiswa bukan organisasi biasa
Setelah disadari bahwa pers mahasiswa tidak memiliki tolak ukur seperti piala atau sertifikat, dan ada banyak hal yang harus dirombak dalam cara pengelolaan pers mahasiswa untuk menghasilkan produk yang lebih baik, sudah saatnya kita mulai banyak berdiskusi tentang bagaimana pers mahasiswa seharusnya dikelola.
Ada satu kata yang agak berat jika diucapkan ini kepada pers mahasiswa, tapi hal itu sangat dibutuhkan. Kata itu adalah profesionalisme. Namun perlu diingat, profesionalisme tidak akan dicapai apabila seseorang tidak ahli di bidangnya, dan seseorang itu tidak akan bisa ahli di bidangnya apabila ia tidak mendapatkan pengalaman belajar yang baik. Sialnya, anggota pers mahasiswa tidak seperti pekerja di perusahaan-perusahaan media yang digaji. Anggota pers mahasiswa adalah seorang relawan/volunteer, dan tidak setiap pers mahasiwa paham akan posisi ini.
pers mahasiwa cenderung untuk meminta anggotanya untuk loyal dan all-out, tapi alfa dalam memikirkan apa yang bisa mereka berikan kepada anggota yang sudah dengan rela menyisihkan waktu dan tenaganya. Di sinilah letak perbedaan besar pers mahasiswa dengan organisasi biasa, bahkan dengan perusahaan media sekalipun. Pers mahasiswa harus merancang sendiri pencapaian dan pengalaman belajar yang harus dicapai para anggotanya. Selain harus memikirkan produk-produk yang akan mereka keluarkan—dan inovasi yang harus mereka lakukan, pers mahasiswa harus bisa menjadi fasilitator belajar yang baik bagi anggota-anggotanya.
Setidaknya ada tiga hal yang harus pers mahasiswa lakukan untuk menyelesaikan sekian masalah di atas. Pertama adalah rencana strategis (renstra), kedua adalah kurikulum, dan yang terakhir adalah silabus. Ketiga hal ini adalah hal dasar yang perlu pers mahasiswa susun untuk bersiap menjadi independen dan mandiri secara kaffah, hingga mencapai profesionalisme untuk setiap tugas anggota-anggotanya.
Rencana strategis adalah sebuah visi, grand design, tentang arah gerak pers mahasiswa dalam rentang waktu tertentu. Renstra inilah yang akan menjadi rujukan untuk setiap program kerja tahunan yang akan disusun. Dalam renstra pula pers mahasiswa menentukan, mereka akan menjadi pers mahasiswa yang seperti apa. Sedangkan kurikulum adalah penentuan proses belajar dalam pengkaderan anggota baru untuk mencapai tujuan tertentu—biasanya dalam mendapatkan kartu pers, dan silabus adalah kumpulan materi yang harus dipelajari anggota selama masa pengkaderan anggota baru.
Setidaknya, dalam menghadapi perubahan-perubahan besar yang begitu cepat, pers mahasiswa sudah memiliki modal sederhana namun berarti, yaitu tujuan dan pondasi keorganisasian yang kokoh. Dengan begitu, kondisi sesulit apapun akan berhasil dihadapi pers mahasiswa. Karena semua hal yang terlihat mustahil bukan tidak bisa dilakukan, tetapi hanya sulit. Tinggal bagaimana kita membedah apa yang menjadi kesulitan untuk menghasilkan inovasi dan gaya-gaya baru untuk mengatakan impossible is possible.

























