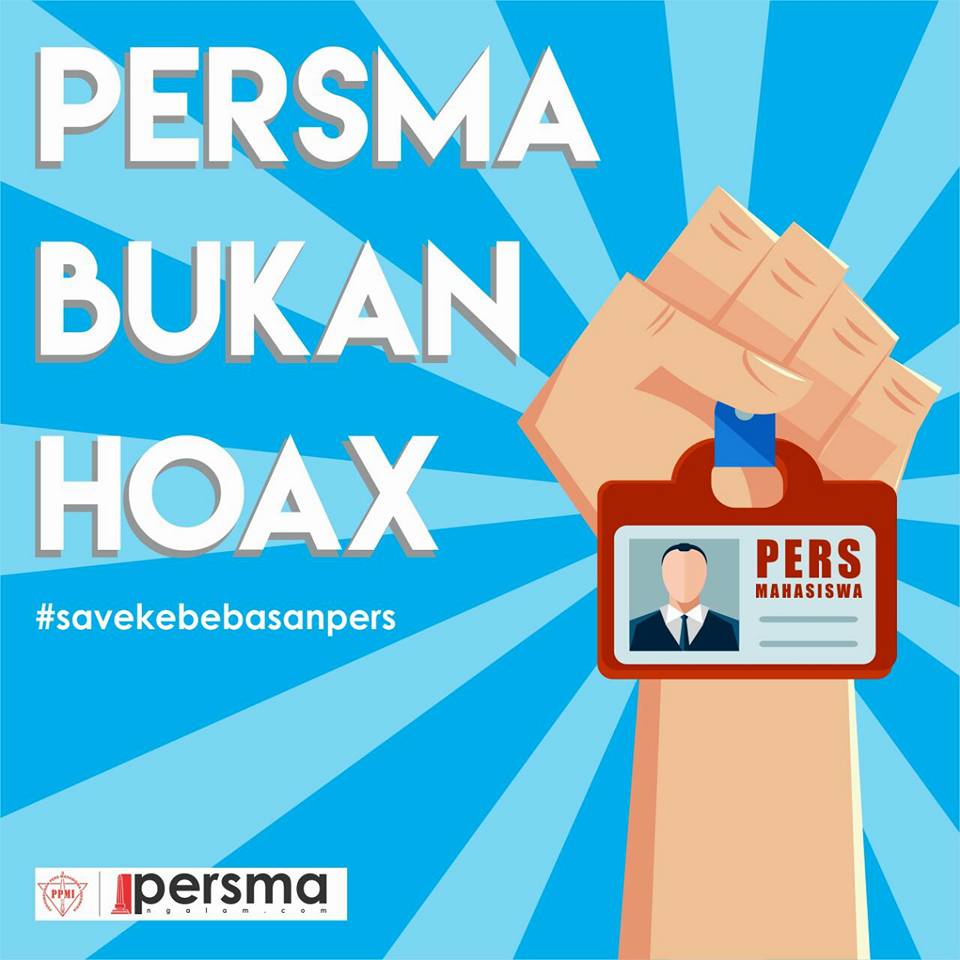Pers mahasiswa dalam perjalanannya sering kali menemui protes yang keras dari berbagai pihak, misalnya dari kalangan pejabat kampus. Mereka menilai pers mahasiswa sering melakukan kritik atas kebijakan-kebijakan kampus yang layak digugat.
Keberadaan pers mahasiswa karena lalu dianggap ancaman terhadap citra dan akreditasi kampus di mata publik. Pejabat kampus lalu nampaknya berusaha meredam gerakan pers mahasiswa, lewat upaya apapun agar pers mahasiswa tak lagi getol menyuarakan kebenaran yang dikemas dalam produk jurnalistik.
Sepanjang 2014-2015 Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) mencatat ada 5 kasus yang mengancam ruang independensi pers mahasiswa. Bentuknya beragam, mulai tindakan intimidasi, pelecehan, diskriminasi, pelarangan pemutaran film, diskusi tematik, sampai pada pemberedelan media.
Lantas siapa yang bisa melindungi ruang independensi pers mahasiswa dari sekian banyak intervensi?
Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, hingga kini jadi perdebatan menarik untuk mengamati kasus ini dari segi hukum. Pada undang-undang ini, tak disebutkan secara gamblang bahwa pers mahasiswa merupakan bagian dari pers di Indonesia. Namun dalam praktiknya, awak pers mahasiswa melakukan kerja-kerja penerbitan media, peliputan, dan kegiatan menyampaikan informasi.
Semua itu ditempuh tanpa mengabaikan kode etik jurnalistik yang ada. Pers mahasiswa memiliki produk pers.
Perhimpunan Pers Mahasiwa Indonesia (PPMI) mewawancarai Yosep Stanley Adi Prasetyo, anggota Dewan Pers periode 2013-2016. Stanley adalah pemerhati hukum. Ia juga merupakan salah satu orang yang ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).Pernah menjadi Direktur Eksekutif Institut Studi Arus Informasi (ISAI).
Sejak awal 1990 menjadi pembicara di berbagai forum. Mulai pelatihan hingga workshop dan seminar, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, dengan topik sekitar media, jurnalisme, konflik, kekerasan, HAM, dan reformasi sektor keamanan. Menjadi ombudsman di majalah Acehkita (2003-2007) dan di tabloid Suara Perempuan Papua sejak 2004 hingga sekarang. Sebanyak 67 buku telah ditulis dan dieditnya. Alamat surel: ruhoro_07@yahoo.com
Hasil wawancara ini bisa didistribusikan lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut anda bagaimana kondisi pers mahasiswa saat ini di tengah besarnya intervensi dari luar redaksi?
Belakangan ini di beberapa perguruan tinggi, pimpinan kampus dan fakultas sepertinya menganggap pers mahasiswa adalah musuh mereka. Mereka itu umumnya tidak tahu sejarah pers mahasiswa dan peranannya dalam menumbuhkan kehidupan intelektualitas mahasiswa. Pers mahasiswa sebetulnya punya sejarah panjang yang penting dalam menumbuhkan demokrasi di negeri ini.
Apakah pers mahasiswa dalam menerbitkan produk medianya sudah sesuai dengan kerja- kerja jurnalistik?
Ya, pers mahasiswa umumnya mengikuti dan mempraktekkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) meski mereka belum bisa dikatakan sebagai pers yang sepenuhnya profesional. Pers mahasiswa umumnya juga mengerjakan kegiatan jurnalistik yang sama dengan pers pada umumnya yaitu mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar serta data dan grafik maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak yang tersedia.
Kalaupun ada yang membedakannya dengan pers profesional, adalah badan hukum dan jadwal terbit yang umumnya tak secara teratur. Hal ini karena sifat alami mahasiswa yang memang harus belajar dan segera lulus sehingga pers mahasiswa kerap menghadapi problem regenerasi.
Bagaimana idealnya peran dan posisi pers mahasiswa di peguruan tinggi?
Pers mahasiswa idealnya bisa berperan sebagai alat bagi mahasiswa untuk berlatih menuangkan pikiran, menjadi alat komunikasi antar civitas kampus dan mengembangkan pendapat kampus, untuk menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi dan menghormati keberagaman, menyampaikan kritik dan koreksi, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Keberadaan pers mahasiswa di perguruan tinggi dirasa mengancam citra lembaga universitas di mata publik, bagaimana menurut anda?
Pers mahasiswa semestinya merupakan bagian dari kegiatan kampus yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa untuk melengkapi kegiatan akademis selain perkuliahan rutin. Tak ada kegiatan pers mahasiswa yang sesungguhnya mengancam universitas. Yang ada umumnya pimpinan kampus lebih khawatir kepada penguasa.
Mereka khawatir bahwa suara mahasiswa akan membuat kampus yang mereka pimpin dinilai tak loyal pada pemerintah. Mereka tak biasa berinteraksi dengan aparat keamanan yang kadang bertanya tentang sikap kritis mahasiswa. Mereka ini umumnya tak mengerti tentang bagaimana menegakkan otoritas kampus yang memiliki kebebasan akademik.
Perlu dipahami juga para pimpinan kampus sekarang ini dulunya, puluhan tahun hidup di zaman Orde Baru yang represif dan dipenuhi ketakutan yang kadang tak sadar bahwa situasi sekarang dan tuntutan jaman sudah berubah.
Dalam melakukan aktivitasnya pers mahasiswa sering kali mengalami tindakan intimidasi oleh pihak birokrasi kampus, bagaimana menurut anda?
Menurut saya, perlu ada kontrak politik baru antara pers mahasiswa dengan pimpinan kampus yang menaunginya. Mungkin hal ini perlu dilakukan melalui organisasi semacam PPMI yang harus mengembangkan sebuah divisi hukum dan juga divisi advokasi.
Bila pimpinan kampus mencederai kebebasan pers mahasiswa, maka pihak pengelola pers mahasiswa bisa mengadukannya ke PPMI yang bisa membawa ini ke Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek.
Akhir- akhir ini tindakan birokrasi kampus semakin represif terhadap pers mahasiswa, terbukti dengan adanya pembatasan ruang gerak pers mahasiswa, pemberedelan, hingga pembekuan lembaga pers mahasiswa. Bagaimana menurut anda melihat fenomena ini?
Mungkin bisa dicoba dengan melaporkannya ke polisi dan diadukan Dewan Pers. Terlepas dari pertanyaan apakah pers mahasiswa itu pers profesional, atau pers sebagaimana yang dimaksud dalam UU Pers.
Barangkali kita perlu menguji keberadaan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa:
“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan seperti penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran (sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2)) termasuk menhambat atau menghalangi pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (sesuai Pasal 4 Ayat (3)) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”
UU Pers no 40 tahun 1999 belum menyebut pers mahasiswa adalah bagian dari pers professional. Lantas bagaimana?
Memang. Dalam UU Pers dinyatakan bahwa pers harus berbadan hukum. Ada 3 bentuk badan hukum yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers No 04/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers yaitu perseroan terbatas, yayasan, atau koperasi. Hal lain adalah terbit secara rutin dan tepat pada deadline.
Aktivis pers mahasiswa juga tidak termasuk dalam definisi wartawan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Umumnya pers mahasiswa baru merupakan sebuah unit kegiatan mahasiswa yang memiliki ketergantungan tinggi pada alokasi bantuan dana dari fakultas atau universitas.
Saya kira ini kendala pers mahasiswa untuk bisa menjadi sebuah pers profesional. Sangat berbeda dengan pers mahasiswa di akhir dekade 1960-an yang bisa menjadi media profesional semacam Mahasiswa Indonesia atau Harian Kami yang akhirnya juga dilarang terbit oleh penguasa Orde Baru.
Ketika tidak diakui, apakah pers mahasiswa tidak dapat menggunakan UU pers jika pers mahasiswa mengalami permasalahan di kampus maupun diluar kampus?
Hal ini harus diuji melalui pengadilan. Untuk itu saya anjurkan apabila ada pers mahasiswa yang mendapat tekanan dari pimpinan fakultas atau kampus tempat mereka bernaung sebaginya dilaporkan ke polisi dan diadukan ke Dewan Pers. Umumnya kasus-kasus yang terjadi tidak berlanjut karena pengelolanya mundur atau berganti, atau tidak terbit lagi.
Apalagi ketika pimpinan fakultas atau universitas mengancam untuk memberikan sanksi akademis. Terlihat organisasi seperti PPMI belum berfungsi dengan baik.
Mengapa Dewan Pers sampai saat ini belum mengakui keberadaan pers mahasiswa, dan menganggap pers mahasiswa adalah ruang untuk berlatih jurnalistik serta mempersiapkan diri menjadi pers yang profesional?
Dewan Pers hanya memegang mandat sebagai pelaksana Undang-Undang Pers, khususnya Pasal 15 ayat (2). Namun, perlu diketahui bahwa setiap tahun Dewan Pers selalu mengisi acara-acara pelatihan pers mahasiswa di berbagai kampus di Indonesia sesuai permintaan. Selain itu Dewan pers juga memiliki program untuk melatih aktivis pers mahasiswa sebagai calon-calon wartawan Indonesia yang berkualitas.
Mengapa begitu?
Ya karena sesuai ketentuan peraturan perundangan yang ada, pers mahasiswa memang dikelompokan sebagai pers profesional. Mungkin tugas PPMI untuk memperjuangkan keberadaan pers mahasiswa sebagai pers profesional.
Jika pers mahasiswa tidak dapat menggunakan UU Pers, menurut anda jalur apa yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan kasus?
Yang dapat menggunakan pidana dalam penegakan UU Pers itu adalah pihak kepolisian dan hakim dalam proses pengadilan. Saya kira kita semua belum pernah mencoba apalagi menguji hal ini.
Apakah mungkin kedepannya pers mahasiswa akan diakui oleh Dewan Pers?
Kenapa tidak? Tentunya apabila UU Pers yang ada diamandemen atau diubah. Hanya saja memang selalu ada pertanyaan yaitu wartawan itu adalah sebuah profesi, apakah aktivis pers mahasiswa itu juga sebuah profesi?!