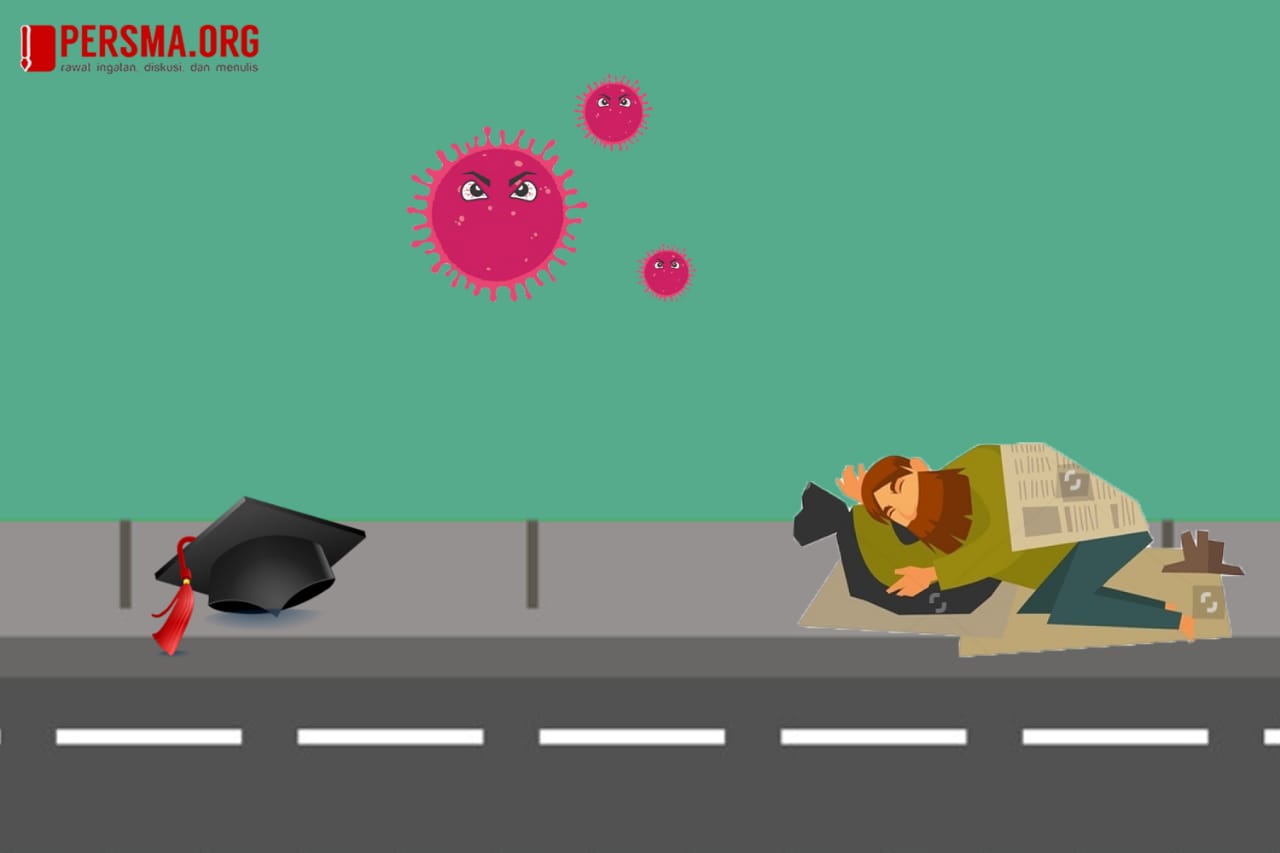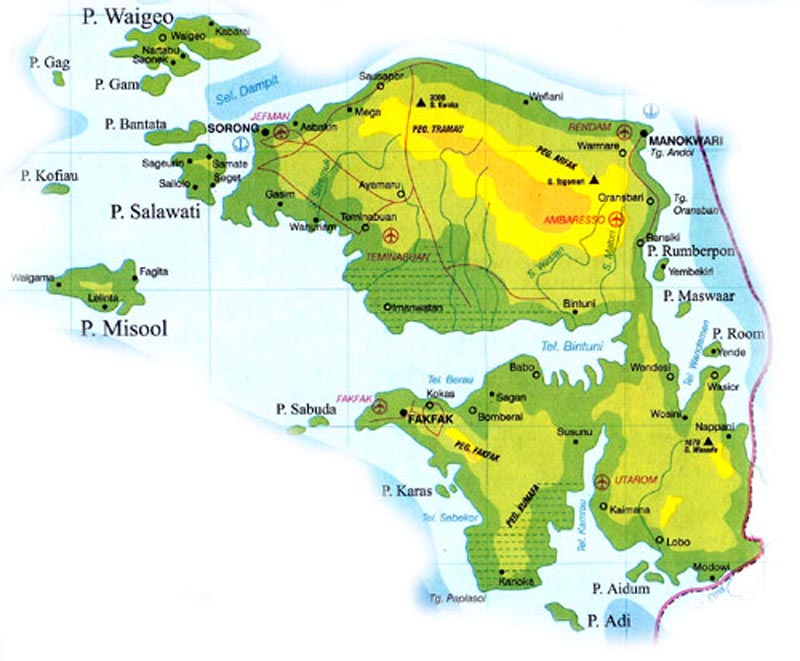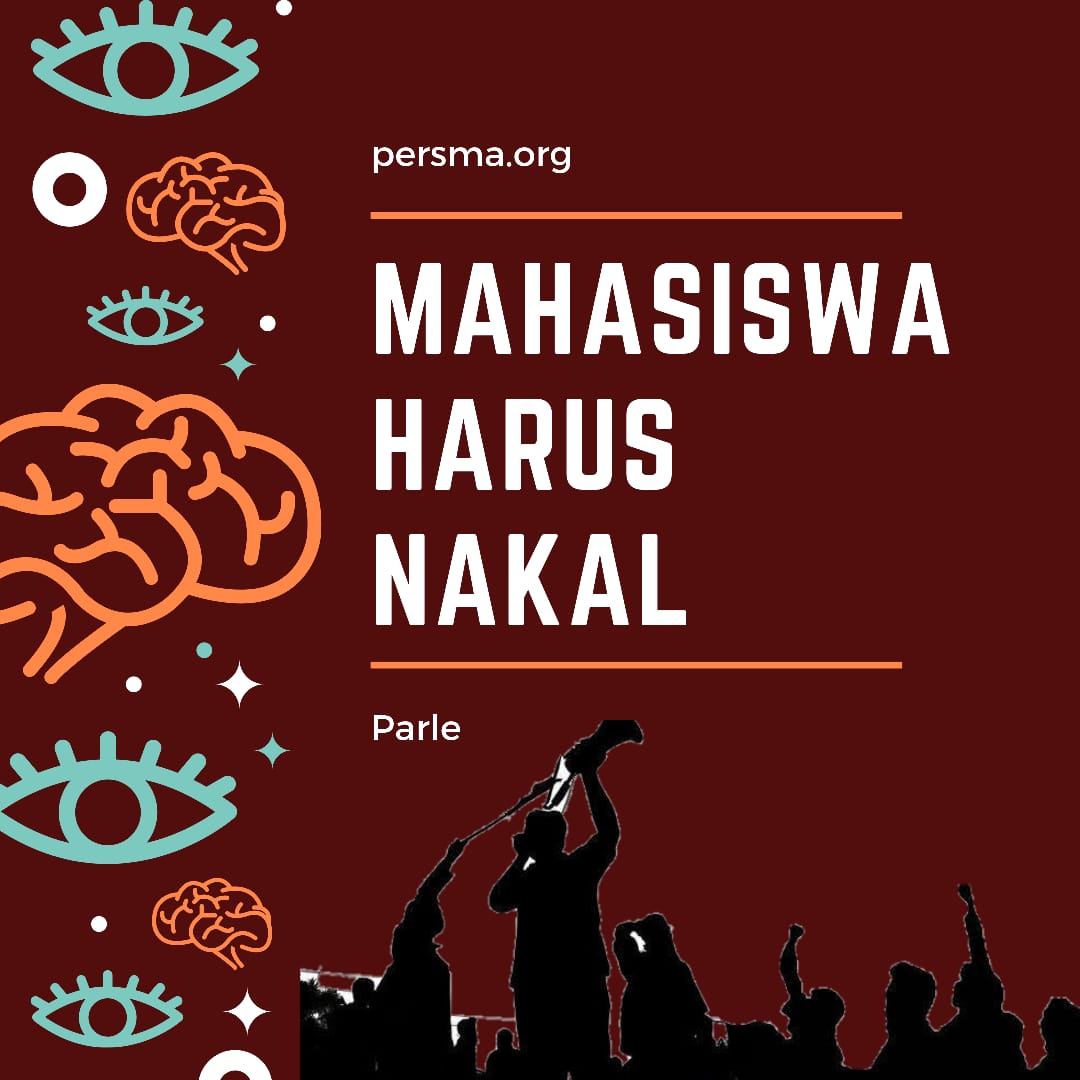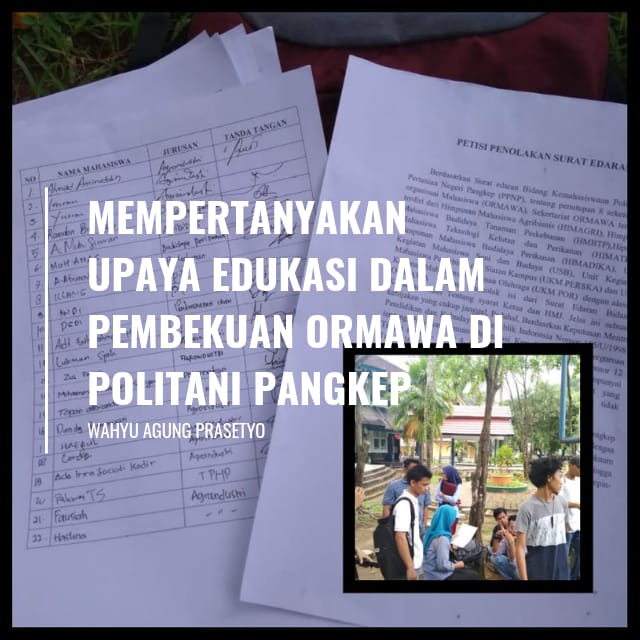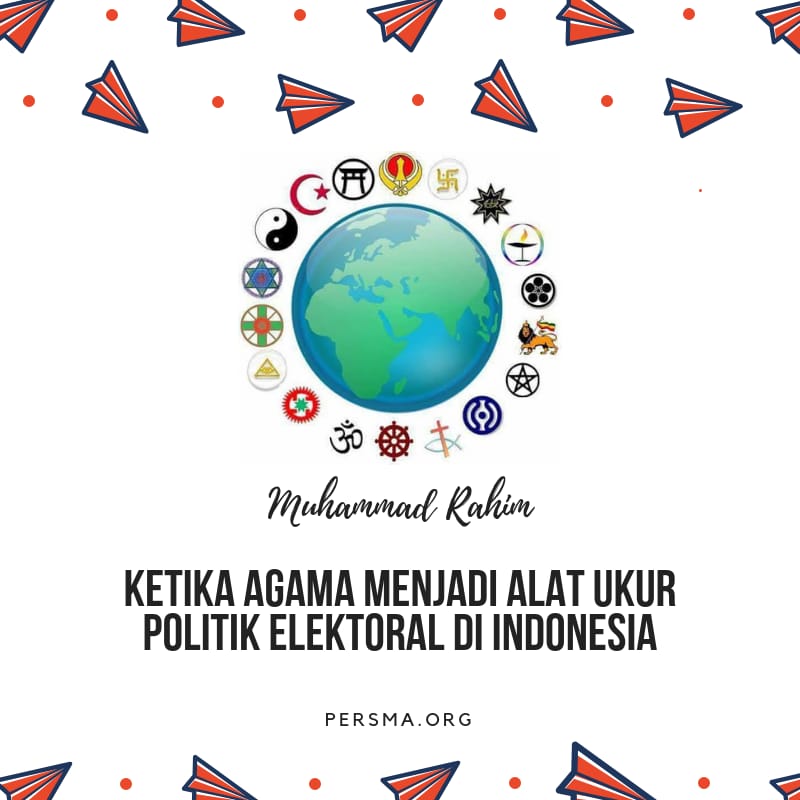Indonesia sedang mengalami problem yang sangat serius, yakni menjadi negara terdampak infeksi SARS-Cov-2 yang mengakibatkan penyakit Coronavirus Disease atau disebut dengan Covid-19. Indonesia secara resmi mengakui merebaknya wabah Covid-19 pada 2 Maret 2020, ditandai dengan diumumkannya dua pasien pertama oleh Presiden Joko Widodo. Sejak itu, peningkatan jumlah pasien positif Covid-19 terus meningkat di Indonesia. Hingga Selasa, 7 April 2020, pukul 19.00 WIB. Pasien positif tercatat mencapai 2.738, pasien dalam perawatan 2.313, pasien sembuh 204 dan pasien meninggal dunia 221. [1]
Saya berdoa pandemi ini akan segera berakhir, tapi nyatanya para ahli dengan berbagai analisisnya, menyatakan pandemi ini tidak akan cepat berlalu dalam beberapa minggu ke depan, sekalipun sudah menerapkan isolasi diri agar mengurangi jumlah sebaran infeksi. Virus ini bisa menyebar dengan cepat khususnya di negara yang jumlah penduduknya padat. Pada 3 April 2020 Badan Intelijen Negara (BIN) menyampaikan prediksinya yang teranyar, jika penyebaran virus Covid-19 akan memuncak pada bulan Juli 2020. Temuan ini disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR. Jumlah kasus positif Covid-19 akan meningkat secara berangsur tiap bulannya 1.577 kasus pada akhir Maret, 27.307 pada akhir April, 95.451 pada akhir Mei, lalu 105.765 pada akhir Juni. [2]
Seiring semakin banyaknya korban berjatuhan dan masih lama berakhirnya virus ini, jika merujuk pada perkiraan para ahli. Hal ini membuat semakin besar kekhawatiran masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari, baik perihal kebutuhan pangan, akses kesehatan sampai menyangkut kebijakan pemerintah dalam merespons wabah Covid-19. Di sini perlu kita renungi dan pertanyakan, bagaimana keseriusan pemerintah dalam menangani Covid-19? Berikut sedikit ulasan saya.
Awal
Mula Virus Muncul dan Kegagapan Pemerintah
Saat
pertama kali virus ini muncul di China dan menyebar ke negara lain, pemerintah
menganut premis yang sama sangat keliru. Pemerintah melalui pernyataan para
pejabat dan elitnya cenderung meremehkan dan menyiratkan seakan-akan semua
masyarakat Indonesia kebal terhadap serangan virus ini. Melalui Menteri
Kesehatan Terawan Agus Putranto memberikan respon terkait penanganan Covid-19
yang cenderung meremehkan dan tidak menggambarkan kemampuan berpikir yang baik.
Benjamin Bland salah satu peneliti sekaligus Direktur Lowy institute Asia Tenggara, lembaga think
thank Australia mengatakan, “Hal yang disampaikan Menteri Kesehatan
Terawan terkait Covid-19 memperlihatkan bahwa pemerintah Jokowi minim berpikir
strategis.” [3]
Tidak berselang lama, Universitas Harvard memprediksi bahwa virus Sars-Cov-2 penyebab Covid-19 sudah sampai di Indonesia, ditolak mentah-mentah. Bukannya dijadikan landasan untuk mempersiapkan kebijakan kesehatan publik yang kuat dan efektif untuk menghadapi virus ini. Sikap meremehkan dan cenderung anti-sains ini sedikit banyak telah membuat pemerintah ter–gagap manakala virus ini benar-benar datang. Sementara para pemimpin negara-negara tetangga jauh hari sudah mempersiapkan negaranya, masing-masing: memperluas kampanye layanan masyarakat, menyiapkan rumah sakit, menetapkan prosedur dan protokol di pelbagai sarana publik, Pemerintah Indonesia terlihat minim inisiatif dan ketinggalan.
Kegagapan nampak dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan baik oleh pejabat pemerintah pusat, maupun daerah. Koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat dan daerah, mis-komunikasi antara Kementerian Kesehatan dengan instansi lainnya, nampak pada saat kasus pertama diumumkan, termasuk pelanggaran hak privasi pasien. Tampak jelas bahwa pemerintah cenderung mendahulukan citra ketimbang kemaslahatan pasien dan keselamatan publik yang lebih luas.
Pemerintah Jokowi tidak memiliki rencana yang jelas dan transparan dalam menangani Covid-19, meskipun Jokowi telah membentuk tim respon cepat untuk mengatasi krisis, hingga menyatakan pemerintah pusat akan mengambil kendali penanganan Covid-19, koordinasi antara istana dan pemerintah daerah juga masih minim, akibatnya banyak tarik ulur kebijakan, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan penanggulangan Covid-19. Bahkan beberapa pemerintah daerah memilih berinisiatif membuat kebijakan tanpa menunggu intruksi dari pemerintah pusat. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah sudah tidak percaya pada pemerintah pusat. Pada situasi seperti ini pemerintah daerah lah yang fokus memberikan perlindungan kepada masyarakat, karena secara sosiologis dan geografis pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat yang terdampak.
Selanjutnya,
langkah yang diambil pemerintah pusat hanya sebatas menghimbau masyarakat untuk
mengambil tindakan pencegahan. Seperti melalui kampanye menjaga kebersihan,
mencuci tangan pakai sabun, mengenakan masker, seruan menghindari keramaian
atau kontak sosial, yang mana hal tersebut terpaku pada kesadaran individu.
Padahal pandemi Covid-19 telah menimbulkan berbagai dampak sosial-ekonomi yang
signifikan bagi kelompok rentan. Sebanyak 16.065 pekerja atau buruh di DKI
Jakarta terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19. Jumlah
tersebut berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
(Disnakertrans) DKI Jakarta. Selain PHK, wabah Covid-19 juga membuat 72.770
pekerja dirumahkan [4], pelaku usaha kecil mandiri juga akan alami berkurangnya
pendapatan, akibat terhentinya pekerjaan atau turunnya daya beli, selain itu
juga disebabkan harga pangan yang naik atau langka sejak pandemi meluas.
Selain
itu, masih ada buruh pabrik yang harus bekerja di tengah bahaya wabah Covid-19,
diketahui buruh pabrik di Sukabumi menuntut untuk libur ramai disuarakan
melalui media sosial, Jarak yang saling berdekatan, bahkan kadang saling
bersenggolan satu sama lain membuat rentan terjangkit virus. Mereka menganggap social distancing tidak berlaku di
tempat mereka bekerja. Seandainya pabrik diliburkan, mereka berharap manajemen
perusahaan tempat mereka bekerja tetap memberikan upah. [5]
Logika
Otoriterisme Pemerintah
Pemerintahan
dalam kebijakan pengamanan akibat pandemi ini didasarkan pada logika otoriter.
Diketahui Polda Metro Jaya menangkap 18 orang di Jakarta Pusat pada Jumat malam
3 April 2020. Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, mereka diduga
melanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB), padahal belum ada penetapan
tentang PSBB. Benar bahwa Presiden telah menetapkan PP No 21 tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19,
namun PP tersebut tidak menetapkan bahwa pada wilayah di Indonesia diberlakukan
PSBB. Belum ada ketentuan pidana yang dapat diterapkan, tapi rakyat sudah bisa
ditindak secara sewenang-wenang, termasuk rakyat yang terpaksa harus tetap
keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. [6]
Untuk
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama menghadapi bencana non-alam,
Pada 4 April 2020, Mabes Polri mengeluarkan Surat Telegram (ST) terkait
penanganan para penyebar hoaks dan penghina presiden saat pandemi Covid-19. Surat
Telegram itu bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020, dokumen tersebut ditandatangani
langsung oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo. Kepala Biro Penmas
Divisi Humas Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menyampaikan sudah
menangani 72 kasus, yang mana kasus tersebut merupakan total hasil penanganan
jajaran kepolisian di berbagai daerah. [7]
Kita
bisa merenungkan tentang berapa banyak sumber dana yang lebih banyak
dialokasikan ke dalam militer, polisi, bank dan pasar saham, daripada
dianggarkan untuk perawatan kesehatan publik dan sumber daya terkait untuk
membantu orang selamat dari krisis ini. Dan faktanya, memidanakan dan
memenjarakan warga sipil karena ketahuan berkeliaran dan ketahuan mengadakan
acara pernikahan akan lebih mudah dilakukan aparatur negara dibandingkan dengan
melakukan tes virus kepada anggota masyarakat. Dan yang perlu diingat baik-baik,
saat warga negara dilarang berkeliaran di jalan, pemerintah dan DPR justru
sedang berkumpul melakukan sidang membahas RUU Omnibus Law, RUU KUHP, RUU
Minerba dan undang-undang yang menyengsarakan rakyat lainnya. Anehnya para
aparat negara tidak ada yang membubarkan atau memberi peringatan kepada DPR dan
pemerintah.
Di
tengah pandemi seperti ini, tentu sangat tidak etis apabila DPR dan pemerintah
memaksakan proses pembahasan, bahkan sampai berencana mengesahkan RUU Omnibus
Law, RUU KUHP, RUU Minerba, karena publik sedang berada pada masa krisis,
publik memberikan fokusnya pada penanganan Covid-19, sehingga partisipasi
publik terbatas. Jika DPR dan pemerintah tetap memaksakannya, maka kita semua
sebagai warga negara tahu bahwa pemerintah pusat dan DPR gagal menentukan
prioritas, tidak peduli dengan ribuan pasien positif dan ratusan pasien yang
meninggal dunia gara-gara Covid-19.
Sebenarnya
pemerintah dapat melakukan tindakan yang benar-benar efektif, apabila
menjalankan dengan serius regulasi yang ada. Serta berpijak pada kepentingan
masyarakat yang lebih luas. Daripada membiarkan wabah semakin meluas, tentu
akan sangat merugikan pemerintah, jika kita memakai logika ekonomi pada
umumnya. Tidak akan ada investasi jika negara tidak bisa menjamin mereka,
khususnya keberlangsungan masyarakat. Jika memakai logika sesuai UUD dan
Pancasila, tentu konteks sosial yang didahulukan daripada memikirkan ekonomi. Karena
kesejahteraan diukur dari terjaminnya hak-hak masyarakat, bukannya dirampas,
sudah sangat jelas sangat anti terhadap filosofi dasar negara ini. Yang hilang
dari pemerintah saat ini adalah tidak mengutamakan masyarakat, karena pada
dasarnya pemerintahan oligarkis hanya memikirkan keuntungan segelintir orang
saja.
Membaca
Regulasi yang Ada
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat (1), Pasal 34 Ayat (3). [8]
Menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak setiap orang yang menjadi tanggung jawab negara atas penyediaannya. Setiap orang berhak dan wajib mendapat kesehatan dalam derajat yang optimal, tidak hanya menyangkut masalah individu–an sich, tetapi meliputi semua faktor yang berkontribusi terhadap hidup yang sehat, seperti masalah lingkungan, nutrisi, perumahan dan juga hak atas kesehatan serta hak atas pelayanan tenaga medis.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. [9]
UU Wabah Penyakit Menular secara jelas disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan penanggulangan wabah penyakit menular, melalui pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina serta pencegahan dan pengebalan. Tujuan UU ini terkait penanggulangan wabah penyakit menular, pemerintah seharusnya melakukan se–dini mungkin dikarenakan akibatnya yang sangat luas. Covid-19 oleh WHO telah dinyatakan sebagai pandemi, mengutip dari Tempo [10] diartikan ketika suatu penyakit menular dengan mudah menjangkiti satu orang ke orang lainnya di banyak negara pada waktu yang bersamaan.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. [11]
Wabah penyakit menular Covid-19 sudah ditetapkan sebagai bencana non-alam. Akibatnya pemerintah memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 7, 8 dan 9. Masyarakat memiliki hak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 26, terutama hak atas kebutuhan dasarnya.
Penanggulangan
bencana dibagi menjadi tiga tahap yaitu, pra-bencana, saat tanggap darurat dan
pasca bencana. Jika melihat kondisi saat pra-bencana, dapat dilihat jika pemerintah
telah abai dalam melakukan kewajibannya. Tahap pra-bencana dibagi menjadi, saat
tidak terjadi bencana dan saat ada potensi bencana, seperti yang tertuang dalam
pasal 34.
Merebaknya
kasus Covid-19 di media internasional dan juga peringatan dari WHO serta
negara-negara lainnya menunjukan bahwa sebelum kasus pertama Covid-19 di
Indonesia ditemukan, pemerintah telah sadar bahwa terdapat kemungkinan Covid-19
untuk masuk ke Indonesia. D dasar tersebut, seharusnya Pemerintah Indonesia
menyelenggarakan penanggulangan bencana seperti perencanaan penanggulangan
bencana, pengurangan resiko bencana dan pencegahan, yang telah diatur dalam
pasal 35. Karena perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah sesuai
dengan kewenangannya.
Selain
itu, pada saat potensi terjadinya bencana, maka pemerintah seharusnya melakukan
kesiap-siapan, peringatan dini dan mitigasi bencana. Dalam hal terjadi potensi
bencana, sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan hal-hal seperti yang
dijabarkan dalam Pasal 45, 46 dan 48, khususnya untuk mengurangi dampak negatif
dari bencana tersebut. Sebab itu, Pemerintah seharusnya menaruh fokus pada
tahap pra-bencana, yang mana tahap ini sangat penting. Tetapi mereka justru
abai, sehingga menyebabkan kondisi seperti pada saat ini. Tahap pra-bencana
menjadi faktor penting untuk mencegah ataupun mengurangi dampak negatif dari
bencana.
Pada saat tahap tanggap darurat, pemerintah memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 dengan memprioritaskan kelompok rentan. Isolasi orang yang terkena Covid-19 cukup memakan waktu cukup panjang. Bagi mereka yang terkena Covid-19 dan berkedudukan sebagai tulang punggung keluarga tentu saja akan memberikan dampak terhadap perekonomian keluarga. Apalagi lebih dari 60% penduduk Indonesia bekerja pada sektor informal. Karena itu seharusnya pemerintah juga memperhatikan hal tersebut.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. [12]
Berdasar UU Kekarantinaan Kesehatan, Indonesia memiliki komitmen melakukan upaya mencegah terjadinya darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia dan juga harus menghormati sepenuhnya martabat hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang dan penerapannya secara universal untuk perlindungan kesehatan masyarakat dan meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan. Kemudian dalam karantina kesehatan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tanggungjawab dalam penyelenggaraan karantina kesehatan. Selama karantina, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Selain menjamin kebutuhan hidup, pemerintah pusat juga harus menjamin kebutuhan sumber daya yang diperlukan dan menyelenggarakan karantina kesehatan di pintu masuk dan di wilayah secara terpadu. Di mana pintu masuk adalah tempat masuk dan keluar orang yang berpotensi besar menimbulkan bahaya kesehatan dan menyebar ke lintas wilayah dan lintas negara.
Semestinya
masyarakat tidak perlu cemas akibat pandemi ini, pemerintah pusat dan daerah
seharusnya bisa memenuhi akses pangan, kesehatan, terutama bagi kelompok
rentan. Pemerintah juga harus bisa mengantisipasi terhadap dampak
sosial-ekonomi dari wabah Covid 19. Semestinya pemerintah jangan hanya
menghimbau masyarakat agar tidak panik, tapi juga memberikan fasilitas kepada
masyarakat, karena sesungguhnya kepanikan masyarakat bersumber dari tidak
adanya pangan dan tidak adanya akses kesehatan. Banyak masyarakat yang berpikir
bahwa pemerintah telah acuh terhadap wabah Covid-19, pemerintah ingin membunuh
masyarakat secara perlahan, entah itu karena mati kelaparan atau terpapar
virus.
Pemerintah
juga tidak usah khawatir terkait lemahnya perekonomian negara, seperti ungkapan
Presiden Ghana, Nana Akufo-Addo di akun Twitter resminya pada tanggal 28 Maret
2020. “Kami tahu cara menghidupkan kembali ekonomi. Yang kami tidak
tahu adalah bagaimana menghidupkan kembali orang yang mati.”
Terakhir,
seandainya kita selamat melewati wabah ini, kita jangan pernah lupa bagaimana
tindak tanduk pejabat-pejabat pemerintahan yang tidak peduli dengan nasib warga
negaranya, banyak tenaga medis dan warga yang meninggal dunia, tetapi mereka
tetap melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law, RUU KUHP, RUU Minerba dan RUU
yang akan menyengsarakan masyarakat lainnya, sementara di beberapa daerah masih
terdapat konflik agraria, kriminalisasi masyarakat dan kelompok adat tetap
berjalan. Setidaknya dengan menjaga ingatan kita bisa tetap merawat kebenaran yang ada, lalu memikirkan ulang
jika diajak oleh pemerintah untuk kembali memilih mereka di bilik suara
pemilihan umum kelak.
Referensi
[1] Kasus Covid19 di Indonesia. Diakses 6 April 2020. www.covid19.go.id
[2] Kompas.com. Prediksi Sejumlah Pakar Soal Puncak Wabah Virus Corona di Indonesai. Diakses 3 April 2020. https://amp.kompas.com/tren/read/2020/04/03/123616065/prediksi-sejumlah-pakar-soal-puncak-wabah-virus-corona-di-indonesia#referrer=https://www.google.com
[3] Benjamin Bland. Indonesia: Covid 19 Crisis Reveals Cracks in Jokowi’s Ad Hoc. The Intrepreter, media Lowy Institute. Diakses 3 April 2020. (Online : https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/indonesia-covid-19-crisis-reveals-cracks-jokowi-s-ad-hoc-politics).
[4] CNN Indonesia. Imbas Corona 16 Ribu Warga DKI Jadi Korban PHK. Diakses 4 April 2020. https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200404134159-92-490291/imbas-corona-16-ribu-warga-dki-jakarta-jadi-korban-phk
[5] Detik.com. Curhat Buruh Pabrik di Sukabumi Yang Masih Bekerja Saat Corona Mewabah. Diakses 6 April 2020. https://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-4960861/curhat-buruh-pabrik-di-sukabumi-yang-masih-bekerja-saat-corona-mewabah
[6] ICJR. Pemerintah Tidak Jelas soal PSBB. Diakses 6 April 2020. http://icjr.or.id/pemerintah-tidak-jelas-soal-psbb-tindakan-kepolisian-melakukan-penangkapan-atas-dasar-psbb-melanggar-hukum/
[7] Liputan 6. Polri Terbitkan Aturan Khusu Tangani Hoaks dan Penghinaan Presiden Terkait Corona. Diakses 6 April 2020. https://m.liputan6.com/amp/4219978/polri-terbitkan-aturan-khusus-tangani-hoaks-dan-penghinaan-presiden-terkait-corona
[8] UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
[9] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
[10] Majalah Tempo. Ketidaksiapan Negara-Negara di Dunia Menghadapi Corona. Diakses 3 April 2020. https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159993/ketidaksiapan-negara-negara-di-dunia-menghadapicorona
[11] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
[12] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.