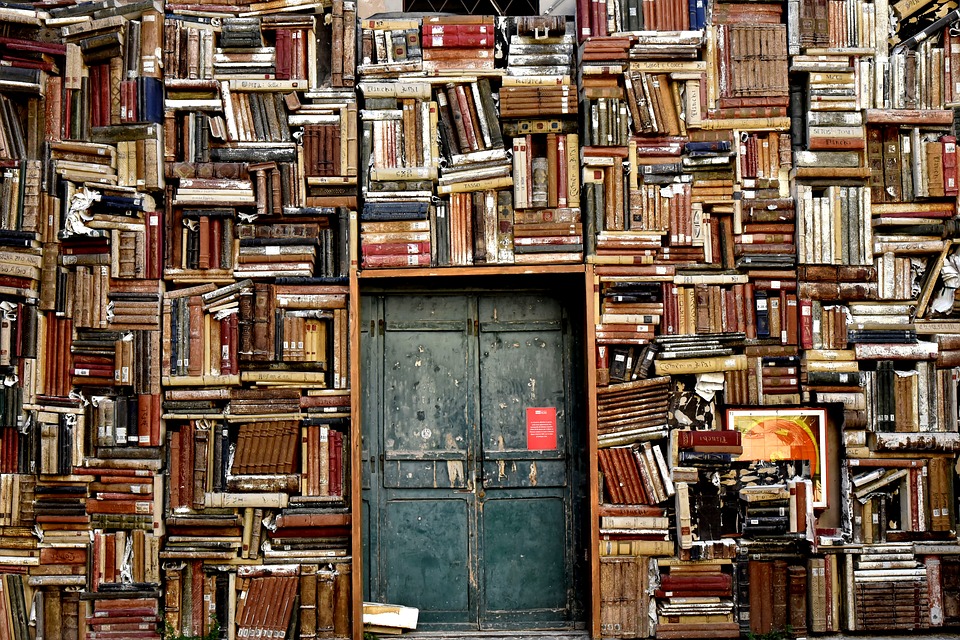Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) merupakan wadah berproses bagi mahasiswa yang berkutat pada persoalan jurnalistik. Dalam peranannya tak jauh berbeda dengan perusahaan media pada umumnya yang melakukan kegiatan jurnalistik seperti mencari berita, meliput, menulis, dan mengolah informasi menjadi sebuah karya yang akan disampaikan ke masyarakat atau publik. Hal ini sebagai bentuk implementasi fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
Dalam kehidupan di kampus, adalah hal yang lumrah ketika pers mahasiswa (persma) melaksanakan peran dan fungsinya. Apalagi kampus merupakan ruang akademis yang dihuni para kaum intelektual. Namun apa jadinya jika kampus saja tabuh dalam menanggapi sebuah pemberitaan yang diterbitkan oleh persma? Sebagaimana perkara yang saat ini tengah dialami oleh LPM Poros Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta.
Kronologi Kasus Represi yang Dialami LPM Poros UAD
Kasus ini bermula ketika Poros menulis tentang praktek penjualan buku yang dilakukan oleh seorang dosen berinisial MN. Melalui pesan WhatsApp Grup, dosen tersebut meminta mahasiswa Ilmu Komunikasi (Ilkom) untuk membeli buku mata kuliah Kemuhammadiyahan berjudul “Kuliah Muhammadiyah Gerakan Tajdid”. Buku tersebut dituliskan oleh H. Anhar Anshori yang diterbitkan oleh UAD PRESS, bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Studi Islam (LPSI) UAD. MN diduga memaksa mahasiwa membeli buku kuliah tersebut dan menyebutkan jika mahasiswa membeli buku, maka akan mendapatkan nilai rata-rata A, dan yang tidak membeli akan mendapatkan nilai B-, C, bahkan D. Menurut pengakuan MN, buku tersebut sudah dicetak UAD sebanyak jumlah mahasiswa di kelasnya.
Poros mewawancarai salah satu mahasiswa di kelas yang diampu MN. Mahasiswa itu memberi bukti-bukti ketika dosen MN mengirim pesan singkat yang bertendensi memaksa dengan ancaman nilai. Poros juga menerima tangkapan layar percakapan MN dan mahasiswa melalui pesan WhatsApp grup dari salah satu mahasiswa yang diampu MN. Selanjutnya, Poros meminta klarifikasi dengan mewawancarai pihak LPSI melalui saluran siaga (16/8). Menurut keterangan LPSI, polemik yang disebabkan MN hanya masalah miskomunikasi. Lebih lanjut, melalui pesan WhatsApp grup angkatan 19 Ilkom, Kaprodi Ilkom mengirimkan bukti obrolan dengan pihak LPSI yang menegaskan bahwa buku yang diterbitkan oleh LPSI sifatnya anjuran dan tidak terkait dengan nilai tertentu. Lalu Poros juga meminta tanggapan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Agama Islam terkait polemik penjualan buku tersebut.
Poros kemudian memberitakan hal tersebut yang berjudul “Nilai A Seharga Buku Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah”, diterbitkan pada 19 Agustus 2021. Kesimpulan dari berita ini adalah mahasiswa tidak lagi diwajibkan membeli buku dan tidak ada kaitannya dengan perolehan nilai. Namun sehari setelahnya (20/8), LPSI melakukan pemanggilan kepada redaksi Poros di Ruang Rapat LPSI dengan dalih berkeberatan (dirugikan) dengan pemberitaan yang telah diterbitkan oleh Poros.
Dalam forum audiensi, Kepala LPSI, Anhar Anshori, menegaskan bahwa lembaganya tidak pernah mewajibkan mahasiswa untuk membeli buku, apalagi sampai memengaruhi nilai akhir mahasiswa. Sebab, pihak LPSI paham mengenai latar belakang mahasiswa yang berbeda-beda. Menurutnya, jika ada dosen yang mengatakan beli buku dapat nilai A, seharusnya mahasiswa perlu menanyakan terlebih dahulu. Hal itu perlu dilakukan karena bisa saja lidah dosen yang mengatakan beli buku dapat nilai A ketlingsut alias salah bicara.
Dalam forum ini, Poros menawarkan hak jawab jika LPSI memang merasa dirugikan. Namun LPSI terus menawarkan opsi yang sama, yaitu menghapus pemberitaan tersebut. Perdebatan ini berlangsung hingga satu jam, hingga akhirnya Poros memutuskan menghapus pemberitaannya lantaran forum sudah semakin tendensius, tidak berimbang, dan represif.
Dasar Hukum dan Analisis Kasus LPM Poros
Mencari titik terang dari perkara pemberitaan Poros yang ditanggapi secara represif oleh LPSI. Badan Pekerja Advokasi Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional kemudian melakukan kajian dan analisis hukum serta mewawancarai beberapa pihak terkait. Menilai sikap LPSI yang cenderung lebih mempermasalahkan terkait pemberitaan Poros ketimbang menindaklanjuti temuan fakta yang disampaikan oleh Poros dalam pemberitaannya terkait dengan praktek penjualan buku yang dilakukan oleh MN patutlah dipertanyakan.
Mengenai praktek dosen jual buku, dilandaskan pada beberapa ketentuan hukum yang terindikasi telah dilanggar oleh MN. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen memiliki kewajiban sebagaimana telah diatur pada ketentuan Undang-undang tentang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 (UUGD No.15 Tahun 2005), pasal 60, poin (d) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran, serta poin (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan , hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika.
Hal tersebut juga berkaitan dengan Peraturan Menteri nomor 2 tahun 2008 tentang Buku, pada ketentuan pasal 11, berbunyi: “Pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah/madrasah, dinas pendidikan pemerintah daerah, pegawai dinas pendidikan pemerintah daerah, dan/atau koperasi yang beranggotakan pendidik dan/atau tenaga kependidikan satuan pendidikan, baik secara langsung maupun bekerjasama dengan pihak lain, dilarang bertindak sebagai distributor atau pengecer buku kepada peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan, kecuali untuk buku-buku yang hak ciptanya sudah dibeli oleh Departemen, departemen yang menangani urusan agama, dan/atau Pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dan dinyatakan dapat diperdagangkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).”
Di samping itu represi yang dialami Poros semakin menegaskan persma dalam kondisi rentan. Pasalnya, posisi persma belum dianggap sebagai entitas pers yang layak mendapatkan proteksi. Dari sisi hukum persma rentan karena secara eksplisit mereka tidak masuk dalam kategori perusahaan pers berbadan hukum seperti yang tertulis dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999. Akibatnya pelarangan atau pembatasan kerja-kerja jurnalistik kerap dialami oleh pers mahasiswa dengan dalih tidak memiliki legitimasi.
Namun, meski tak dijamin secara spesifik dalam undang-undang No. 40 Tahun 1999, pers mahasiswa memiliki perlindungan secara konstitusional maupun perundang-undangan dengan pendekatan kebebasan akademik. Seperti Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan akademik bisa dijamin melalui penafsiran meluas atas ketentuan Pasal 28, 28C, 28E, 28F Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia (RI) Tahun 1945.
Selain itu, secara umum, kebebasan akademik juga dijamin dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), serta pasal-pasal dalam UU Nomor 11 dan 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yakni Pasal 13 terkait hak atas pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta Pasal 19 terkait Hak Sipil dan Politik. Dan, secara khusus, kebebasan akademik dilindungi dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 8 ayat 1 dikatakan “Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.” Dan ayat 3, Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi”. Dan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik diterangkan pada pasal 9 dan 54 UU Dikti.
Di luar aturan hukum negara, kebabasan akademik juga diatur dengan adanya aturan internal kampus masing-masing. Namun, baik UU Dikti maupun aturan internal, masih belum cukup memberikan perlindungan terhadap keberadaan persma. Dari beberapa regulasi di atas, persma sebagai entitas yang bekerja dengan semangat dan nilai-nilai kemerdekaan pers, mestinya memiliki hak dan porsi yang sama dengan pers umum.
Akan tetapi, kekerasan terhadap jurnalis mahasiswa bukan hanya karena minimnya perlindungan secara spesifik, namun juga karena sikap otoritarianisme yang semakin mengakar yang bahkan juga terjadi dalam lingkungan akademik.
Sikap Kontra Universitas atas Tindakan LPSI yang Represif
Praktek penjualan buku dengan sebuah ancaman nilai yang dilakukan oleh tenaga pendidik jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan di atas dan tentu tidaklah dapat dibenarkan dalam sebuah Perguruan Tinggi. Sebagaimana yang diterangkan oleh Wakil Rektor (WR) Bidang Kemahasiswaan UAD, Gatot Sugiarto, “UAD tidak membenarkan tindakan seperti itu, kalau menjual buku dengan paksaan, yah, tentu tidak boleh karena mahasiswa punya hak untuk membeli atau tidak, itu kebebasannya memilih, ini etika akademik, yah, dan ini harus dijaga juga,” ujarnya via WhatsApp saat diwawancarai oleh awak PPMI (25/8).
Lebih lanjut, Gatot Sugiharto mengatakan bahwa saat ini pihak rektorat tengah melakukan evaluasi terhadap sistem pembelajaran, khususnya di mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) dan juga melakukan upaya tabayyun terhadap pemberitaan Poros sebagai langkah tindaklanjut dari temuan fakta dalam pemberitaan tersebut. “Kalau seandainya nanti ada hal-hal yang bisa dibuktikan itu akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ini juga banyak yang bertanya ke saya, apakah poros ini akan dibredel? Saya kira tidaklah, UAD tidak akan sampai membredel, karena kita juga menjaga kebebasan berpendapat dan kreatifitasnya”.
Perihal keputusan sikap yang diambil oleh rektorat, dalam hal ini Rektor UAD mengamanahkannya kepada WR bidang AIK, Parjiman, yang menaungi dan bertanggungjawab atas mata kuliah yang sifatnya institusional. Melalui wawancara via telepon (27/8), Parjiman mengatakan bahwa dosen yang bersangkutan telah dimintai klarifikasinya, “memang, yah, buku itu sangat dianjurkan tapi tidak harus berakibat kalau beli buku dapat nilai sekian, nah, itu sangat fatal, itukan melanggar karena itu bukan standar pembelajaran”.
Dari hasil evaluasi dan upaya tabayyun yang dilakukan oleh pihak jajaran rektorat, Parjiman menyampaikan bahwa ke depannya buku Kuliah Muhammadiyah Gerakan Tajdid akan dibuat dalam bentuk e-book agar mahasiswa dapat secara mudah mendapatkannya sebagai bahan pembelajaran. Dan secara khusus sanksi yang akan diberikan bagi oknum dosen yang bersangkutan berdasarkan fakta dan bukti dari hasil evaluasi dan tabayyun. “Praktis sanksinya sudah tidak kita pakai, kalau untuk catatan-catatan yang berat seperti itu,” tegas Parjiman.
Parjiman juga membantah terkait beredarnya kabar isu terkait ancaman sanksi yang akan dikenakan kepada Poros. Dalam perkara ini, ia menegaskan kembali komitmen UAD sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi. “Kalau di rektorat dari rektor sampai semua wakilnya itu satu bahasa, jadi kita berpihak kepada siapa yang jujur dan siapa yang benar, insyaalah tidak ada itu”.
Kembali pada tindakan LPSI yang mendesak Poros untuk menghapus pemberitaanya dan menolak menggunakan hak jawabnya. Menanggapi hal tersebut, pada saat wawancara, Parjiman terdengar kaget ketika mengetahui bahwa pemberitaan poros berjudul “Nilai A Seharga Buku Tiga Puluh Lima Ribu” tak lagi dapat diakses. Menurutnya menghapus pemberitaan tersebut telah bertentangan dengan kode etik jurnalistik, “itu sebenarnya tidak boleh yah, jadi kami di pimpinan sepakat, yah, menggunakan hak jawab dan tidak harus ditakedown kayak gini, jadi hanya tinggal diklarifikasi saja”.
Kasus represi yang dialami oleh Poros hingga saat inipun juga tengah menjadi sorotan dan terus mendapat dukungan publik dari jejaring media umum, persma, dan individu atau organisasi pro demokrasi. Pasalnya tindakan LPSI dianggap telah mencederai demokrasi dikarenakan sangat berlebihan dalam menanggapi pemberitaan yang diterbitkan oleh Poros. Menindak hal ini, BP Advokasi PPMI Nasional juga mencoba mewawancarai pihak LPSI melalui kontak hotline untuk meminta klarifikasi terkait hal yang dianggap telah merugikan LPSI dalam pemberitaan Poros. Selama beberapa hari BP Advokasi PPMI Nasional meminta klarifikasinya melalui saluran siaga lembaga namun hingga tulisan ini diterbitkan, LPSI enggan memberikan tanggapan.