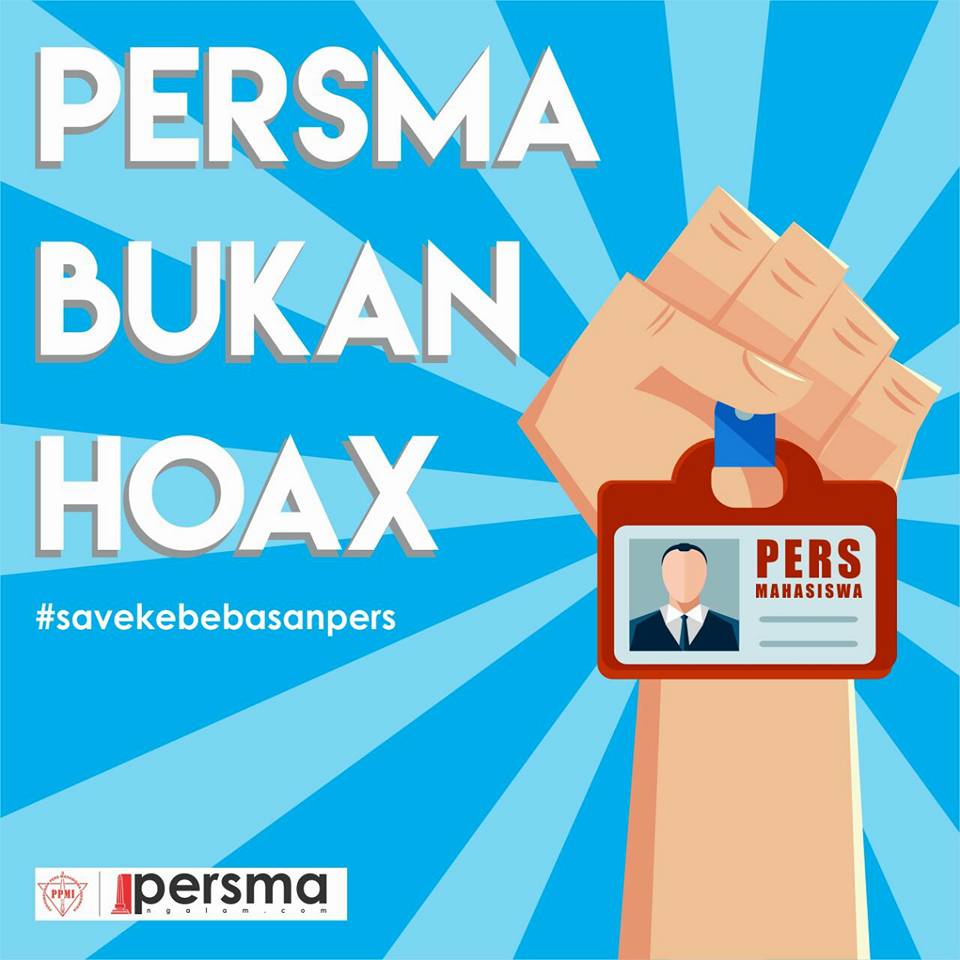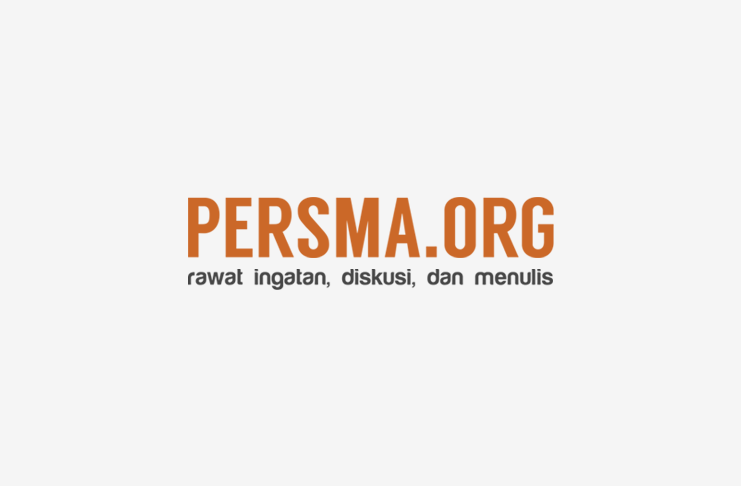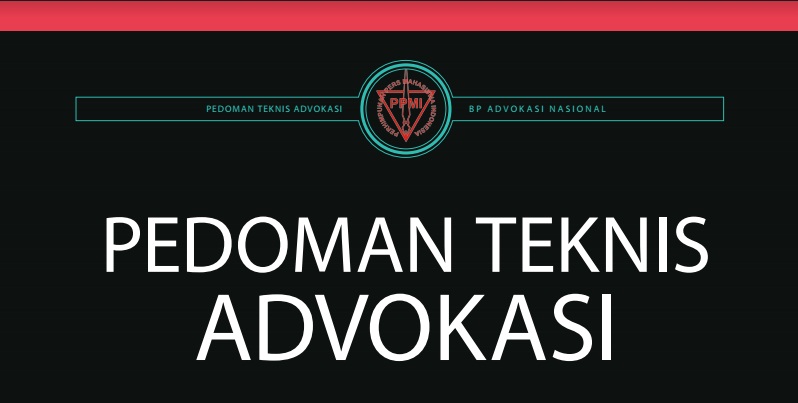Melalui sebuah rilis dan kronologinya, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Pendapa menyatakan tengah dibungkam oleh Rektorat Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST). Kabar ini tentu saja meresahkan banyak pihak. Tidak hanya kalangan pers mahasiswa (Persma)namun juga pihak-pihak yang peduli dengan nasib ajaran Tamansiswa. Sebab, UST sebagai kampus dalam naungan Perguruan Tamansiswa telah dinilai mencederai nilai-nilai luhur Tamansiswa yang diwarisi Ki Hadjar Dewantara.
Berdasarkan narasi sejarah, Tamansiswa didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara pada 3 Juli 1922 sebagai wadah gerakan pendidikan untuk melawan penjajahan rezim Hindia Belanda kepada pribumi. Ki Hadjar menginginkan suatu ruang pendidikan alternatif yang tidak mengabdi kepada rezim penjajah. Ruang pendidikan ini pun menerapkan prinsip-prinsip humanistis yang mendukung daya inteligensia, kreativitas, dan moral anak-anak didik. Selain dikenal sebagai pendiri Tamansiswa, Ki Hadjar merupakan tokoh pers kebangsaan yang kala itu kerap mengkritik kebijakan Hindia Belanda dan memperjuangkan kepentingan rakyat terjajah.
Maka sangat wajar bila pembungkaman terhadap LPM Pendapa begitu mengkhawatirkan pihak-pihak yang bersolidaritas dan sempat terpikir bahwa hal tersebut telah melenceng dari perjuangan pendidikan Tamansiswa. Melihat hal demikian, PPMI DK Yogyakarta dan jajaran Persma menggelar diskusi publik bertajuk “Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Nilai-nilai Tamansiswa” pada 22 November 2016 di Pendopo Agung Tamansiswa. Agenda yang juga turut mengundang Dewantara Institute, AJI Yogyakarta, dan Rektorat UST ini bertujuan untuk menarik kesepahaman bahwa Tamansiswa merupakan pelopor gerakan pendidikan yang menjamin kebebasan berekspresi. Sayangnya, pihak Rektorat tidak hadir dalam diskusi publik tersebut.
Selang dua hari berikutnya, 24 November, pengurus PPMI DK Yogyakarta pun menemui Rama Prambudhi Dikimara dari Dewantara Institute; lembaga kajian pendidikan bermazhab Ki Hadjar Dewantara dan pengamat ke-Tamansiswa-an, di Perpustakaan Tamansiswa, Mergangsan, Yogyakarta. Berikut petikan-petikan obrolan penting dengan Kang Rama; yang dahulu sempat menjadi Pemimpin Umum LPM Pendapa dan aktivis senat mahasiswa, mengenai pengakomodiran kritik dan kreativitas mahasiswa sekaligus kondisi terkini Perguruan Tamansiswa.
Seberapa pentingkah keberadaan Persma dalam Perguruan Tamansiswa?
Seharusnya menjadi ruh Tamansiswa; sebagai penerus pola kerja politik dan kebudayaan Ki Hadjar Dewantara. Mengingat Ki Hadjar merupakan tokoh pers, kalau di Tamansiswa tidak ada kantong kebudayaan dalam ranah jurnalistik, saya pikir ini akan memadakan api yang sudah dihidupkan lama oleh Ki Hadjar.
Saya menyayangkan ketika Majalah Pusara sudah tidak terbit lagi. Juga ada Majalah Sinus yang untuk anak-anak, sekarang kabarnya nggak tahu bagaimana. Nah, adanya Pendapa itu ditujukan untuk melanjutkan ruh perjuangan Ki Hadjar lewat menulis (jurnalistik). Pendapa seharusnya menjadi aset bukan hanya untuk UST, melainkan juga Tamansiswa.
Sejak awal didirikan pada 1988, apakah Pendapa sudah berparadigma kritis?
Saya menyimpan majalah-majalah Pendapa dari awal. Yang saya cermati, tradisi kritik-otokritik kepada Tamansiswa, kampus, dan negara sedari jauh-jauh hari sudah dilakukan. Saya yakini ini yang akan mendewasakan kita semua. Dahulu, Ki Hadjar kerap mengkritik Pemerintah Hindia Belanda. Tradisi kritik ini kemudian melekat. Saya mengkronik Majalah Pendapa dari awal. Dahulu, kritik malah lebih keras daripada sekarang. Cuma tergantung bagaimana tanggapan atau kedewasaan dari yang dikritik, sebab ini penting sebagai suatu dialektika.
Kalau kedewasaan pihak yang dikritik sekarang lemah sehingga melakukan cara-cara tidak demokratis, ini akan menghambat semua kreativitas mahasiswa. Dahulu ada unit teater Kelompok Sastra Pendapa (KSP) yang tutup aktivitas pada 2003. Terus ada Mapala Bangkel yang akhirnya tutup untuk kedua kalinya. Sekarang malah mau mencoba membungkam Pendapa. Tidak menutup kemungkinan, unit kegiatan lainnya juga bakal mengalami nasib sama jika Rektorat tidak memiliki kedewasaan. Tingkat kedewasaan personal dari tiap pemimpin di Tamansiswa itu penting. Kalau dikritik namun menanggapinya dengan cara anti-demokratis, itu membahayakan ruang.
Ki Hadjar sempat membuat catatan dan menjadi buku Demokrasi & Liederschap (Democracy and Leadership). Di situ ada argumentasi tentang demokrasi yang tidak mematikan ruang dan bisa memberi harapan bagi tumbuh kembang jiwanya anak-anak didik secara terpimpin. Inilah yang harus dipahami oleh Birokrat UST sekarang.
Melihat kondisi Tamansiswa sekarang, ada birokrat yang anti-kritik, sebenarnya ada sejak kapan kecenderungan begini? Bagaimanakah Tamansiswa awalnya mengakomodir kritik?
Melihat catatan sejarahnya, sebenarnya Tamansiswa tidak alergi kritik. Kecenderungan ini; mulai ada pola kemunduran Tamansiswa, terjadi paska tahun 1965. Rezim Orde Baru menghancurkan Tamansiswa dan sampai sekarang masih terjadi. Dan, pola ini malah ditiru oleh birokrat-birokrat kampus UST. Penyakit semacam ini seharusnya dipotong; tidak hanya memotong generasinya namun juga kebiasaan buruknya. Saya melihat kebiasaan buruk ini bisa mematikan Tamansiswa secara perlahan.
Ketika otokritik internal kampus saja dihambat, lantas apa ukuran kinerja tanpa kritik? Kinerja itu bisa diukur dengan kritik. Kalau kinerja tanpa kritik, itu akan menjadi rezim. Apalagi bila nalar dimatikan, ini akan berbahaya bagi kemanusiaan. Padahal ajaran Ki Hadjar sudah jauh-jauh hari menyiratkan bahwa kemerdekaan jiwa harus diberikan; tentang bagaimana pamong tidak boleh menghambat kreativitas dan memutus impian anak-anak didik. Namun sayangnya birokrat kampus sekarang tidak mempelajari ajaran itu. Kalau hal ini diterapkan secara serampangan, dampaknya tidak hanya kepada UST, juga terhadap Tamansiswa secara keseluruhan. UST seharusnya bisa menjadi tolok ukur bagi kampus-kampus lain, kalau di Perguruan Tamansiswa ternyata hubungan relasional kampus dan mahasiswa buruk, ini akan merembet ke kampus-kampus lainnya.
Dengan kondisi Tamansiswa seperti ini, banyak kreativitas mahasiswa dihambat, pun malah Persma dibungkam, menurut Kang Rama, apa yang seharusnya bisa dilakukan kawan-kawan mahasiswa UST?
Kesadaran kolektif harus dibangun. Bila kesadaran ini tidak dibangun, teman-teman (mahasiswa UST) akan diam. Pendapa dan teman-teman sejaringannya harus membangun kesadaran kolektif itu. Harus sama-sama disepakati tujuan dan dicarikan solusinya supaya Tamansiswa bangkit. Bila pembungkaman ini berlanjut tanpa solusi, UST sebagai lembaga kampus bisa dipertanyakan eksistensinya; universitas tidak bisa eksis tanpa unit kegiatan mahasiswa (UKM). Universitas harus ada unit kegiatan mahasiswa sebagai upaya pengabdian ke masyarakat dan menampung kreativitas mahasiswa.
Mahasiswa tidak hanya dianggap sebagai obyek pembelajaran, tapi di Tamansiswa juga dianggap anak didik yang sedang tumbuh kembang. Tumbuh kembang anak juga harus diberi ruang, kalau dihambat, mereka tidak akan maksimal. Di Tamansiswa tidak hanya dididik secara inteligensia, namun juga mendorong orang untuk berkreativitas dan memiliki kemampuan non-akademik. Dahulu, Tamansiswa menjadi kantong-kantong aktivis politik dan kebudayaan karena Tamansiswa memberinya ruang.
Kendala mahasiswa sekarang membangun kesadaran kolektif?
Menjadi aktivis dahulu gengsinya tinggi, kesadaran kolektif juga dibangun lewat pengayaan wacana yang lebih mudah. Sekarang mencari kader saja kesulitan dengan adanya silabus dan perkuliahan yang padat atau katakanlah mahasiswa dipaksa selesai dalam 4 tahun. Risikonya, aktivisme di kampus sekarang menjadi terbatas; tidak ada ruang lagi berekspresi. Hanya segelintir orang yang berani menjadi aktivis. Masalah itu harus dicarikan solusi.
Masalah dahulu beda dengan sekarang. Dulu belum ada gawai dan tempat-tempat hiburan yang cukup banyak. Kalau sekarang mahasiswa justru menghindari kegiatan kampus karena yang menjadi aktivis cenderung bermasalah dengan rektorat. Di banyak kampus juga begitu sebab relasional yang terjadi, rektorat tidak menganggap aktivisme mahasiswa sebagai aset; untuk persemian pengaderan kampus. Kalau aktivisme dianggap sebagai aset, lewat jembatan pembantu rektor (PR) III, bisa dibuka ruang-ruang dialog dan fasilitas berekspresi.
Sayangnya di UST, sudah 2 kali pergantian PR III, justru dijabat orang yang tidak paham bagaimana membangun relasional yang baik antara Rektorat-UKM. Apalagi mendekati UKM Persma, pendekatannya harus lain. Kalau Persma dijauhi, risikonya besar. Harus dilakukan komunikasi yang intens. Pendekatan tidak bisa dilakukan oleh pejabat yang birokratis; datang ke kantor, kerja, lalu pulang. Pejabat harus punya ketekunan untuk melakukan pendekatan. PR III harus orang yang menyediakan diri selama 24 jam/hari untuk mau mendengar kemauan mahasiswa. Jika begitu, komunikasi akan baik dan informasi tak terputus. Apa yang terjadi terhadap Pendapa selama ini merupakan miss-komunikasi dan informasi yang terputus.
Ketika saya dan teman-teman di Pendapa dulu, kami sering memaksa birokrat untuk mengobrol, ada ruang komunikasi yang dibangun, keluh kesah disampaikan. Teman-teman UKM sekarang juga harus punya cara elegan menghadapi rektorat supaya lebih mudah berkomunikasi. Di sisi lain, nanti otokritik terhadap kampus bisa dianggap penting.
Mengamati kritik mahasiswa sekarang terhadap negara atau kampus, bagaimana tanggapan senior-senior mantan aktivis kampus? Apakah kritik sekarang kurang cerdas?
Variannya banyak sih; beda-beda. Saya masih mendapat majalah dari teman-teman di berbagai kota; dari beberapa Persma. Itu sudah bagus, saya pikir sudah sesuai kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Kualitas teman-teman tidak bisa dipaksakan.
Saya sebagai alumni Persma, melihatnya sih sudah maksimal sebab melihat isu yang diangkat oleh lembaga Persma memang sedang krusial di suatu tempat. Tapi kalau mau dianalisis bobotnya juga bisa; misal seberapa kritik terhadap negara sekarang, apakah menurun? Kritik lembaga Persma terhadap kondisi internal mereka sendiri pun harus dianalisis. Justru PPMI harusnya menjadi suatu lembaga yang bisa membedah itu. Hal ini menarik sebagai sebuah kajian dan bisa dijadikan buku.
Persma sebagai lembaga yang menyemai benih jurnalistik di tiap kota, menurut saya sudah bagus. Misal permasalahan Majalah Lentera dengan kampusnya, itu menunjukkan capaian yang bagus. Saya baca hasil investigasi mereka, kualitasnya menyamai media mainstream. Beberapa terbitan Persma juga menggunakan pisau analisis lebih tajam dan independen dibanding media mainstream. Persma bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan media mainstream. Ketika Persma memiliki potensi lebih seperti ini, inilah yang harus didorong. Nilai lebih ini justru sebagai pembeda dan eksistensi Persma.
Sebagai penutup nih, dari obrolan ini, berarti bisa disimpulkan bahwa Persma yang berada di Tamansiswa maupun perguruan tinggi lainnya harus tetap berparadigma kritis. Tamansiswa sebagai pelopor pendidikan harusnya mengakomodir kritik.
Iya, saya setuju. Paradigma kritik harus tetap dipakai dan teman-teman Persma pun harus mendewasakan diri; masih banyak pisau analisis yang bisa dipakai. Jika di Tamansiswa; khususnya UST, ternyata Pendapa masih dibungkam, ini bukan hanya ajaran Tamansiswa yang dicederai. Dampaknya juga ke kampus-kampus lain. Makanya ini harus dihentikan.