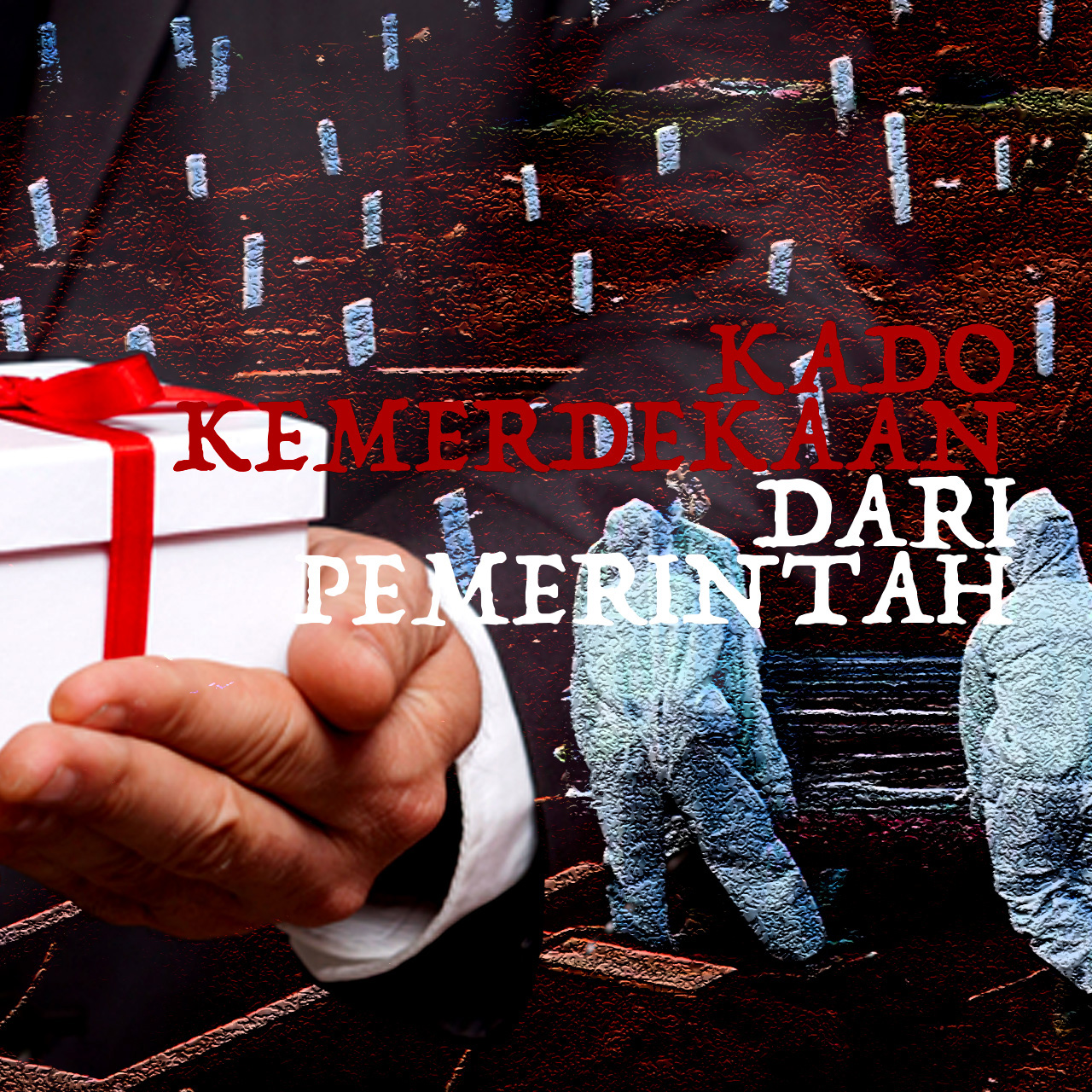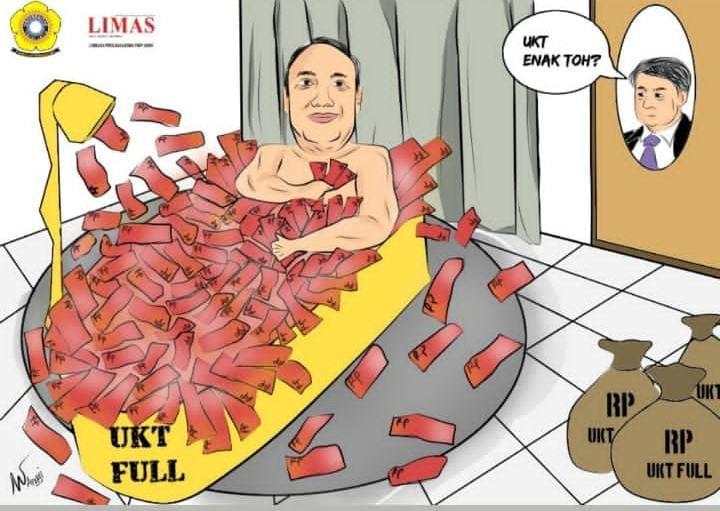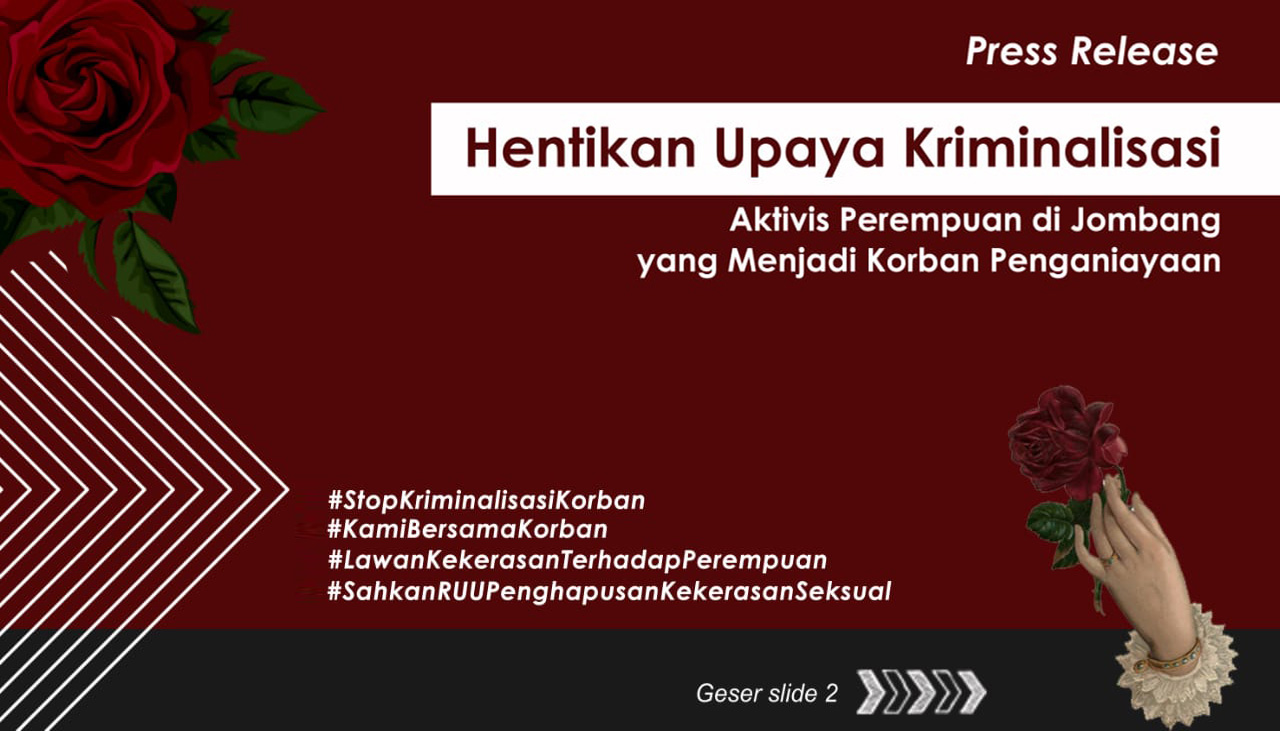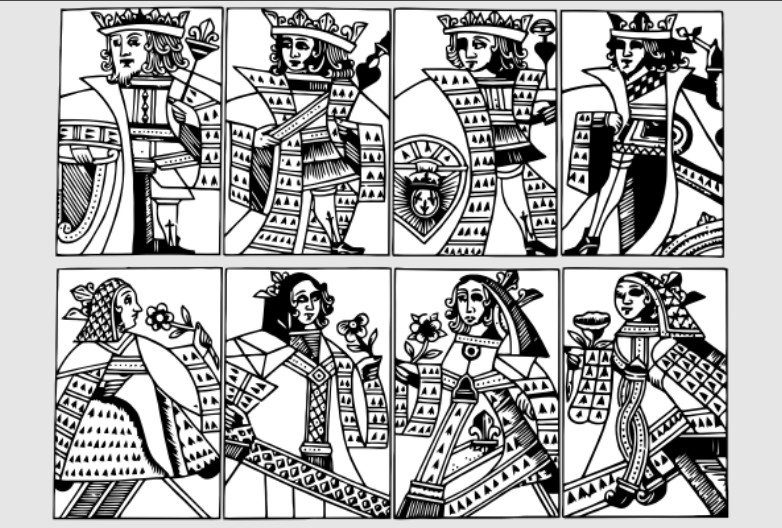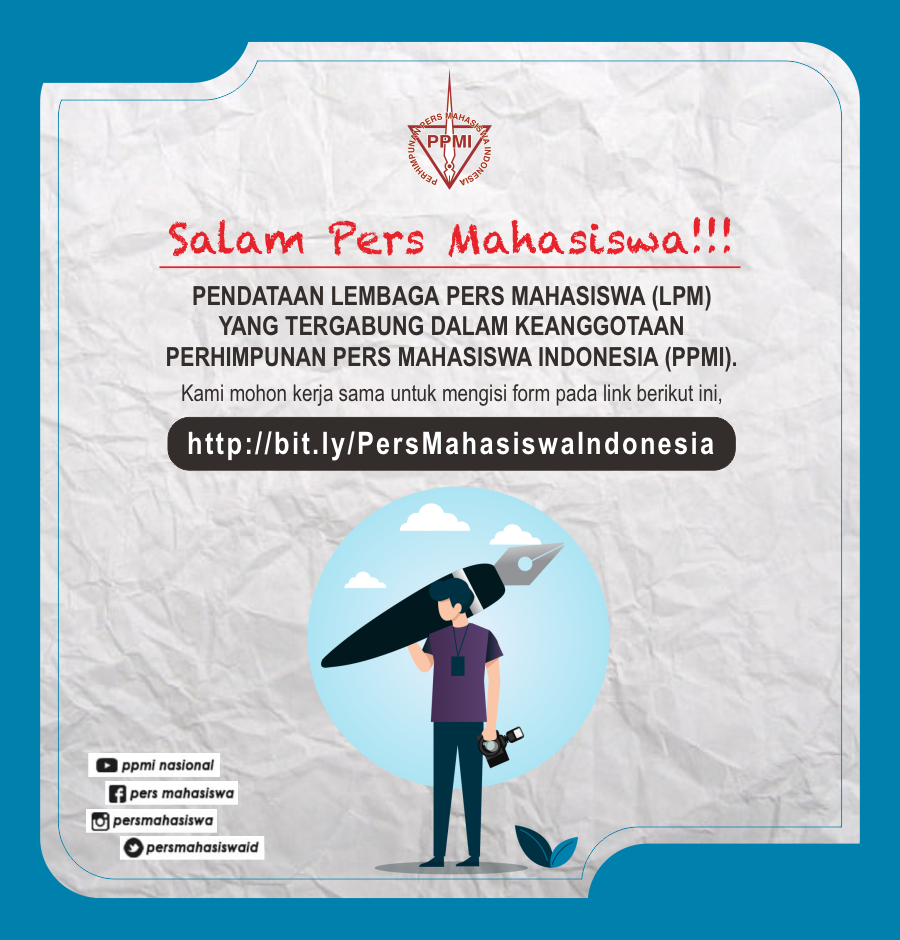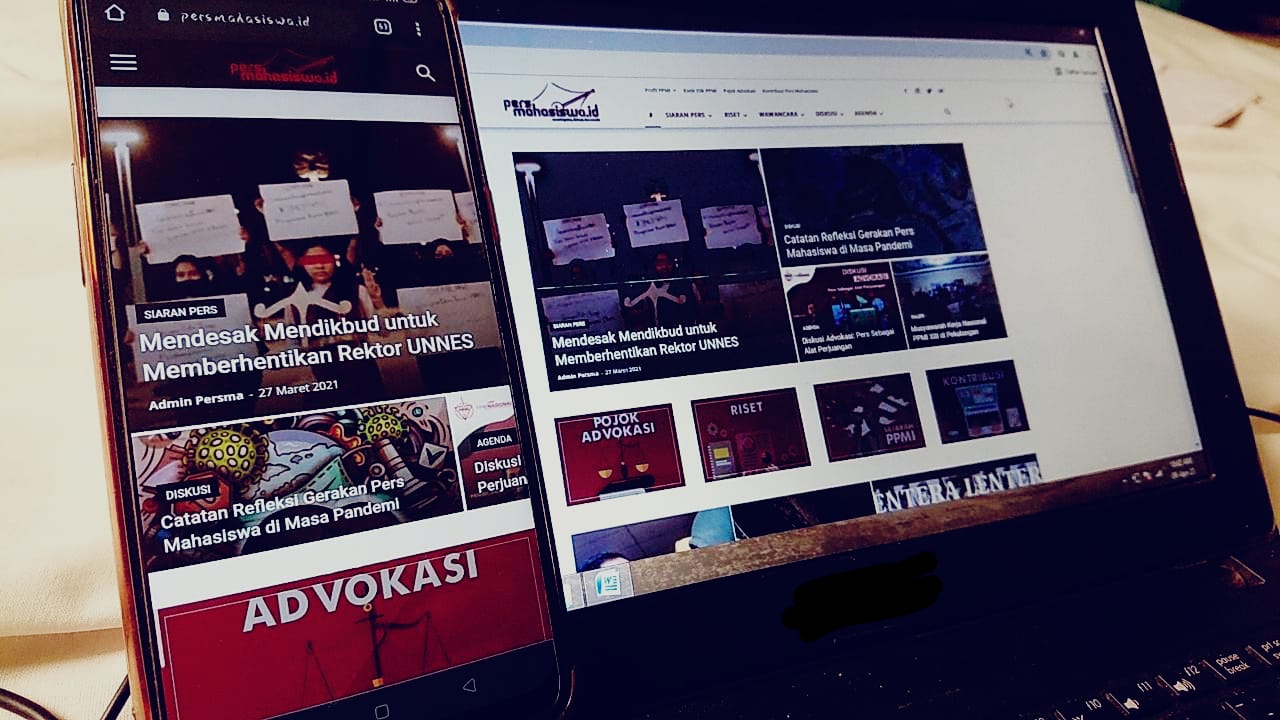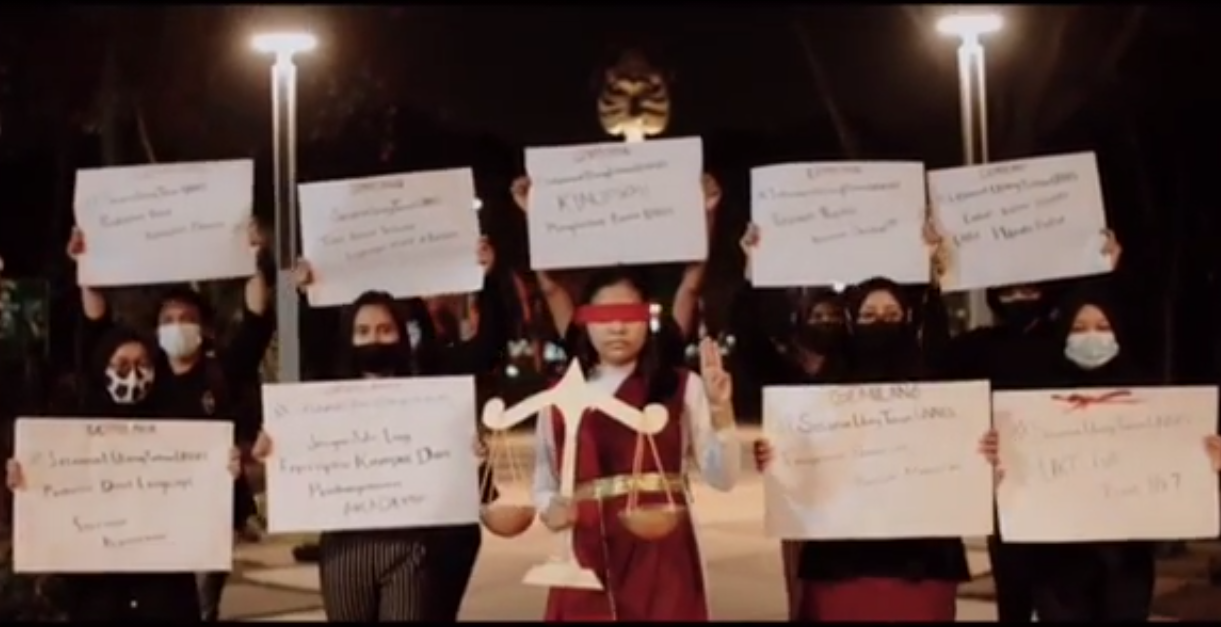Jika pemerintah terus salah mengambil kebijakan, rakyat bisa berjatuhan mati masal. Tercatat pertanggal 15 Agustus 2021, di laman covid19.go.id menunjukkan jumlah rakyat Indonesia mati karena Covid-19 mencapai 117.588. Tentu saya yakin data tersebut bukan data asli. Dapat dipastikan data yang tidak tercatat jauh lebih banyak. Berdasarkan pemantauan lapor covid data yang masuk ada perselisihan antara data daerah dan pusat. Banyaknya saudara kita yang meninggal dunia dan pendataan yang amburadul menunjukkkan ada masalah yang serius dalam penanganan dan kebijakan yang diambil pemerintah dalam menangani pandemi. Ribuan nyawa orang yang meninggal semestinya mendapat perhatian serius, bukan hanya sekedar data angka, karena setiap warga negara hidup, keselamatan, dan kesehatannya semestinya dijamin dalam undang-undang.
Tak terbilang berapa kali pemerintah melakukan pergantian nama kebijakan dalam menangani pandemi. Berganti siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut, kepemimpinan Satgas tak pernah sama sekali diserahkan kepada ahli kesehatan masyarakat atau epidemiolog. Beberapa pekan terakhir pun dunia Internasional menyoroti Indonesia menjadi episentrum pandemi dunia dengan penanganan yang carut marut. Sempat banyak ketidaktersediaan rumah sakit, kelangkaan oksigen, rencana vaksin berbayar, banyak tenaga kesehatan yang gugur, bahkan kematian anak Indoneisa akibat covid tertinggi di dunia. Seolah kebijakan pemerintah tersebut tak menunjukkan hasil yang signifikan.
Sebagai warga negara patut kita semua mengerti, kenapa kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi tidak membuahkan hasil? Apakah pemerintah membuat kebijakan tidak mempertimbangkan kebutuhan rakyatnya? Atau memang sengaja pemerintah tidak memprioritaskan kebutuhan rakyat, sehingga menyebabkan kematian massal? Jika demikian pantaskah kita menyebut pemerintah sebagai pembunuh rakyat di tengah pandemi? Berikut sedikit catatan dari saya menyoal kematian massal yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah.
PPKM Tanpa Jaminan Hidup
PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tanpa jaminan hidup adalah sebuah kebijakan pemerintah yang sangat tidak manusiawi, pasalnya tidak semua rakyat siap melindungi dirinya dengan berbagai jenis keamanan di tengah pandemi, tidak semua mampu mempersiapkan kebutuhan makanan pokok. Banyak rakyat yang mengantungkan hidupnya dengan berjualan di pasar, menjadi tukang becak, tukang ojek, dsb. Mereka tidak bisa untuk tetap dirumah saja, untuk bisa bertahan hidup ia harus bekerja, jika tidak bekerja ia tidak makan dan bisa mati kelaparan. Maka dari itu tak salah jika banyak masyarakat di berbagai daerah beberapa waktu yang lalu berdemonstrasi menolak PPKM, tidak salah pula masyarakat di berbagai daerah mengibarkan bendera putih sebagai tanda bahwa masyarakat sudah tidak kuat bertahan dalam himpitan masalah ekonomi saat pandemi.
Kejamnya pemerintah dan aparat di tengah pandemi juga dipertontonkan dengan banyaknya pembubaran usaha warga di berbagai daerah oleh Satpol PP dengan menggunakan kekerasan. Diantaranya terjadi di Semarang, pada 7 Juli 2021, Satpol PP melakukan penyemprotan lapak pedagang di pinggir jalan yang melanggar aturan PPKM dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran. Petugas juga bergerak cepat menyita dagangan dan peralatan dagang milik pedagang tersebut. Kemudian di Surabaya, pada 11 Juli 2021, petugas menyita tabung LPG 3 Kg milik pedagang di sebuah warung di Kecamatan Kenjeran. Tak hanya itu, petugas juga menyita e-KTP pemilik warung tersebut. Sedangkan di Tasikmalaya seorang penjual bubur didenda 5 juta rupiah karena melayani pembeli yang ingin makan di tempat. Penjual mengaku tidak tahu aturan PPKM. Namun, hakim tetap menjatuhkan hukuman denda. Beberapa kejadian tersebut adalah bukti nyata kekerasan yang dilakukan pemerintah melalui aparat negara.
Pemerintah dan aparat tidak menjamin kebutuhan hidup warga negaranya. Sementara Pendekatan yang dilakukan pemerintah dan aparat terhadap warga melanggar peraturan selama pandemi ini cenderung represif. Pemerintah berpikir dengan pikiran yang sangat kolot, menganggap situasi darurat kesehatan ini sama dengan darurat sipil atau militer. Sehingga warga banyak yang direpresi dan menerima berbagai tindak kekerasan, sedangkan warga butuh uang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dengan ini, jelas kita mengerti pemerintah memang tak peduli dengan kekhawatiran rakyat Indonesia yang takut mati kelaparan. Barangkali memang benar kelaparan tidak ramai diperbincangkan oleh pemerintah ataupun media mainstream, karena kelaparan tidak akan membunuh orang kaya, terlebih seperti pejabat pemerintah.
Jika pemerintah memiliki hati nurani, maka sudah semestinya pemerintah menyuplai kebutuhan hidup dasar masyarakat dan makanan hewan ternak yang ada di wilayah karantina tersebut. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, “Dengan begitu masyarakat bisa berdiam diri ditempat tinggal dan setidaknya bisa tetap tenang karena ada yang mencukupi biaya kehidupan dasarnya.” Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan tersebut sangat progresif dan berpihak kepada rakyat di situasi pandemi seperti ini, namun pada kenyataannya pemerintah tidak mau melaksanakan apa yang sudah diundangkan tersebut.
Pemerintah Melanggar Hak Kesehatan Masyarakat
Secara konstitusional, hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Di antaranya disebutkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
Namun apa yang terjadi di Indonesia saat pandemi covid meledak dan menjadi episentrum pandemi dunia, beberapa masyarakat tidak bisa dirawat di rumah sakit karena rumah sakit penuh, sehingga harus menunggu diluar atau harus berkeliling mencari rumah sakit lewat Aplikasi/telephone. Beberapa dari mereka tak kunjung mendapatkan rumah sakit, sehingga harus berkeliling secara manual. Hal itulah yang membuat banyak pasien covid meninggal dunia di jalan, di rumah sakit saat menunggu kamar, atau meninggal saat memilih melakukan perawatan di rumah karena kelelahan menunggu rumah sakit.
Ketika rumah sakit atau fasilitas kesehatan tidak lagi dapat menampung pasien, isolasi mandiri di rumah diharapkan bisa menjadi alternatif untuk perawatan pasien, tapi pada kenyataannya banyak pasien yang tidak tertolong. Berdasarkan data laporcovid19 pada 24 Juli 2021, ada sebanyak 2.491 orang meningal dunia saat isolasi mandiri/di luar fasilitas kesehatan. Pasien isolasi mandiri dirawat tanpa pemberian pengawasan dan pelayanan kesehatanyang memadai. Banyaknya pasien isolasi mandiri yang meninggal dunia menandakan tidak ada perhatian serius kepada pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah.
Tak hanya pasien, berdasarkan data dari laporcovid19 pada 10 Agustus 2021, ada 1646 tenaga kesehatan yang meninggal dunia karena covid. Hal ini dikarenakan kelelahan tak sanggup menangani pasien yang membludak.
Komitmen pemerintah masih lemah dalam menjalankan 3T, yaitu testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan), dan treatment (perawatan). Vaksin di beberapa daerah kehabisan, sementara di daerah lain bisa melakukan vaksin dengan leluasa. Hal tersebut tentu tidak bijak, karena sesungguhnya semua masyarakat harus mendapatkan vaksin, kelompok lansia sabagai prioritas vaksin harus ditingkatkan terus. Pada dasarnya kita tidak akan mencapai herd immunity jika masih banyak kalangan yang tidak mendapatkan vaksin. Selain itu di berbagai daerah muncul vaksinasi berbayar yang tidak hanya dilakukan oleh oknum individu, tetapi juga perusahaan.
Selain itu Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mencatat lonjakan kasus covid mulai terjadi di enam provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali dalam sebulan terakhir. Enam provinsi tersebut meliputi, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Riau, dan Kalimantan Selatan. Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan penanganan di luar Pulau Jawa dan Bali berbeda karena lebih sulit. Hal tersebut disebabkan dukungan infrastruktur kesehatan yang belum memadai dan tantangan lainnya yang cukup besar di luar Jawa-Bali. Ini akan menjadi memperpanjang adanya ketimpangan kesehatan dan kematian massal yang tidak terbayangkan.
Ini adalah beberapa catatan buruk dunia kesehatan Indonesia yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah, bisa jadi masih ada banyak catatan yang mungkin belum tercatat di sini.
Tidak ada Keterbukaan Informasi Publik
Informasi tentang pandemi covid adalah informasi yang wajib diumumkan secara serta merta oleh badan publik yang memiliki kewenangan dan menguasai informasi tentang covid, karena covid dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Dasar hukum mengenai ketentuan ini, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Namun pada kenyataannya keterbukaan informasi publik dalam masa pandemi ini, masih dianggap menjadi momok berbahaya, dalam penanganan pandemi Covid di Indonesia. Aparat dan pemerintah melakukan represi terhadap jurnalis, sehingga menghambat peran media sebagai pengawas kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi.
Inisiator LaporCovid-19 sekaligus jurnalis Kompas, Ahmad Arif, artikelnya seputar Covid-19 diberi label hoaks selama 2020-2021. Salah satu artikelnya berjudul ”63 Pasien di RSUP Dr Sardjito Meninggal dalam Sehari” tayang pada 4 Juli 2021. Padahal kerja Jurnalis dilindungi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Selanjutnya Melalui Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, saat mengumumkan perpanjangan PPKM, Senin (9/8/2021). Pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19. Pasalnya, ditemukan masalah dalam input data sehingga menyebabkan akumulasi dari kasus kematian di beberapa minggu sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan bahwa kebijakan itu jelas keliru, selain itu juga berbahaya karena indikator kematian adalah indikator kunci adanya suatu wabah untuk melihat bukan hanya performa intervensi di hulu, tapi juga menilai derajat keparahan suatu wabah. Alih-alih data kematian yang menumpuk dan memunculkan ketidakakuratan, seharusnya tidak membuat pemerintah menghilangkannya begitu saja. Data kematian tersebut cukup diperbaiki dengan secepat dan seakurat mungkin tanpa perlu menghilangkannya. tujuan penanganan pandemi adalah untuk meminimalisir angka kematian. Bahkan harus menghilangkan angka kematian yang diakibatkan oleh pandemi.
Berdasarkan hal ini, harusnya pemerintah sejak awal melakukan komunikasi krisis yang baik di masa pandemi. Komunikasi krisis membutuhkan keterbukaan informasi tentang Covid-19, pengakuan dan kejujuran dari pemerintah terkait penanganan, sehingga bisa menciptakan edukasi risiko kepada masyarakat luas.
Masyarakat tidak menjadi prioritas Utama
Beberapa catatan di atas adalah bukti bahwa di tengah pandemi, masyarakat bukanlah prioritas utama dalam kinerja pemerintah. Hal ini diperjelas dengan pemerintah yang mengesahkan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang tergesa-gesa pada 5 oktober 2020, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Membangun PLTU di tengah pandemi, pemerintah menyisihkan anggaran untuk mengecat pesawat Jokowi, dana bansos dikorupsi oleh menteri sosial, sementara banyak masyarakat yang menderita dibatasi PPKM tanpa tunjangan hidup, kesulitan mencukupi kebutuhan dasar dan terancam terinveksi virus covid.
Jika pemerintah memang memprioritaskan kepentingan masyarakat, harusnya pemerintah menerapkan lockdown yang sudah diatur oleh Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan. Membuka informasi seluas-luasnya, karena informasi informasi bisa mengedukasi masyarakat, bukan malah meminta rakyat untuk menelan ludah dan bersabar mengahadapi wabah yang hadir di tengah kita. Sungguh ini adalah masalah yang serius, kita tidak bisa menjamin kesalamatan kita dalam pandemi ini, pun kita tidak tahu sampai kapan kebijakan pemerintah membatasi kegiatan masyarakat yang membuat rakyat kecil hanya ada pada dua pilihan, mati kelaparan atau mati karena virus. Untuk itu penting bagi kita untuk saling bersolidaritas dan saling menguatkan, perkuat pertahanan rakyat bantu rakyat, warga bantu warga, mengumpulkan donasi, membantu kebutuhan umum, membantu pasien yang sakit, kita tidak bisa berharap lagi pada pemerintah. Ini adalah perayaan kemerdekaan Indonesia yang muram, dan kado kemerdekaan dari pemerintah kita kali ini adalah kematian massal saudara-saudara kita, akibat salah mengambil kebijakan.
Penulis: Najmu Tsaqiib