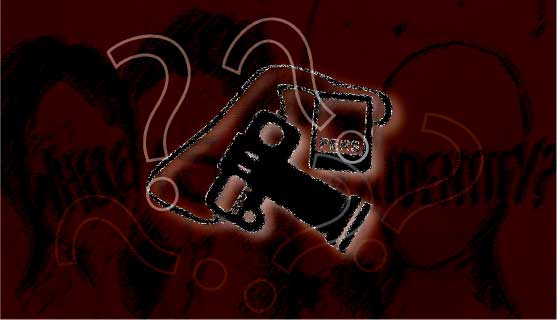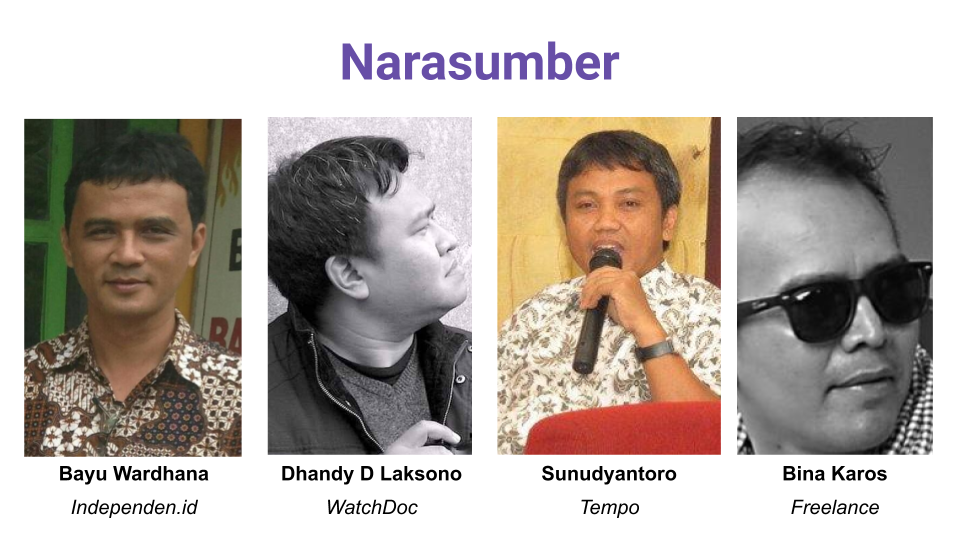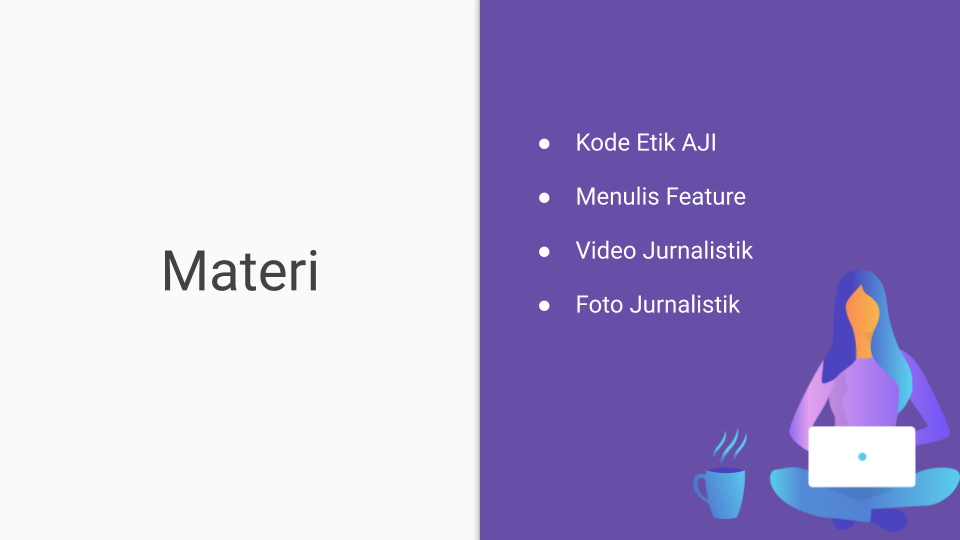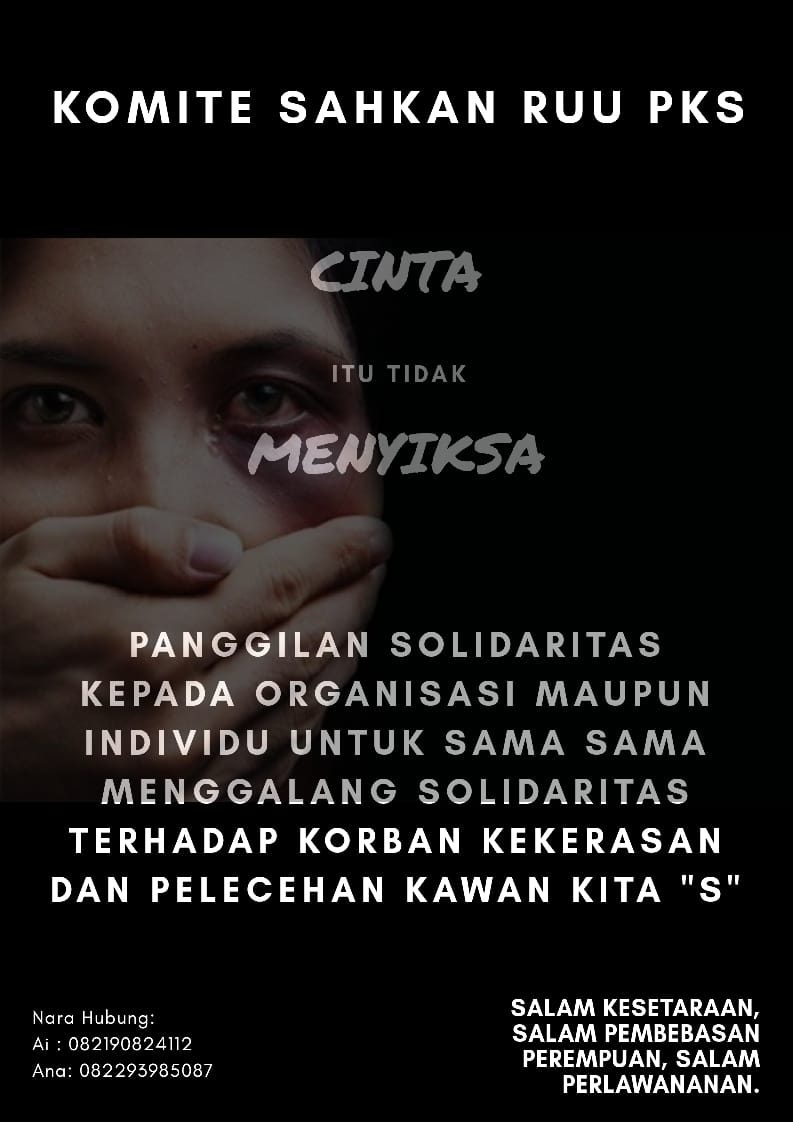I. Pengantar Advokasi Kasus Pelecehan Seksual
14 Februari 2020, Badan Pekerja Advokasi Nasional Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (BP Advokasi Nas PPMI) mendapatkan laporan dari salah satu anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) (selanjutnya disebut pelapor) terkait pelecehan seksual yang dilakukan oleh Muhammad Shofi Tamam, Sekjend PPMI Dewan Kota (DK) Semarang. Pelapor menjelaskan bahwa ada lebih dari satu penyintas dari pelecehan seksual yang dilakukan Tamam.
Pelapor memberikan keterangan itu kepada BP Advokasi Nas PPMI ketika PPMI mengadakan Kongres Nasional ke 15 PPMI di Madura. Pelapor bercerita kepada BP Advokasi Nas PPMI supaya PPMI maupun lembaga lainnya bisa menghadirkan lingkungan yang ramah perempuan dengan mengadili serta membuat jera pelaku, melindungi penyintas, dan mendengar tuntutan penyintas.
Setelah mendapatkan keterangan dari pelapor, BP Advokasi Nas PPMI mengajak seluruh BP Nas PPMI yang hadir di Kongres untuk membahas hal tersebut. Setelah membahas keterangan dari pelapor, BP Advokasi Nas PPMI membentuk tim advokasi kasus kekerasan seksual. Tim advokasi kasus kekerasan seksual terdiri dari seluruh BP Nas PPMI dan BP Advokasi PPMI DK Malang. Kemudian, pada tanggal 15 Februari 2020, forum Kongres dipending ketika Laporan Pertanggungjawaban BP Advokasi Nas PPMI. Forum dipending dengan alasan ada kasus yang harus segera diselesaikan oleh BP Nas PPMI. Setelah forum dipending, BP Advokasi Nas PPMI menemui Tamam untuk melakukan proses verifikasi dan memberi ruang pembelaan pelaku.
Hasil proses dari ruang pembelaan pelaku kemudian dibahas oleh seluruh BP Nas PPMI. Lalu pada 16 Februari 2020, BP Nas PPMI melalui Rahmat Ali selaku Sekjend Nas PPMI memberikan keputusan kepada Tamam untuk memenuhi tuntutan penyintas yang salah satunya adalah memberhentikan Tamam dari jabatan Sekjend PPMI DK Semarang.
Berikut kami sampaikan ruang pembelaan pelaku, hasil pembahasan dan keputusan BP Nas PPMI kepada Tamam, serta advokasi bersama AJI Semarang dan LRC-KJHAM Semarang.
II. Ruang Pembelaan Pelaku
BP Advokasi Nas PPMI memberikan ruang pembelaan pelaku kepada Tamam pada tanggal 15 Februari 2020. Pihak yang hadir di ruang pembelaan pelaku itu adalah Wahyu sebagai BP Advokasi Nas PPMI, Tamam sebagai terduga pelaku pelecehan dan Fitron sebagai BP Advokasi PPMI DK Malang yang membantu BP Nas PPMI dalam advokasi kasus. Selain itu ada pengurus PPMI DK Semarang yaitu Gunawan (LPM Dimensi) sebagai BP Advokasi PPMI DK Semarang, Bagas (LPM Suprema), Yusron (LPM Gema Keadilan) dan Diki (LPM Vokal).
Ruang pembelaan pelaku dimulai dengan proses verifikasi keterangan pelapor kepada Tamam sebagai terduga pelaku pelecehan seksual. Ketika proses verifikasi, Tamam membenarkan bahwa dia melakukan pelecehan kepada penyintas. Tamam juga membenarkan bahwa dia menggunakan relasi kuasanya di LPM Menteng, PPMI DK Semarang dan Aliansi Jurnalis Independen(AJI)Semarang (berupa sekretariat LPM, kantor AJI Semarang), maupun kegiatan-kegiatan Persma seperti malam keakraban (Makrab) dan kunjungan LPM untuk melakukan tindakan pelecehan kepada penyintas.
Tamam juga mengakui bahwa dia melakukan pelecehan kepada penyintas dengan mengajaknya camping (dengan tenda pinjaman milik AJI Semarang) maupun ketika membonceng penyintas dengan motor. Selain itu, Tamam juga mengakui bahwa dia tidak hanya melakukan pelecehan ke beberapa anggota LPM, tapi Tamam juga melakukan pelecehan ke penyintas dari organisasi di luar LPM atau PPMI DK Semarang.
Selain membenarkan tindakan pelecehan yang dilakukan, Tamam juga memberi klarifikasi atas tindakannya itu. Klarifikasi pertama, pelecehan di atas motor ketika membonceng penyintas sepulang dari kunjungan LPM. Tamam tidak merasa melakukan pelecehan karena waktu itu ia meminta penyintas untuk pegangan ke perut Tamam, namun penyintas menolak. Kemudian ketika Tamam mempercepat laju motor, penyintas tiba-tiba memeluknya tanpa Tamam memintanya.
Klarifikasi kedua ketika pelecehan di tenda waktu camping, di sekretariat LPM Menteng dan kantor AJI Semarang. Tamam mengatakan kalau penyintas tidak menolak kontak fisik (pelukan maupun ciuman) yang dilakukannya dan penyintas membalas kontak fisik itu. Sehingga, Tamam merasa kalau dia tidak melakukan pelecehan karena penyintas membalas kontak fisik itu.
Klarifikasi ketiga yaitu tentang pelecehan yang terus menerus dilakukan Tamam kepada penyintas. Tamam terus melakukan pelecehan itu karena dia menganggap bahwa yang dilakukannya bukan pelecehan, tapi suka sama suka karena penyintas juga membalas kontak fisiknya. Tamam juga mengatakan kalau penyintas merasa nyaman dan menikmati kontak fisik itu. Selain itu, Tamam mengatakan kalau penyintas juga pernah mengajaknya camping, sehingga Tamam merasa bukan hanya dia yang salah, tapi penyintas juga salah.
Setelah mendengar klarifikasi dari Tamam, Wahyu melakukan verifikasi kembali terhadap klarifikasi Tamam dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, Wahyu menanyakan apakah kontak fisik yang dilakukan Tamam itu melalui persetujuan (consent) dari penyintas? Lalu Tamam menjawab bahwa dia tidak meminta persetujuan dalam bentuk verbal (kata-kata) untuk melakukan kontak fisik ke penyintas, tapi Tamam langsung melakukan kontak fisik dengan gerakan tubuhnya.
Kedua, Wahyu menanyakan ajakan camping Tamam ke penyintas, apakah Tamam mengajak camping dengan penyintas untuk melakukan kontak fisik itu? Kemudian Tamam menjawab bahwa dia tidak mengajak camping penyintas untuk melakukan kontak fisik itu. Begitu juga penyintas, Tamam mengatakan kalau penyintas tidak mengajak camping Tamam untuk melakukan kontak fisik itu. Tamam maupun penyintas saling mengajak camping untuk mengerjakan tugas atau untuk refreshing saja.
Ketiga, Wahyu menanyakan kepada Tamam siapa yang pertama dan paling sering mengajak camping serta melakukan kontak fisik? Lalu Tamam menjawab bahwa dia sendiri yang pertama dan paling sering mengajak camping serta melakukan kontak fisik. Sedangkan penyintas hanya mengajak camping sekali saja, itu pun tidak jadi camping.Penyintas juga tidak pernah mengajak atau memulai untuk melakukan kontak fisik. Tamam sendiri mengatakan kalau penyintas tidak pernah berkata merasa nyaman dan menikmati kontak fisik itu.
Keempat, Wahyu menanyakan kepada Tamam, apakah dia tahu bahwa penyintas merasa terpaksa, takut dan tidak punya pilihan ketika Tamam melakukan semua kontak fisik itu sampai penyintas mau lompat dari motor ketika Tamam memaksa penyintas untuk memeluknya? Kemudian Tamam mengiyakan kalau dia mengetahui semua itu. Tamam mengatakan kalau dia baru mengetahui ketidaknyamanan penyintas setelah penyintas menolak kontak fisik dari Tamam dengan tegas. Setelah mengetahui kalau penyintas merasa tidak nyaman dan berani menolak kontak fisiknya, Tamam mengatakan beberapa bulan setelah Reuni Nasional dan Dies Natalis PPMI (25 – 28 Oktober 2019 di Semarang) selesai, dia tidak melakukan lagi kontak fisik itu ke penyintas.
Setelah melakukan verifikasi kembali terhadap klarifikasi Tamam dan mendengar jawaban-jawabannya, Wahyu menyampaikan bahwa Tamam juga sudah mengakui tindakan pelecehan yang dilakukannya, sehingga Tamam harus memenuhi tuntutan penyintas untuk memberhentikannya dari jabatan Sekjend PPMI DK Semarang. Selain itu, Tamam juga harus memenuhi tuntutan lain dari penyintas yaitu meminta maaf secara langsung kepada semua penyintas yang pernah dilecehkan serta kepada publik dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan pelecehan lagi kepada siapapun. Serta menanggung biaya pemulihan semua penyintas yang pernah dilecehkan.
Namun, Tamam tidak terima dengan tuntutan penyintas untuk berhenti atau mengundurkan diri dari Sekjend PPMI DK Semarang. Tamam memberatkan pemberhentian itu dengan alasan kalau dia tidak sepenuhnya salah tapi penyintas juga salah, serta alasan-alasan lain dari klarifikasi yang sudah disebutkan sebelumnya.
Melihat Tamam yang tidak terima dengan konsekuensi itu, Wahyu membuka sesi dialog untuk mendengar pendapat dari Fitron, Gunawan, Bagas, Yusron dan Diki.
Bagas yang pertama menyampaikan pendapatnya. Bagas mengatakan kalau dia kecewa dengan tindakan Tamam. Bagi Bagas, tindakan Tamam adalah tindakan yang sangat tidak etis. Bagas menilai kalau tindakan Tamam tidak bisa dilanjutkan lagi, kalau dilanjutkan tentu menjadi kebiasaan yang buruk. Bagas menekankan kalau penyintas adalah seorang wanita, kalau dipaksa melakukan kontak fisik, pasti dia akan takut, dia ingin menolak tapi dia diam dan tidak bisa berbuat apa-apa.
Bagas meminta supaya Tamam lebih merasakan rasa sakitnya penyintas ketika dilecehkan. Bagi Bagas, penyintas mungkin bisa menahan rasa sakitnya, tapi kalau suatu saat nanti dia tidak menahannya, dia bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Bagas memperingatkan Tamam supaya tidak terus melakukan pelecehan kepada wanita lain. Menurut Bagas, perempuan harus lindungi, bukan malah dimanfaatkan.
Setelah itu, Diki memberi pertanyaan kepada Tamam, apakah Tamam bersedia untuk tidak memojokkan penyintas setelah forum ruang pembelaan ini? Lalu ketika Tamam memojokkan penyintas setelah forum ruang pembelaan ini apakah Tamam mau tanggungjawab? Kemudian, Tamam mengatakan kalau penyintas mempunyai hak untuk melaporkan ke BP Advokasi Nas PPMI sehingga Tamam bersedia untuk tidak memojokkan penyintas dengan meminta klarifikasi dan sebagainya. Tamam juga akan bertanggungjawab kalau setelah forum ruang pembelaan dia malah memojokkan penyintas.
Setelah itu, Yusron menyampaikan pendapatnya. Menurut Yusron, dia tidak ingin tindakan pelecehan ini terjadi lagi, karena itu akan berdampak ke nasib PPMI DK Semarang.
Kemudian, Gunawan memberikan pendapatnya. Dia mempertanyakan pemberhentian Tamam dari Sekjend PPMI DK Semarang. Gunawan bertanya kepada Wahyu, apakah tuntutan penyintas untuk memberhentikan Tamam dari Sekjend PPMI DK Semarang tidak mempertimbangkan faktor lain? Kemudian, Wahyu menjawab kalau penyintas berhak menuntut Tamam untuk berhenti dari Sekjend PPMI DK Semarang. Kemudian yang berwenang untuk memberi sanksi pemberhentian itu adalah Rahmat Ali, selaku Sekjend Nas PPMI. Hal ini sesuai Anggaran Rumah Tangga (ART) PPMI Pasal 63 tentang Mekanisme Pemberian Sanksi ayat 1 yang menjelaskan, “sanksi diberikan oleh Sekjend Nasional atas pertimbangan Koordinator Wilayah”.
Lalu Gunawan menanyakan lagi, apakah sanksi itu sudah menjadi hasil keputusan pengurus Nas PPMI? Kemudian Wahyu menjawab bahwa sanksi itu belum bisa diberikan, karena yang dilakukan Wahyu adalah pemberian ruang pembelaan pelaku kepada Tamam sebelum Tamam diberi sanksi. Hal ini sesuai Anggaran Rumah Tangga (ART) PPMI Pasal 63 tentang Mekanisme Pemberian Sanksi ayat 2 yang menjelaskan, “sebelum sanksi dijatuhkan, setiap anggota berhak melakukan pembelaan”.
Menambahi pertanyaan Gunawan, Tamam kembali menyatakan ketidakterimaannya dengan tuntutan penyintas. Tamam mengakui kalau dia melanggar AD/ADT, tapi Tamam mempertanyakan sanksi pemberhentian yang akan dia terima. Tamam membandingkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PPMI DK lainnya ketika tidak membayar iuran kas rutin ke pengurus Nas PPMI. Menurut Tamam, masalah pelecehan ini terlalu dibesar-besarkan karena PPMI DK lainnya juga melanggar AD/ADT dengan tidak membayar iuran kas rutin, tapi hanya ditegur oleh pengurus Nas PPMI, sedangkan ketika melakukan pelecehan dia harus diberhentikan oleh pengurus Nas PPMI.
Tamam kembali mengatakan bahwa dia merasa tidak sepenuhnya salah. Tamam merasa kalau dia salah, tapi penyintas juga salah karena penyintas pernah mengajaknya camping, penyintas juga membalas kontak fisiknya dan Tamam merasa bahwa kontak fisik itu didasari suka sama suka. Bahkan, Tamam juga menyatakan tuntutan balik kepada penyintas. Tamam menuntut supaya penyintas merasa biasa-biasa saja dan tidak tertekan. Bagi Tamam, penyintas merasa tertekan karena tindakan penyintas sendiri yang membalas kontak fisik itu dan pernah mengajak Tamam camping.
Menurut Tamam, tuntutan penyintas untuk memberhentikannya dari Sekjend PPMI DK Semarang terlalu berat. Tamam mengatakan kalau meminta maaf saja ke penyintas itu sudah cukup. Tidak hanya itu, Tamam juga mengungkit sifat penyintas yang mirip anak kecil. Tamam mengatakan kalau penyintas suka dekat-dekat dengannya sehingga Tamam merasa terpancing untuk melakukan kontak fisik ke penyintas. Tamam merasa kalau penyintas itu awalnya bersikap cuek, maka Tamam akan cuek dan tidak akan melakukan kontak fisik itu.
Tamam terus menyatakan keberatannya dengan alasan bahwa dia sudah bertahun-tahun mengabdi di PPMI, tapi hanya karena pelecehan yang dia lakukan dia harus diberhentikan dari Sekjend PPMI DK Semarang. Kemudian, Tamam juga mengatakan kalau tuntutan pemberhentiannya yang berdasarkan AD/ART PPMI itu tidak logis.
Selain itu, bagi Tamam tuntutan pemberhentian itu tidak adil karena tuntutan itu hanyalah asumsi penyintas yang tidak relevan. Tamam merasa kalau penyintas tidak melihat apa yang dilakukan Tamam di PPMI. Bahkan Tamam menyamakan sikap penyintas seperti orang putus pacaran yang merasa tertekan dan ingin bunuh diri, serta memiliki nuansa benci sehingga menuntut Tamam seperti itu. Dalam pertimbangan Tamam, dia sudah melakukan banyak hal, tapi karena hal kecil ini, semuanya ambruk.
Menanggapi pendapat Gunawan dan Tamam, Wahyu menjelaskan bahwa kasus pelecehan seksual tidak bisa dibandingkan dengan masalah pelanggaran pembayaran iuran kas rutin PPMI. Mekanisme penyelesaian masalah pelanggaran pembayaran iuran kas rutin jelas berbeda dengan mekanisme penyelesaian kasus pelecehan seksual. Sasaran iuran kas rutin adalah PPMI DK, bukan personal seperti Sekjend PPMI DK. Kemudian pihak yang berwenang adalah Biro Umum Bendahara Nas PPMI, seperti yang dijelaskan dalam ART PPMI Pasal 17 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Biro Umum berwenang untuk menarik iuran anggota.
Sedangkan dalam kasus pelecehan seksual, sasarannya adalah Sekjend PPMI DK. Kemudian pihak yang berwenang memberi sanksi adalah Sekjend Nas PPMI. Kemudian yang lebih penting lagi adalah penilaian pelanggaran antara pembayaran iuran kas dan kasus pelecehan seksual itu didasarkan oleh masing-masing dampak yang diakibatkan. Kalau pelanggaran pembayaran iuran kas rutin PPMI dampaknya pada keuangan BP Nas PPMI dan diperbaiki dengan cara menekan PPMI DK untuk membayar iurannya. Tapi kalau kasus pelecehan seksual, dampaknya pada kondisi psikologis penyintas. Sehingga dampak dari pelecehan seksual itu diperbaiki dengan pemulihan kondisi psikologis penyintas dan pemenuhan keadilan bagi penyintas.
Wahyu juga menjelaskan pertimbangan lain ketika Tamam tetap tidak terima dengan tuntutan penyintas. Ada pertimbangan kalau PPMI, terutama Tamam sebagai pelaku, akan mendapatkan tekanan dari individu atau organisasi di luar PPMI. Individu atau organisasi di luar PPMI itu bisa saja menekan PPMI karena menilai PPMI tidak bisa menindak tegas pelaku pelecehan seksual dan tidak bisa menciptakan ruang yang aman bagi perempuan. Selain itu, PPMI bisa dianggap malah melindungi pelaku pelecehan seksual.
Menanggapi penjelasan Wahyu, Tamam mengatakan kalau dia sudah menyadari dampak itu. Tamam mengatakan kalau dia sudah berubah dan tidak pernah melakukan pelecehan lagi mulai beberapa bulan lalu.
Kemudian, Fitron menjelaskan kembali bahwa forum tersebut adalah ruang pembelaan pelaku kepada Tamam. Jadi, hasil forum ruang pembelaan pelaku ini perlu segera dikembalikan kepada pengurus Nas PPMI untuk ditindaklanjuti.
Menanggapi penjelasan Fitron, Wahyu mengatakan kalau di ruang pembelaan pelaku ini Tamam dan pengurus PPMI DK Semarang lain bisa menyatakan pendapat termasuk menolak tuntutan penyintas beserta alasan penolakannya. Kemudian sebelum menutup forum ruang pembelaan pelaku, Wahyu menayakan kembali kepada Tamam, apakah dia bersedia menerima tuntutan penyintas? Lalu Tamam mengatakan kalau dia tetap tidak menerima dengan alasan-alasan yang sudah dia sebutkan sebelumnya. Mendengar jawaban akhir Tamam, Wahyu menutup forum ruang pembelaan pelaku itu.
III. Hasil Pembahasan dan Keputusan BP Nas PPMI
BP Nas PPMI kemudian membahas hasil dari ruang pembelaan pelaku pada 15 Februari 2020. Kemudian dari pembahasan itu kami mencatat tiga poin penting, yaitu:
- Berdasarkan pembahasan kronologi dari penyintas dan hasil ruang pembelaan, Tamam melakukan pelecehan seksual kepada penyintas. Mengacu pada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.
Tamam sendiri membenarkan bahwa dia melakukan pelecehan kepada penyintas. Tamam juga membenarkan bahwa dia menggunakan relasi kuasanya di LPM Menteng, PPMI DK Semarang dan AJI (berupa sekretariat LPM dan kantor AJI Semarang), maupun kegiatan-kegiatan pers mahasiswa seperti malam keakraban (Makrab), dan kunjungan LPM untuk melakukan tindakan pelecehan kepada penyintas.
Tamam juga mengakui bahwa dia melakukan pelecehan kepada penyintas dengan mengajaknya camping (dengan tenda pinjaman milik AJI Semarang) maupun ketika membonceng penyintas dengan motor. Selain itu, Tamam juga mengakui bahwa dia tidak hanya melakukan pelecehan ke beberapa anggota LPM, tapi Tamam juga melakukan pelecehan ke penyintas dari luar LPM maupun PPMI DK Semarang.
- Tamam berulang kali melakukan kontak fisik ke penyintas tanpa persetujuan (consent) dari penyintas. Tamam sendiri mengakui kalau dia tidak meminta persetujuan dalam bentuk verbal (kata-kata) untuk melakukan kontak fisik ke penyintas, tapi dia langsung melakukan kontak fisik dengan gerakan tubuhnya. Tamam tidak menerima kondisi penyintas yang tertekan, terpaksa, takut dan tidak punya pilihan dengan kontak fisik yang terus dilakukannya.
Bagi Tamam kontak fisik yang dilakukannya itu didasari oleh rasa suka sama suka karena penyintas membalas kontak fisik dari Tamam dan pernah mengajak Tamam camping. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Tamam sebelumnya yang mengakui bahwa dia melakukan pelecehan dan mengetahui bahwa penyintas yang tertekan, terpaksa, takut dan tidak punya pilihan dengan kontak fisik yang terus dilakukannya.
Seharusnya, ketika mengetahui kondisi penyintas yang tertekan, Tamam mengakui sepenuhnya bahwa tindakannya itu salah karena dia melakukan pemaksaan kepada penyintas, bukan malah mengatakan bahwa tindakannya didasari rasa suka sama suka. Apalagi, Tamam sendiri mengakui kalau penyintas tidak pernah mengajaknya camping untuk melakukan kontak fisik, tapi penyintas mengajaknya camping untuk mengerjakan tugas atau untuk refreshing saja.
- Tamam malah menyalahkan penyintas (victim blaming). Tamam mendiskreditkan tuntutan penyintas karena Tamam merasa tuntutan itu tidak adil dan tuntutan itu hanyalah asumsi penyintas yang tidak relevan. Tamam merasa kalau penyintas tidak melihat apa yang dilakukannya di PPMI.
Bahkan Tamam menyamakan sikap penyintas seperti orang putus pacaran yang merasa tertekan dan ingin bunuh diri, serta memiliki nuansa benci sehingga menuntut Tamam seperti itu. Dalam pertimbangan Tamam, pelecehan yang dilakukannya adalah hal kecil dan tuntutan pemberhentiannya itu terlalu dibesar-besarkan.
Upaya mendiskreditkan penyintas itu kemudian dilanjutkan Tamam dengan menyalahkan penyintas. Tamam mengatakan kalau sifat penyintas mirip anak kecil karena penyintas suka dekat-dekat dengannya, sehingga Tamam merasa terpancing untuk melakukan kontak fisik ke penyintas. Tamam merasa kalau penyintas itu awalnya bersikap cuek, maka Tamam akan cuek dan tidak akan melakukan kontak fisik itu.
Tamam mengatakan bahwa dia merasa tidak sepenuhnya salah. Tamam terus menyalahkan penyintas dengan alasan yang sama, bahwa penyintas pernah mengajaknya camping, penyintas juga membalas kontak fisiknya dan Tamam merasa bahwa kontak fisik itu didasari suka sama suka. Bahkan, Tamam juga menyatakan tuntutan balik kepada penyintas. Tamam menuntut supaya penyintas merasa biasa-biasa saja dan tidak tertekan. Bagi Tamam, penyintas merasa tertekan karena tindakan penyintas sendiri yang membalas kontak fisik itu dan pernah mengajak Tamam camping. Semua alasan yang digunakan Tamam untuk menyalahkan penyintas itu kemudian dijadikan dasar bahwa dia tidak menerima tuntutan pemberhentian dari Sekjend PPMI DK Semarang dan mengatakan kalau meminta maaf saja ke penyintas itu sudah cukup.
Berdasarkan pembahasan kronologi kekerasan seksual dari penyintas, hasil ruang pembelaan pelaku dan tiga poin penting dari ruang pembelaan pelaku, maka kami BP Nas PPMI memutuskan untuk:
- Memberhentikan Muhammad Sofi Tamam dari jabatan Sekjend PPMI DK Semarang.
- Menuntut Muhammad Sofi Tamam untuk meminta maaf secara langsung kepada semua penyintas yang pernah dilecehkan serta kepada publik dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan pelecehan lagi kepada siapapun.
- Menuntut Muhammad Sofi Tamam untuk menanggung biaya pemulihan semua penyintas yang pernah dilecehkan.
- Mengimbau kepada seluruh PPMI di masing-masing Dewan Kota untuk bersolidaritas dalam mendukung penyelesaian kasus pelecehan seksual yang dialami oleh pers mahasiswa, mendukung pemenuhan tuntutan penyintas, bertanggungjawabmendampingi penyintas dalam proses pemulihan, menciptakan ruang yang aman bagi penyintas, serta tidak memberi ruang bagi Tamam maupun segala bentuk tindakan kekerasan seksual.
Pada 16 Februari 2020, Tamam sudah diberhentikan dari Sekjend PPMI DK Semarang. Kemudian, PPMI DK Semarang mengadakan Musyawarah Kota Luar Biasa (Muskotlub) pada 1 Maret 2020. Hasil Muskotlub PPMI DK Semarang memutuskan Amiruddin Nur Yusron dari LPM Gema Keadilan sebagai Sekjend PPMI DK Semarang.
IV. Advokasi bersama AJI Semarang dan LRC-KJHAM Semarang
BP Nas PPMI (kemudian menjadi Demisioner PPMI karena kepengurusannya sudah selesai setelah Kongres PPMI di Madura) melanjutkan advokasi bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang. Pada 4-9 Maret 2020, Rahmat Ali dan Wahyu (perwakilan Demisioner PPMI) bertemu dengan AJI Semarang untuk membahas pemulihan dan pemenuhan keadilan bagi penyintas. AJI Semarang menyarankan PPMI untuk bekerjasama juga dengan Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang dalam advokasi kasus pelecehan seksual ini. Kemudian Demisioner PPMI dan AJI Semarang bertemu dengan LRC-KJHAM Semarang untuk membahas advokasi kasus pelecehan seksual. Dalam pembahasan itu, disepakati bahwa tim advokasi akan menempuh jalur hukum sebagai bentuk tindakan tegas ke Tamam.
Setelah pembahasan dengan AJI Semarang dan LRC-KJHAM, Demisioner PPMI membentuk tim advokasi yang beranggotakan Wahyu dan Jenna (perwakilan Demisioner PPMI), Tsamrotul Ayu Masruroh dan Muhammad Firman (perwakilan BP Nas PPMI), Yusron dan Gunawan (perwakilan PPMI DK Semarang) bersama perwakilan AJI Semarang dan LRC-KJHAM. Pada 2 April 2020, tim advokasi melakukan pembahasan untuk mempersiapkan bukti, saksi dan keperluan lain yang berkaitan dengan pelaporan ke kepolisian. Selain itu, tim advokasi juga mempersiapkan aduan ke Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang (tempat Tamam berkuliah) terkait kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Tamam. Laporan tersebut akan ditembuskan ke Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah, dan LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah.
11 Juni 2020, tim advokasi mengirimkan surat pengaduan kasus pelecehan seksual ke Unwahas Semarang serta tembusan ke lembaga-lembaga lainnya. Pada 3 Agustus 2020, Komnas Perempuan memberikan surat rekomendasi kepada Unwahas Semarang untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap Tamam yang sudah melakukan pelecehan seksual. Kemudian, pada 2 September 2020, Unwahas Semarang memberikan sanksi Drop Out kepada Tamam dengan keterangan karena telah melanggar Kode Etik Mahasiswa dan Peraturan Akademik Unwahas Semarang.
Pada 17 September 2020 penyintas memutuskan untuk tidak melanjutkan advokasi jalur hukum. Penyintas merasa lelah menunggu dan bergantung kepada pendamping hukum dari LRC-KJHAM Semarang yang proses pelaporan ke kepolisiannya lambat. Pelaporan ke kepolisian seharusnya dilakukan pada 28 Agustus 2020, namun pelaporan tersebut tidak terealisasikan karena fokus pendamping hukum yang terpecah-pecah. Komunikasi yang kurang intens dari pendamping hukum terkait kepastian pelaporan ke kepolisian juga membuat penyintas lelah menunggu dan bergantung. Ketidakpastian tersebut berdampak pada kegiatan sehari-hari penyintas. Penyintas merasa tambah tertekan karena lelah menahan amarahnya dan merasa sulit untuk mengingat pengalaman getirnya itu.
V. Permintaan Maaf dan Evaluasi dari PPMI
PPMI menyadari keterlibatannya dalam kesalahan dalam advokasi yang membuat penyintas tambah tertekan. Maka dari itu PPMI menyatakan:
- Meminta maaf kepada penyintas karena belum bisa memberikan pendampingan yang maksimal untuk memulihkan kondisi mental serta mewujudkan keadilan bagi penyintas, malah pendampingan yang diberikan PPMI juga membuat penyintas tambah tertekan karena adanya ketidakpastian selama proses advokasi.
- Berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam advokasi kasus kekerasan seksual di PPMI.
- Melakukan evaluasi terhadap AD/ART dan Kode Etik PPMI sbagai salah satu bentuk komitmen dalam mendukung upaya penindakan tegas pelaku kekerasan seksual, menciptakan ruang yang aman bagi penyintas, serta melawan segala bentuk kekerasan seksual di PPMI.
- Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di PPMI.
- Mendorong setiap Lembaga Pers Mahasiswa untuk menciptakan ruang aman bagi penyintas dan melakukan pengawalan kasus kekerasan seksual yang ada di kampus.
Sampai rilis ini diterbitkan, Tamam masih tidak mengakui pelecehan seksual yang dilakukannya serta belum memenuhi tuntutan dari penyintas. Maka dari itu, PPMI mengimbau kepada seluruh PPMI di masing-masing Dewan Kota serta seluruh organisasi yang mana Tamam aktif di dalamnya untuk bersolidaritas dalam mendukung pemenuhan tuntutan penyintas, menciptakan ruang yang aman bagi penyintas, serta tidak memberi ruang bagi Tamam maupun segala bentuk tindakan kekerasan seksual.
Narahubung:
Tsamrotul Ayu Masruroh, Badan Pekerja Advokasi 2019-2020-085704248033
Wahyu Agung Prasetyo, Badan Pekerja Advokasi 2018-2019-089682373953
Amiruddin Nur Yusron Sekjend PPMI DK Semarang 2020-2021-089652294488