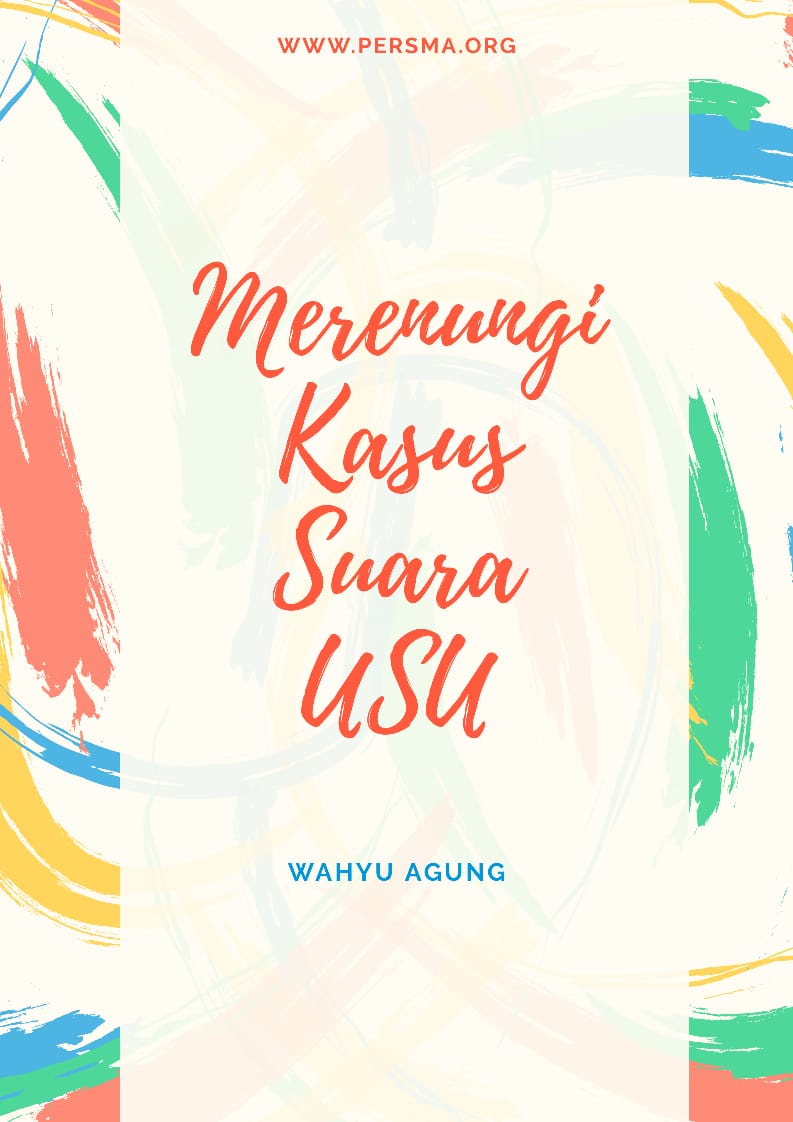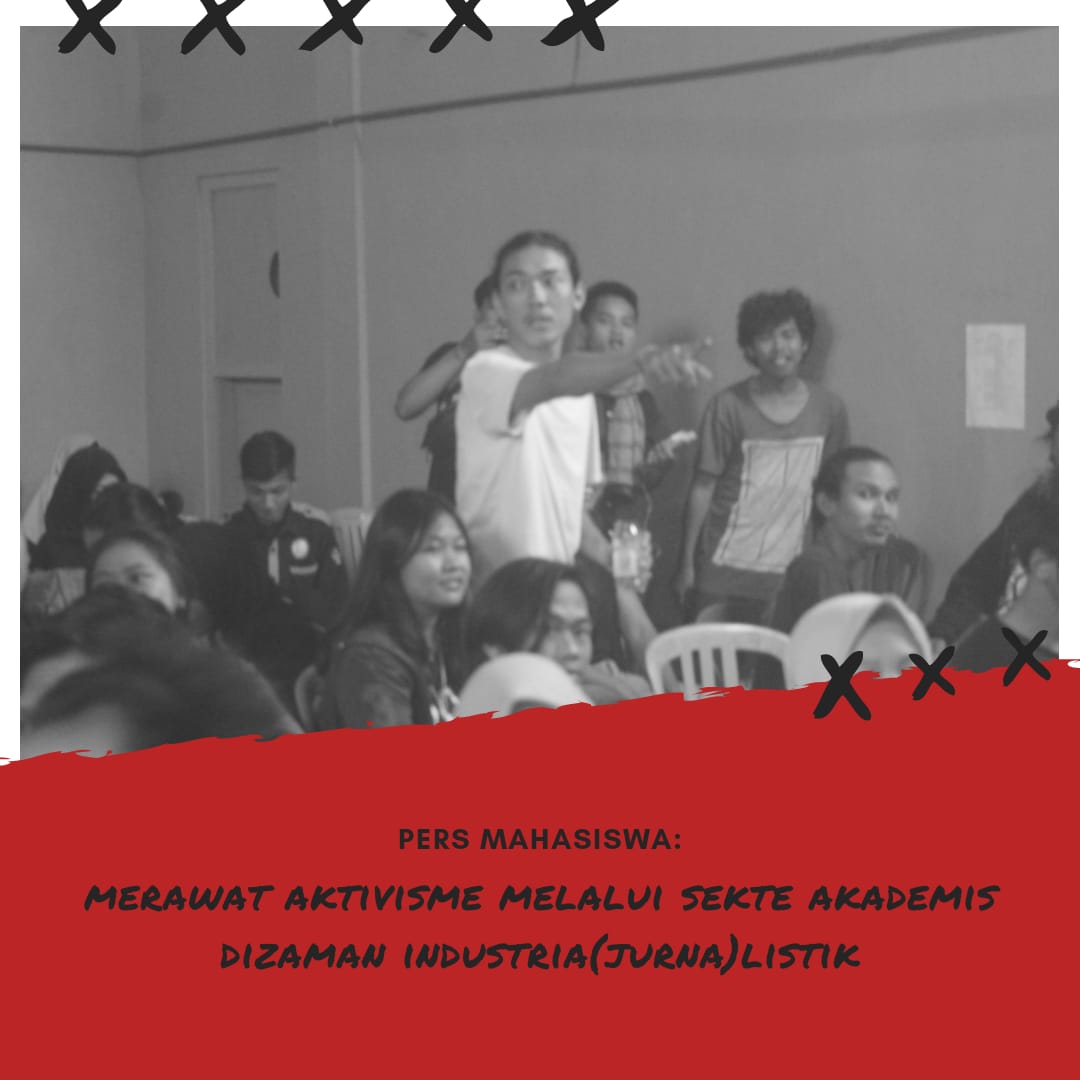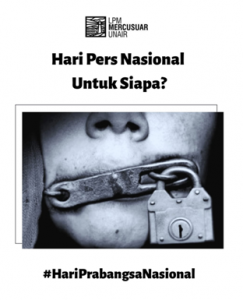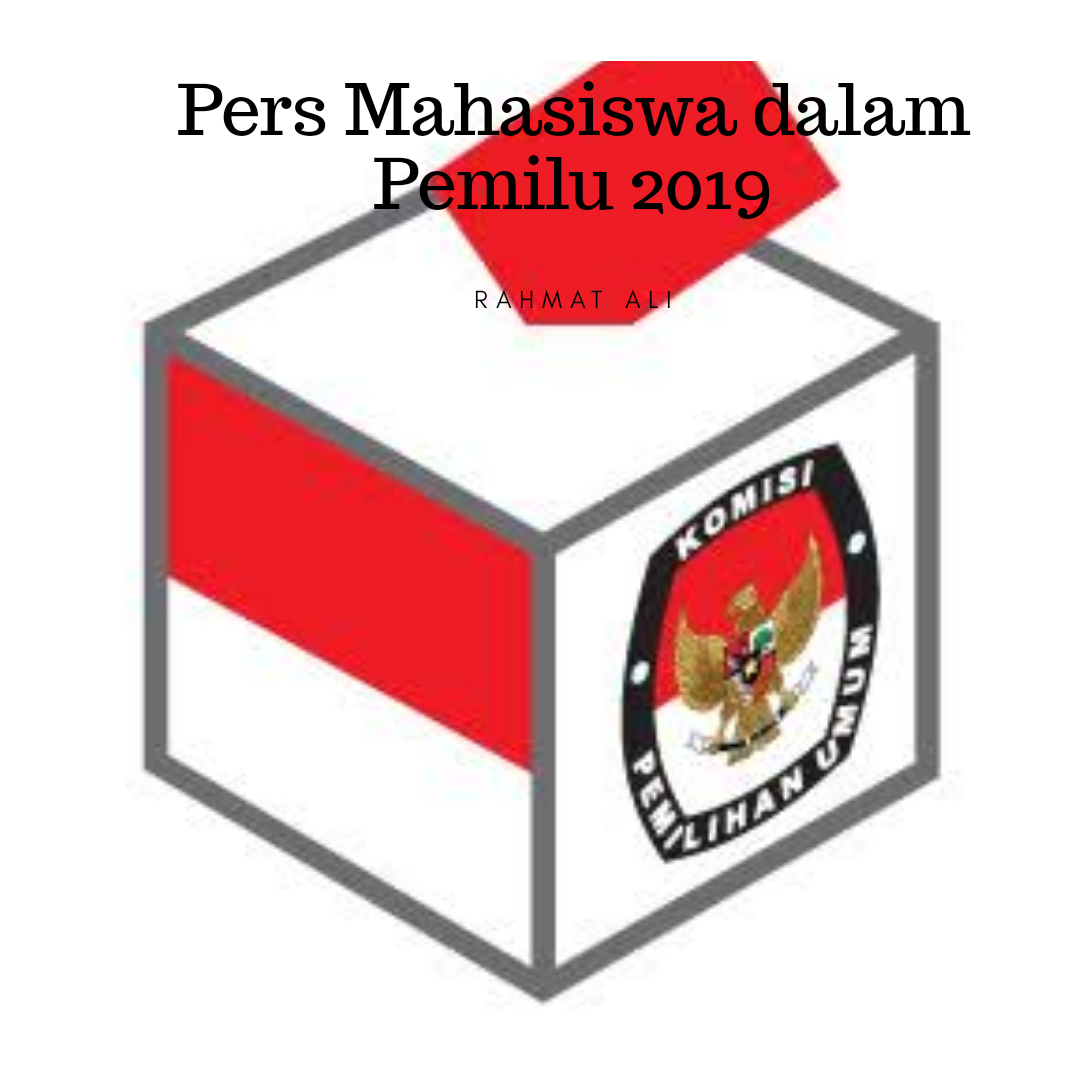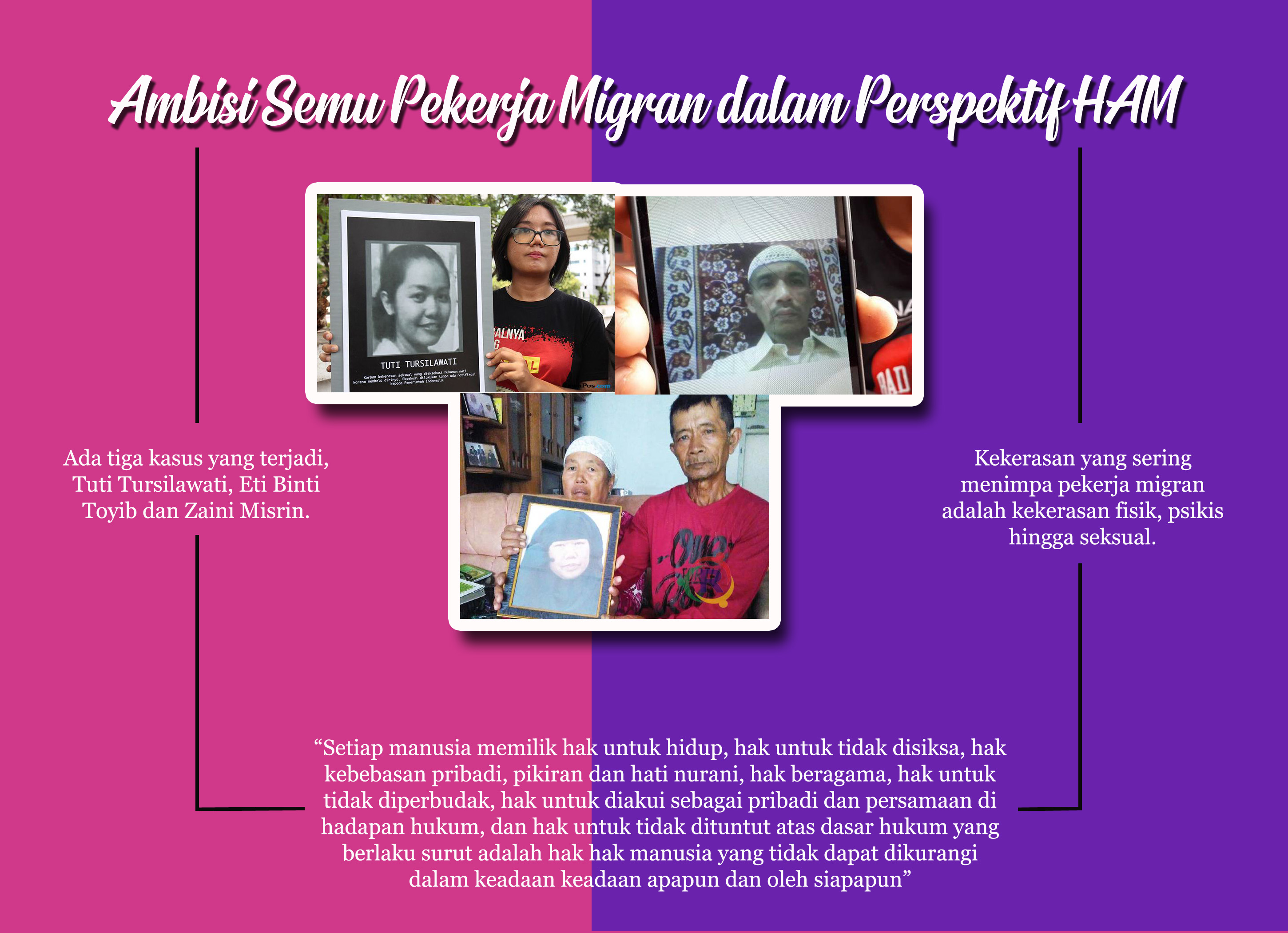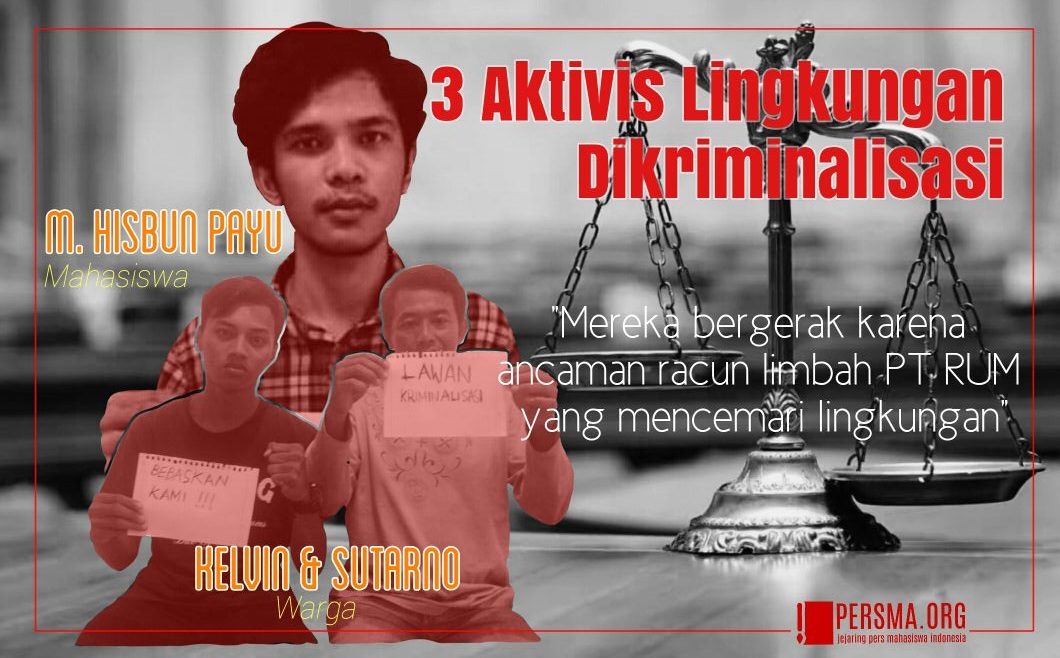Terkait pemecatan seluruh anggota Pers Mahasiswa Suara USU oleh Runtung Sitepu selaku Rektok Universitas Sumatera Utara (USU), saya menilai bahwa itu adalah tindakan yang tergesa-gesa. Mengapa demikian? Saya akan coba menelaah kasus pemecatan karena Cerita Pendek (Cerpen) yang dianggap memuat unsur pornografi dan mendukung LGBT ini dari sudut pandang peraturan-peraturan yang berlaku di USU.
Akan tetapi sebelum ke pembahasan peraturan-peraturan, saya akan memberikan tanggapan dulu terkait penilaian Rektor terhadap cerpen berjudul “Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya” itu. Kita perlu mengacu pada Surat Keputusan (SK) Rektor USU nomor 1319/UN5.1.R/SK/KMS/2019 tentang Perubahan Pertama SK Rektor No.1026/UN5.1.R/SK/KMS/2019 Tanggal 19 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Sumatera Utara Tahun 2019. Kita bahas satu persatu.
Bagian menimbang di poin a menjelaskan, “bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap berita, cerita dan konten yang dimuat dan diumumkan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pers Suara USU dan atau media elektronik ternyata ditemukan cerita atau konten yang mengantung unsur-unsur pornografi. Di mana hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai: Bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa dalam Bingkai Kebhinekaan; inovatif yang berintegritas, Tangguh dan arif (BINTANG) yang merupakan tata nilai USU yang tertuang dalam Renstra USU 2014-2019”.
Nah, yang perlu kita cermati adalah kata “pornografi”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi. Pornografi juga bisa diartikan sebagai bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks. Namun dalam SK tersebut, kata-kata yang memuat unsur “pornografi” tidak disebutkan di bagian mana.
Dalam SK tersebut juga tidak ada kajian akademik yang menjadi dasar untuk menilai bahwa Cerpen tiu memuat unsur pornografi. Mengapa kajian akademik? Karena itu adalah ukuran minimal untuk memberikan penilaian. Dalam konteks cerpen, harusnya ada kajian akademik sesuai rumpun keilmuannya seperti analisis sastra misalnya.
Kemudian bagian menimbang poin b yang menjelaskan, “bahwa atas pengumuman publikasi cerita dan konten oleh UKM Pers Suara USU, telah menimbulkan protes keras dari Sivitas Akademika USU dan Alumni USU, serta dari masyarakat”. Nah, dalam SK itu juga tidak disebutkan siapa saja yang protes? Dalam bentuk apa protes itu? Dan seperti apa protesnya? Hal ini penting untuk menelaah lagi kebenaran dari poin b ini, karena dalam peraturan pemberian sanksi ada tahap-tahap yang harus dilalui. Hal tersebut akan dibahas nanti.
Lalu bagian menimbang poin c yang menjelaskan, “bahwa setelah dilakukan pertemuan dengan para mahasiswa personal UKM pers Suara USU pada hari Senin, 25 Maret 2019 dengan pimpinan USU ternyata para mahasiswa yang merupakan personal UKM pers Suara USU tetap bersikukuh bahwa cerita tersebut pada huruf a, hanya merupakan karya sastra biasa dan tidak mengakui kekeliruannya”. Poin ini juga tidak menyebutkan apa argumentasi Suara USU terkait hal penilaian tersebut. Sehingga pemahaman yang muncul adalah Suara USU ini keras kepala saja.
Dari ketiga dasar pertimbangan SK tersebut, saya menarik satu kesimpulan bahwa dasar pemecatan seluruh anggota Suara USU masih bisa diperdebatkan. Tentu juga dicabut jika SK itu benar-benar tidak memiliki dasar yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti yang saya katakan di awal bahwa pemecatan ini adalah tindakan yang tergesa-gesa. Hal ini dikarenakan kurangnya kajian akademik, bukti protes keras dan argumentasi dari Suara USU. Kemudian, pemecatan seluruh anggota Suara USU bukanlah solusi yang akademis.
Seharusnya, ketika ada permasalahan di kampus penyelesaiannya juga dengan cara-cara yang berlaku di kampus. Ketika ada masyarakat yang protes terhadap konten cerpen Suara USU seharusnya Rektor menemukan pihak Suara USU dengan pihak masyarakat yang protes. Sehingga permasalahan bisa selesai dengan cara musyawarah mufakat.
Memang pihak Rektor sudah melakukan pertemuan dengan Suara USU, tapi benarkah itu sebuah pertemuan adil? Kita bisa tanyakan hal ini kepada Suara USU. Saya sudah menanyakannya kepada Yael Stefany selaku Pemimpin Umum Suara USU sekaligus penulis cerpen yang dipermasalahkan. Ia mengatakan kalau dalam rapat itu, yang berbicara hanya Rektor. LPM Suara USU tidak diberi kesempatan untuk berpendapat, sehingga Suara USU tidak memiliki kesempatan untuk mempertanggungjawabkan cerpennya.
Membaca Peraturan-Peraturan yang Berlaku
Maka dari itu, saya kira perlu untuk merenungkan lagi SK Rektor kemudian melakukan peninjauan ulang terhadap SK tersebut. Kita juga perlu mengacu pada beberapa peraturan yang berlaku di USU. Ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ada juga Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Sumatera Utara dan Keputusan Rektor USU no. 1177/H5.1.R/SK/KMS/2008 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Kita telaah satu persatu lagi.
Cerpen dalam konteks ini adalah bentuk kebebasan berekspresi. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikirandengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu cerpen merupakan salah satu bentuk kebebasan akademik. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 9 ayat 1 yang menjelaskan bahwa kebebasan akademik merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
Begitu juga dengan peraturan yang ada di USU sendiri Dalam Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara pasal 15 ayat 1 yang menyatakan, sivitas akademika USU memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Serta pasal 16 ayat 1 yang menyatakan, kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara mandiri dan bertanggungjawab melalu pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di USU.
Kemudian, kita perlu melihat lebih detail pada Keputusan Rektor USU no. 1177/H5.1.R/SK/KMS/2008 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Hal ini penting, supaya kita bisa mengetahui benarkah Rektor sudah bertindak sesuai aturan yang berlaku? Dalam BAB IV tentang Penegakan Pedoman Perilaku Pasal 14 ayat 4 tertulis:
Penegakan Pedoman Perilaku memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Terhadap tindakan yang melanggar Pedoman Perilaku dan Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik, penegakannya tunduk pada ketentuan Peraturan Akademik;
- Terhadap tindakan pelanggaran Pedoman Perilaku yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa peneguran, atau tidak diijinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/ petugas laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran;
- Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Pedoman Perilaku;
- Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
- Pemeriksaan terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administratif, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Pedoman Perilaku;
- Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Pedoman Perilaku.
Kalau kita melihat khususnya pada poin 2 dan 3, benarkah rector sudah bertindak sesuai aturan yang berlaku? Sedangkan kalau kita lihat kronologinya, Suara USU pernah dimatikan websitenya dan tidak diberi akses liputan.
Selain itu, kita perlu mencermati Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Sumatera Utara BAB IV Penegakan Pedoman Perilaku pasal 16 tentang pemeriksaan yang menjelasakan:
- Komisi Disiplin dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Pedoman Perilaku.
- Komisi Disiplin memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku.
- Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang tidak menggangu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan.
- Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
- Komisi Disiplin wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan Akademik.
Kita bisa mempertanyakan lagi, apakah Rektor sudah bertindak sesuai aturan yang berlaku? Pertanyaan itu bisa kita tanyakan sekarang atau ketika di forum pengkajian ulang nanti. Nah, terkait kajian ulang, sebenarnya juga diatur dalam Pedoman Perilaku Mahasiswa USU lho. Kita lihat pasal 18 tentang keberatan mahasiswa, tertulis jelas:
- Mahasiswa yang keberatan terhadap sanksi yang diberikan dosen dalam ruangan perkuliahan/laboratorium sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan diatas dapat mengajukan keberatan kepada Dekan Fakultas didampingi oleh Pembimbing Akademik.
- Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan Dekan Fakultas terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku dapat mengajukan keberatan kepada Rektor Universitas.
Nah, sudah jelas kan? Semua bisa dikaji ulang dan itu adalah hak setiap mahasiswa. Maka dari itu, kita perlu banyak membaca. Semua data-data terkait peraturan itu bisa diakses di internet. Silahkan baca, mari berdiskusi dan membalas tulisan ini dengan tulisan.