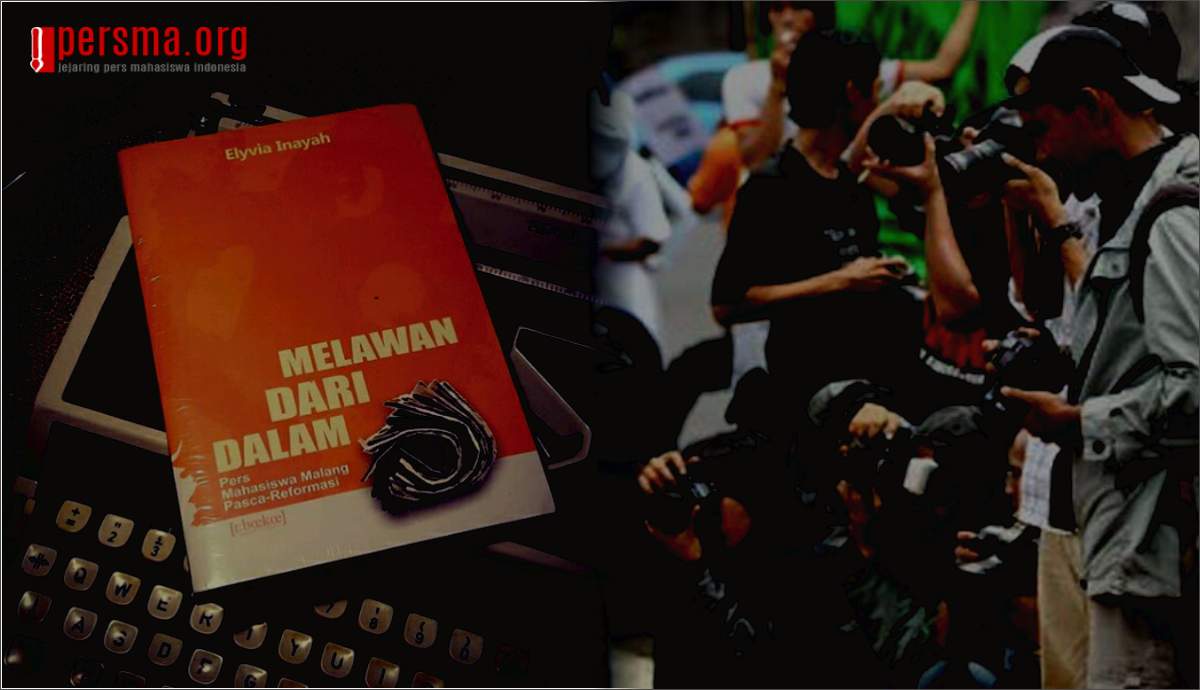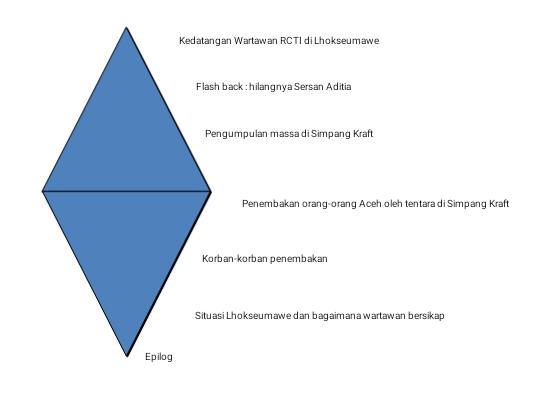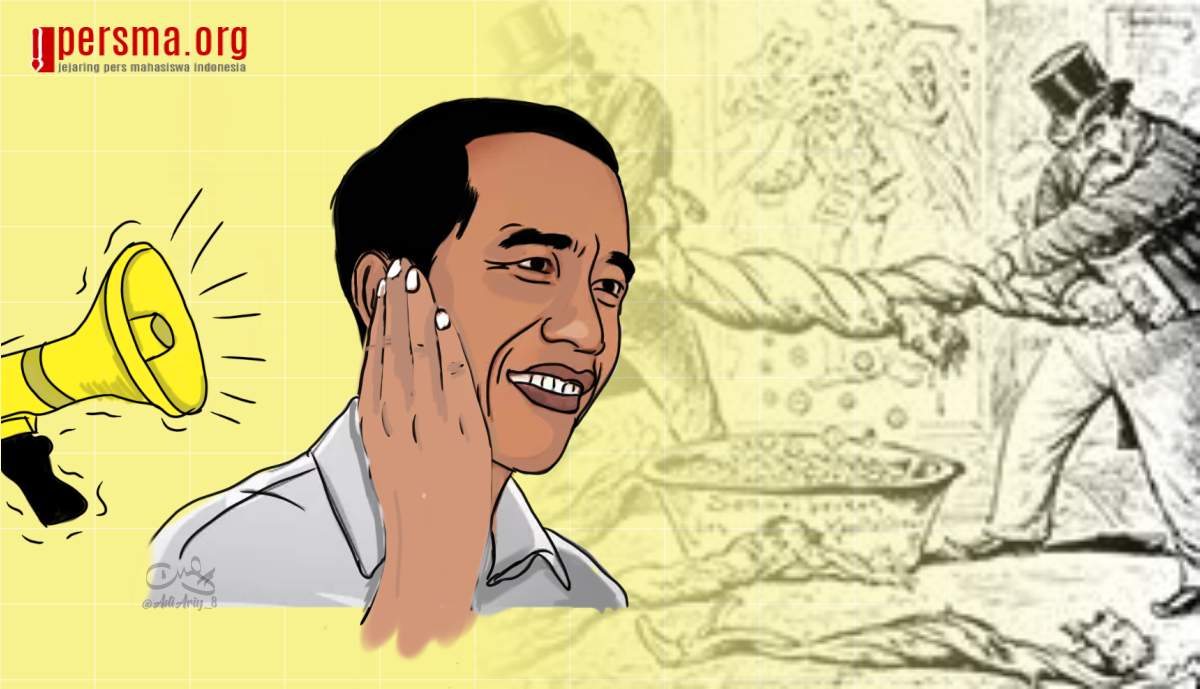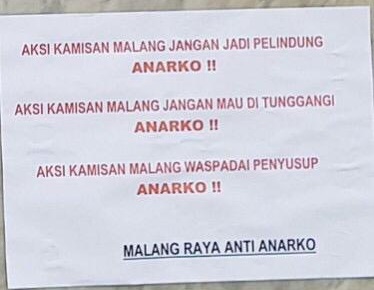Pandemi Covid-19 menjadi cerita muram bagi masyarakat, situasi menjadi semakin kalut, karena mengakibatkan krisis di banyak sektor. Para buruh banyak mengalami nasib buruk, banyak di antara mereka mengalami pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan. Dilansir dari Tempo.com, pemerintah menyebutkan bahwa angka pemutusan hubungan kerja dampak dari Covid-19 telah mencapai 3,05 juta. Di sini dapat kita ketahui, nasib buruh sedang dipertaruhkan dan keberlangsungan hidup mereka terancam.
Instruksi pemerintah agar para mahasiswa belajar dari rumah selama masa pandemi pun menunjukkan dampak negatif. Banyak mahasiswa yang stres karena tidak nyaman dengan sistem belajar daring. Sejak pandemi berlangsung sampai sekarang, pemerintah terlihat tidak peduli dengan dunia pendidikan. Mahasiswa diperintah untuk belajar dari rumah, tapi pemerintah tidak peka dengan biaya kuota yang dikeluarkan oleh mahasiswa, sedangkan tidak semua mahasiswa memiliki kemudahan akses internet. Lebih-lebih mahasiswa juga tetap dituntut untuk membayar biaya kuliah.
Dari sini sangat terlihat pemerintah dan kampus tidak mau tahu akan situasi dan kondisi mahasiswa di tengah pandemi. Situasi pandemi ini juga berdampak pada kehidupan mahasiswa maupun keluarganya. Terlebih sebagian besar mahasiswa berasal dari kalangan menengah ke bawah, berasal dari kalangan buruh, yang saat ini nasibnya tidak tentu. Boro-boro untuk membayar biaya pendidikan, biaya makan sehari-hari saja susah. Padahal perihal pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk bisa bertahan hidup.
Di tengah krisis akibat pandemi, hingga saat ini masih belum ada suatu kebijakan yang memihak kepada para pelajar atau mahasiswa. Saya merasa pada tahun ini banyak mahasiswa yang putus kuliah, karena tidak mampu membayar biaya kuliah. Selain itu siswa sekolah menengah atas pun tak banyak yang bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. mengapa demikian?
Pengelolaan Pendidikan yang Ruwet
Masih banyak terdapat tindakan diskriminatif terhadap para pelajar atau mahasiswa yang bisa dibilang berasal dari kelas sosial rendah atau kurang mampu. Padahal sudah jelas tertuang dalam pasal 31 UUD 1945: “(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Maka, berdasarkan pasal 31 ini, negara memiliki dua kewajiban terhadap dunia pendidikan, yaitu: menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara, dan membiayai pendidikan bagi peserta didik. Selain itu dalam salah satu butir pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Lalu bagaimana jika butir ini belum terpenuhi? Sudah jelas akan pincang.
Masalah pendidikan yang terus menghantui negara dan masih belum bisa teratasi secara maksimal, ditambah dengan kondisi sosial yang carut marut akibat pandemi Covid-19. Penerapan sistem pendidikan yang masih jauh di luar ekspektasi, terlebih oleh masyarakat kelas bawah, seakan masih menjadi hantu yang menakutkan. Bagaimana tidak, hanya masyarakat kelas menengah ke atas sajalah yang masih tergolong mudah memperoleh akses pendidikan. Problem utamanya adalah biaya. Ya, biaya pendidikan di negara ini masih tergolong sangat tinggi, sulit dijangkau.
Hal tersebutlah yang menyebabkan tidak semua orang dapat menikmati bangku perkuliahan apalagi di situasi pandemi seperti ini. Diperjelas lagi dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yang bila disimpulkan bunyinya adalah: “setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, memperoleh pendidikan layanan khusus, dan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.” Apakah teks undang-undang tersebut benar-benar diterapkan? Tentulah tidak.
Dunia pendidikan seakan menjadi ajang untuk komersialisasi atau meraup keuntungan sebesar-besarnya. Institusi pendidikan yang dilepaskan negara berubah menjadi perusahaan jasa pendidikan. Meskipun kita selama ini berdalih jika komersialisasi pendidikan harus dihapuskan, tetapi hal itu belumlah terlaksana.
Hal itulah di antara sebab mahasiswa menjadi lebih kritis dan lebih berkesadaran progresif di tengah pandemi seperti ini. Karena mereka merasakan hidup di situasi krisis tetapi tetap dituntut untuk membayar biaya kuliah. Hampir merata mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia menuntut adanya biaya kuliah gratis, penurunan biaya kuliah dan menolak adanya privatisasi pendidikan. Mereka melakukan aksi langsung, membentangkan poster, dan meramaikan banyak tuntutan di media sosial. Mereka memasang tagar #gratiskanukt #sudahkrisiswaktunyauktgratis #nadimkemanamahasiswamerana #janganbayarukt #turunkanukt dan masih banyak lagi. Munculnya tersebut menunjukkan hari ini dunia pendidikan sedang tidak baik-baik saja, terlebih pada kehidupan mahasiswa.
Menanggapi banyaknya tuntutan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi dan ramainya tuntutan di sosial media, pemerintah melalui Kemendikbud dalam surat yang dikeluarkan pada 3 Juni 2020, menyatakan tidak ada kenaikan UKT di masa pandemi. Para rektor perguruan tinggi negeri juga menyepakati ada penundaan pembayaran dan pembayaran bisa dicicil. Selanjutnya pemerintah memfasilitasi Kartu Indonesia Pintar dengan jumlah yang tidak seimbang dengan jumlah mahasiswa yang ada di Indonesia. Ditambah prosedur kepengurusannya yang ruwet, banyak syarat dan ketentuan, informasinya pun terbatas. Hal ini menjelaskan pemerintahan tidak bisa menjawab keresahan mahasiswa, terlebih di situasi seperti ini, perekonomian tidak bisa serta merta dipulihkan seperti sebelum terjadi pandemi.
Universitas Nasional dan Represi Membabi Buta
Diantara masifnya gerakan mahasiswa untuk minta keringanan biaya uang kuliah, hati saya condong dengan gerakan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan Aliansi Mahasiswa UNAS Gawat Darurat (UGD) di Universitas Nasional, Jakarta. Gerakan ini bertahan dan tumbuh semakin masif, terlebih mereka menerima banyak represi dari birokrasi, mulai dari baku hantam, penabrakan dengan mobil, ditangkap dan dilaporkan ke Polsek Pasar Minggu, hingga diancam dilaporkan UU ITE.
Gerakan ini memiliki beberapa tuntutan:
- Menuntut pihak birokrasi memberi keringanan mahasiswa dengan potongan 50 sampai 65 persen, karena kampus hanya memberi keringanan biaya 100 ribu dan 150 ribu dengan syarat dan ketentuan berlaku;
- Menuntut kampus untuk tidak hanya memberikan kuota gratis sebesar 30 GB untuk mahasiswa pengguna Telkomsel dan Indosat saja untuk membuka Web resmi UNAS, sebab tidak semua mahasiswa UNAS menggunakan Telkomsel dan Indosat, sedangkan para dosen dalam pemberian materi perkuliahan menggunakan aplikasi diluar web resmi UNAS;
- Mereka menuntut agar para dosen dan pekerja kampus mendapatkan upah layak di masa pandemi;
- Menuntut rektor untuk audiensi terbuka;
- Menuntut adanya transparansi dan terbukanya statuta kampus agar bisa dikritisi bersama;
- Menuntut diberhentikanya kriminalisasi dan intimidasi terhadap mahasiswa.
Gerakan UGD telah menggelar berbagai diskusi online, mengumpulkan berbagai data dari penelitian yang dilakukan terkait pendapatan UNAS dari pembayaran mahasiswa per-semester, pembayaran upah dosen, hingga pemotongan biaya yang tidak layak bahkan dirasa menghina para mahasiswa.
Melalui hasil investigasi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa UGD, terdapat 12.367 mahasiswa aktif di tingkatan D3–S1 di UNAS. UGD juga telah mengaudit pendapatan UNAS dari pembayaran biaya pendidikan mahasiswa sebanyak 6.672 (54%) yang dihitung dengan detail per-angkatan dari setiap fakultas/jurusan. Rp 49.401.600.000 adalah hasil keuntungan UNAS dari mahasiswa yang didapat secara terbatas oleh kawan-kawan UGD. 5.695 (46%) data mahasiswa UNAS yang belum mampu ter-update secara detail per angkatannya untuk mengetahui hasil pendapatannya. Fakultas/jurusan per-angkatan yang belum mampu terakses yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Bahasa, Abanas dan FTKI merupakan daftaran yang belum mampu diakses kawan-kawan karena terbatasnya akses data yang dihambat UNAS.
UNAS hanya mengeluarkan Rp. 1.114.200.000/semester untuk mengupah pekerjanya yang terdiri dari 94 office boy, security dan cleaning service. Upah pekerja hanya dikisar pada 2,4% dari pendapatan yang diaudit secara terbatas. Namun sekali lagi, hasil investigasi yang didapat untuk data pekerja tidak mendapatkan akses untuk data office boy di kampus utama. Pekerja parkir di UNAS sebanyak 6 orang pekerja dirumahkan tanpa diupah. Data yang belum mampu menyeluruh didapatkan sebagai kebutuhan audit keseluruhan. Tentunya dihambat oleh UNAS melalui karakter-karakter yang anti demokratis. Upaya audit yang dilakukan memiliki tujuan untuk membuka transparansi keuangan UNAS di masa pandemi. UNAS hanya menerapkan potongan Rp 100.000 dengan jumlah pengeluaran Rp 1.236.700.000 yang didapat dari total mahasiswa 12.367. Ternyata pengeluaran UNAS untuk potongan Rp 100.000 hanya 2,5% dari audit pendapatan mahasiswa UNAS sebanyak 7.248.
Merespon hasil audit tersebut, Aliansi Mahasiswa UGD menggelar aksi damai di depan kampus pada Rabu (10/6), dengan mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak dan menggunakan masker, kemudian aksi tersebut dibubarkan dengan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh kurang lebih 32 aparat keamanan yang dikerahkan oleh kampus. Satu orang Babinsa dan beberapa orang lainnya tidak berseragam juga turut serta. Mereka memukul muka beberapa massa aksi, melakukan tendangan ke perut dan kepala, pendorongan hingga jatuh, pengeroyokan, perampasan dokumentasi serta penangkapan salah satu anggota pers mahasiswa yang bernama Togi dari Universitas Bunda Mulia (UBM). Kemudian Togi dibawa ke Polsek Pasar Minggu atas laporan UNAS, yang pada akhirnya dia dibebaskan. Pada hari itu juga terdapat pemanggilan terhadap 29 mahasiswa oleh Komisi Disiplin UNAS, atas ujaran di sosial media tentang menyampaikan aspirasi di masa pandemi, dengan tagar #unasgawatdarurat. Mahasiswa yang menghadap diminta melakukan pengakuan dalam surat pernyataan bersalah. Berdasarkan dengan keterangan mahasiswa yang menandatangi pernyataan bersalah dari kampus, mereka diancam jeratan pidana UU ITE.
Kamis (11/6), Aliansi Mahasiswa UGD kembali melakukan aksi solidaritas untuk mengawal 27 kawan yang dipanggil oleh komisi disiplin UNAS dan menagih janji audiensi terbuka UNAS. Pada hari itu, birokrasi UNAS menyewa preman dan melakukan penabrakan terhadap massa aksi dengan mobil saat pulang.
Aliansi Mahasiswa UGD tetap menagih janji untuk audiensi terbuka dengan pihak birokrasi kampus padaJumat (12/6). Alih-alih akan menemui massa aksi, semua massa aksi malah akan diancam dengan UU ITE.
Sabtu (13/6), LPM Progres meliput aksi-aksi UGD dan memuat dua berita di laman online LPM Progres, dengan judul “Tuntutan Belum Dipenuhi Aliansi Mahasiswa Unas Gawat Darurat kembali Aksi” dan “Aksi Penyampaian Aspirasi di Unas Berujung Tindakan Represif dan Intimidasi”. Pihak LPM Progres lalu mendapat telepon dari Humas UNAS untuk menurunkan berita, LPM Progres dianggap tidak mempunyai kewenangan untuk meliput kejadian di UNAS, karena LPM Progres dianggap dari UNINDRA, Universitas yang berbeda. Padahal kedudukan pers mahasiswa seperti halnya pers lainnya, yang bisa meliput semua kejadian, baik yang ada di kampus maupun di luar kampus, sebagai bentuk kepedulian sosial.
Dalam waktu sehari, LPM Progres diminta untuk menurunkan berita. Jika tidak, LPM Progres diancam jerat pidana UU ITE Pasal 28 ayat 2 yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan.”
Ancaman pidana dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016, yakni: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”
Selanjutnya, Senin (15/6), berdasarkan laporan dari Instagram @unasgawatdarurat, UNAS memasukkan sekitar 50 polisi ke dalam kampus, padahal kita ketahui dari beberapa keterangan di atas, yang melakukan represi dan membuat keadaan ricuh adalah pihak UNAS, gerakan Aliansi Mahasiswa UNAS Gawat Darurat hanya menyampaikan keresahan hatinya.
Saya merasa, pihak birokrasi Universitas Nasional ketakutan dan panik akan adanya tuntutan Aliansi Mahasiswa UGD dan adanya beberapa pemberitaan beredar yang diliput oleh kawan-kawan LPM Progres. Sehingga pihak birokrasi UNAS melakukan represi yang membabi buta, sangat ngawur dan tidak patut untuk dibenarkan. Mereka sudah mencederai hak asasi manusia. Padahal semua manusia berhak menyampaikan pendapat dan mendapat keamanan dalam menyampaikan. Oleh karena itu di situasi seperti ini terlampau rumit untuk dihadapi dan diselesaikan oleh segelintir orang. Kita perlu kerjasama, kerjarasa, berdiskusi, berdebat, berdialektika, musyawarah, melakukan aksi dan menjadikan ini sebagai keresahan bersama. Untuk itu mari bersolidaritas dan saling menguatkan.